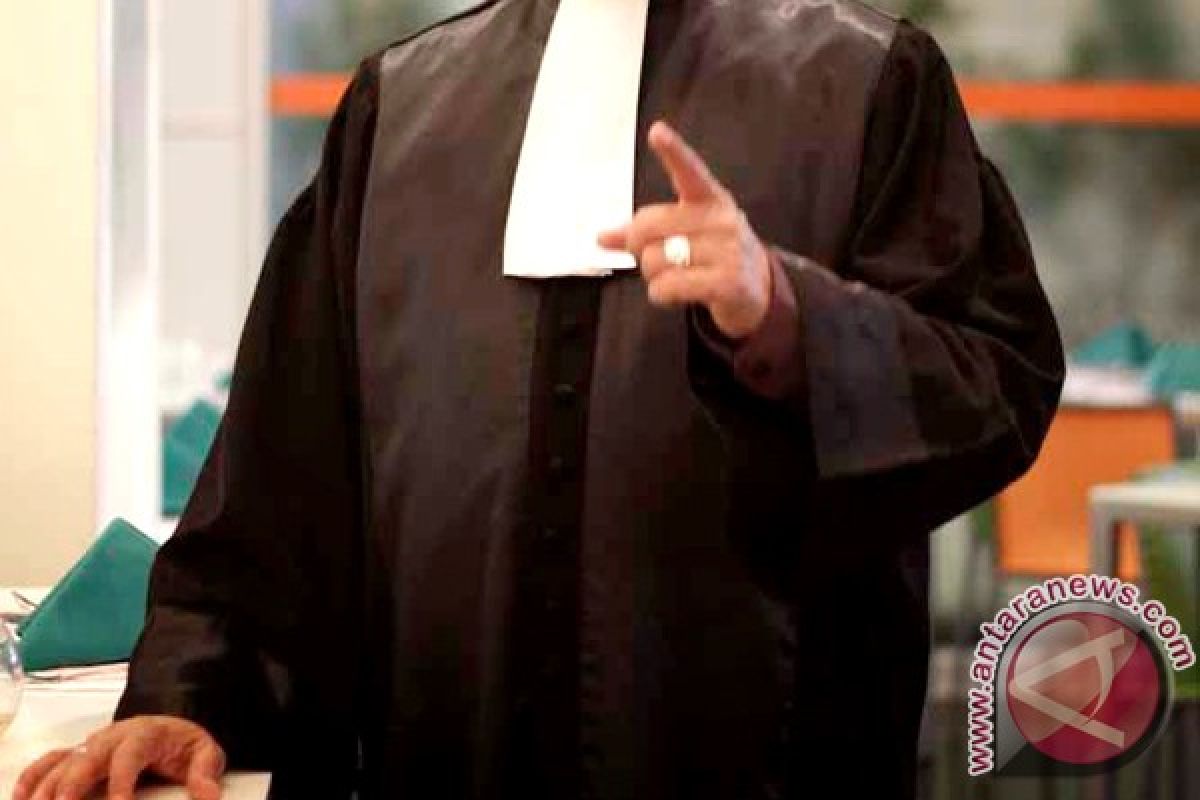Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memproyeksikan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia akan sedikit melemah pada tahun 2025, meskipun nilai penerimaan pajak secara nominal diperkirakan terus meningkat.
Kondisi ini menggambarkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang membaik dan upaya memperkuat penerimaan negara.
Saat rapat kerja bersama Komisi XI pada 3 Juli 2025 lalu, Kementerian Keuangan memperkirakan rasio perpajakan atau tax ratio pada tahun 2025 hanya akan mencapai 10,03 persen atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tax ratio pada tahun 2024 yang sebesar 10,08 persen.
Berdasarkan data, capaian tax ratio Indonesia telah mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023 turun menjadi 10,31 persen dari capaian 10,38 persen, pada tahun 2022, dan kemudian menyusut lagi ke 10,08 persen di tahun 2024. Untuk tahun 2025 juga diprediksi tax ratio akan mengalami penurunan dengan outlook diperkirakan hanya mencapai 10,03 persen.
Penurunan tax ratio Indonesia menjadi 10,03 persen dalam proyeksi tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran tersendiri di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.
Tax ratio, yang mencerminkan perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan indikator utama kapasitas fiskal sebuah negara. Jika tren penurunan ini tidak segera direspons dengan strategi yang tepat, maka potensi penerimaan negara akan semakin terbatas, padahal kebutuhan belanja terus meningkat.
Tantangan struktural
Tax ratio yang rendah bukan hanya persoalan angka, melainkan cerminan dari tantangan struktural dalam perekonomian Indonesia. Dominasi sektor informal, keterbatasan kepatuhan pajak, pemberian insentif fiskal yang berlebihan, serta inefisiensi administrasi perpajakan menjadi faktor utama penyebab stagnasi penerimaan.
Padahal, belanja negara terus meningkat, baik untuk subsidi energi, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, maupun untuk mendanai reformasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih digerakkan oleh UMKM dan sektor informal menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar pelaku usaha belum terintegrasi ke dalam sistem perpajakan secara formal.
Upaya digitalisasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang menjanjikan potensi integrasi yang lebih luas. Namun demikian, untuk memastikan keberhasilan transformasi tersebut, dibutuhkan ekosistem pendukung seperti penyederhanaan administrasi, peningkatan literasi perpajakan, dan insentif yang memudahkan pelaku usaha bertransisi ke sektor formal.
Di sisi lain, pemberian berbagai insentif fiskal untuk mendorong investasi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 memang membawa dampak positif dalam mendorong aktivitas ekonomi, namun juga memunculkan tantangan baru terhadap basis perpajakan.
Beberapa skema seperti tax holiday dan tax allowance dalam jangka pendek memang menurunkan potensi penerimaan negara. Oleh karena itu, evaluasi yang menyeluruh atas efektivitas dan efisiensi insentif pajak mutlak dilakukan agar pemerintah tetap memiliki ruang fiskal yang sehat tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan efisiensi.
Praktik penghindaran pajak lintas negara melalui skema transfer pricing dan under-invoicing juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, kerja sama internasional seperti implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) dan partisipasi aktif Indonesia dalam kerangka Inclusive Framework OECD-G20 menjadi langkah penting.
Selain itu, pemerintah juga harus segera merespons perkembangan global dengan menerapkan ketentuan global minimum tax agar potensi penerimaan dari perusahaan multinasional dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan persaingan tarif yang tidak sehat
Optimalisasi penerimaan
Transformasi sistem administrasi perpajakan merupakan pilar penting dalam agenda optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan saat ini. Implementasi Coretax Administration System dan penggunaan big data oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan langkah awal yang strategis.
Namun demikian, optimalisasi ini tidak akan efektif tanpa disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi proses pemeriksaan, dan penguatan teknologi keamanan data. Reformasi ini juga harus disertai dengan penguatan pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi analitik untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara lebih dini.
Di level domestik, harmonisasi kebijakan perpajakan antara pusat dan daerah menjadi isu yang semakin mendesak. Potensi penerimaan dari sektor daerah belum tergali optimal karena masih adanya fragmentasi regulasi dan sistem pemungutan yang tidak efisien.
Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), peluang integrasi dan sinergi antara pajak pusat dan daerah semakin terbuka. Digitalisasi pajak daerah dan insentif kinerja fiskal bagi pemerintah daerah bisa menjadi instrumen yang mendorong optimalisasi basis pajak lokal secara signifikan.
Pelajaran penting bisa diambil dari pengalaman beberapa negara seperti Jerman, Kanada, Afrika Selatan dan India. Beberapa hal yang bisa diterapkan di Indonesia antara lain: membangun sistem koordinasi berbasis data nasional antara DJP dan Bapenda melalui dashboard real-time, menyusun insentif fiskal berbasis kinerja daerah seperti matching fund untuk daerah yang meningkatkan basis pajak secara signifikan, serta membentuk forum koordinasi nasional perpajakan daerah, mirip dengan GST Council di India atau equalization system seperti Jerman.
Namun semua upaya ini hanya akan berhasil jika ditopang oleh kepercayaan publik. Kepatuhan pajak tidak hanya dibentuk oleh kewajiban hukum, melainkan juga oleh persepsi masyarakat terhadap penggunaan pajak.
Ketika masyarakat melihat bahwa pajak digunakan secara akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi mereka, maka kemauan untuk membayar akan tumbuh secara sukarela.
Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat komunikasi publik mengenai pemanfaatan anggaran, membangun mekanisme transparansi anggaran berbasis digital, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan belanja negara.
Hal penting bagi Indonesia adalah mengembangkan dashboard belanja negara berbasis digital, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi APBN/APBD, serta mendorong pemanfaatan teknologi pengawasan sosial oleh masyarakat sipil untuk melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian belanja.
Selanjutnya kondisi global juga harus diperhitungkan secara cermat. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta gangguan rantai pasok memberi tekanan tambahan terhadap potensi penerimaan pajak nasional.
Dalam situasi seperti ini, ketergantungan terhadap sumber penerimaan yang sempit menjadi risiko. Diversifikasi sumber penerimaan melalui pajak karbon, pajak atas kekayaan, serta optimalisasi aset negara harus segera dicanangkan.
Pajak karbon, khususnya, dapat menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan dan sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju ekonomi rendah emisi. Hal ini misalnya telah dipraktikkan di Swedia, Norwegia, Spanyol, dan Singapura.
Pengalaman dari negara-negara tersebut dapat mendorong adanya percepatan road map penerapan pajak karbon, mengkaji potensi pajak kekayaan progresif untuk kelompok ultra-kaya sebagai instrumen pemerataan, serta membangun sovereign wealth fund yang lebih transparan dan proaktif, untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari aset BUMN dan tanah negara.
Titik balik
Meskipun tax ratio dalam jangka pendek belum dapat menembus angka ideal, bukan berarti negara kehilangan daya untuk mendanai pembangunan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menyusun strategi fiskal yang lebih tajam dan efisien.
Fokus anggaran harus diarahkan pada program-program berdampak tinggi seperti perlindungan sosial yang produktif, pendidikan vokasi yang adaptif, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi. Setiap rupiah yang diterima harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi pertumbuhan dan pemerataan.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi antara instansi fiskal, sektor swasta, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu diperkuat agar upaya optimalisasi penerimaan pajak benar-benar terwujud.
Selain itu, penguatan tata kelola fiskal harus menjadi agenda utama agar ruang fiskal yang tersedia, meskipun terbatas, dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.
Akhirnya, tren penurunan tax ratio harus menjadi titik refleksi bagi semua pihak bahwa pengelolaan penerimaan negara tidak bisa dijalankan secara biasa-biasa saja. Diperlukan terobosan kebijakan, keberanian politik, serta kapasitas institusi yang tangguh untuk mengubah tantangan menjadi peluang.
Optimalisasi penerimaan pajak tidak berarti menambah beban rakyat, tetapi memastikan bahwa sistem perpajakan kita menjadi lebih adil, transparan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Kementerian Keuangan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.