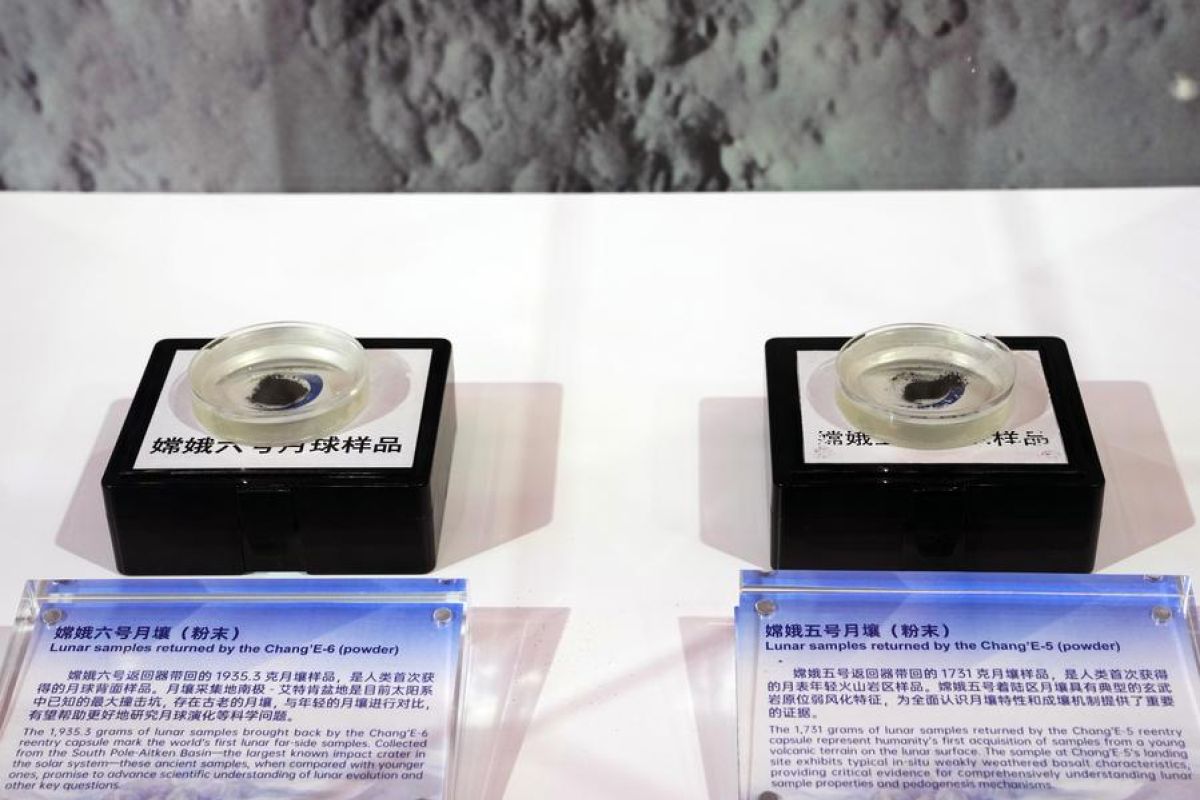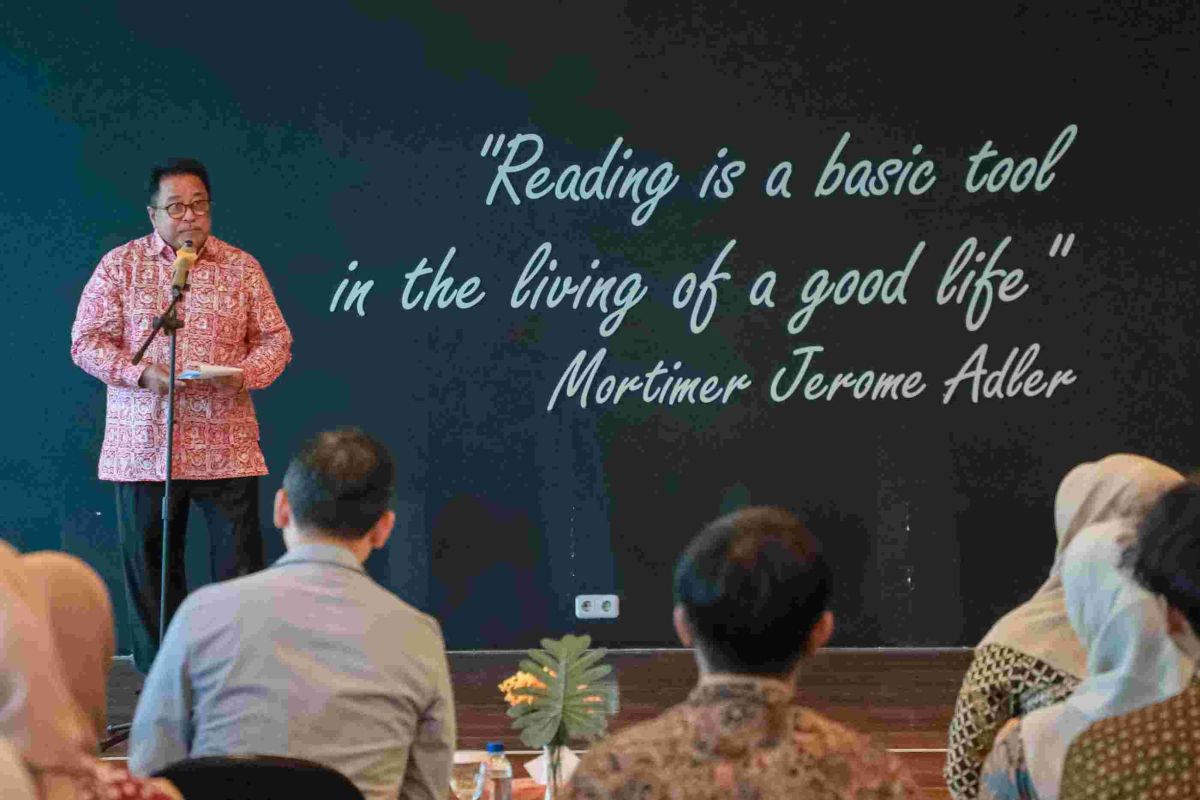Jakarta (ANTARA) - Kelapa sawit, di satu sisi adalah “emas hijau” yang menggerakkan ekonomi dan menghidupi jutaan rakyat Indonesia.
Namun, di panggung global, sawit kerap dicitrakan sebagai penjahat iklim, dituding biang deforestasi, perusak habitat, hingga penyumbang besar emisi karbon dunia. Narasi negatif ini begitu gencar, hingga tidak jarang kita sendiri ikut percaya bahwa sawit identik dengan kerusakan lingkungan.
Padahal, fakta terbaru dari International Energy Agency (IEA) dan World Resources Institute (WRI) menunjukkan gambaran berbeda, dimana penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca global bukanlah sawit, melainkan energi fosil seperti pembangkit listrik, transportasi, dan industri, yang mencapai hampir tiga perempat total emisi. Sementara itu, deforestasi dan alih guna lahan hanya menyumbang seperlima.
Temuan ini penting bagi Indonesia dan ASEAN untuk menata ulang narasi sawit di forum internasional, sebab selama ini sawit kerap dijadikan kambing hitam, sementara minyak nabati lain yang justru jauh lebih boros lahan luput dari sorotan.
Sawit adalah realitas ekonomi bagi Indonesia sekaligus peluang energi terbarukan yang bila dikelola berkelanjutan, dapat berperan penting dalam mitigasi iklim. Karena itu, Indonesia perlu lebih percaya diri menghadapi sorotan dunia, sambil terus memperbaiki tata kelola.
Menyibak kabut narasi
Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati paling efisien di dunia. Produktivitasnya mencapai 8–10 kali lipat per hektare dibanding minyak nabati lain. Untuk menghasilkan 1 ton minyak, sawit hanya membutuhkan sekitar 0,3 hektare lahan, jauh lebih sedikit dibanding bunga matahari (1,3 ha), rapeseed (1,4 ha), atau kedelai (2,1 ha).
Artinya, mengganti sawit dengan minyak nabati lain justru akan menuntut lahan yang jauh lebih luas, yang berpotensi memicu deforestasi lebih besar. Fakta ini sering luput dalam perdebatan publik, padahal sangat penting untuk memberi perspektif yang lebih adil terhadap sawit.
Salah satu mitos terbesar yang beredar adalah anggapan bahwa sawit merupakan penyumbang utama pemanasan global. Berbagai laporan aktivis lingkungan kerap menyoroti deforestasi akibat ekspansi kebun sawit, terutama di Asia Tenggara, seolah-olah inilah faktor dominan krisis iklim.
Padahal, jika ditelusuri dengan data, kontribusi emisi dari seluruh sektor perkebunan (termasuk sawit) sangat kecil dibandingkan sektor energi berbasis fosil. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam tetap menjadi kontributor utama pemanasan global, yang menyumbang lebih dari dua pertiga total emisi, sementara deforestasi dan alih guna lahan berada di kisaran belasan persen.
Sayangnya, sisi positif sawit jarang mendapat sorotan sebesar isu deforestasi. Padahal, sawit tidak hanya efisien sebagai penghasil minyak nabati, tetapi juga berpotensi besar sebagai sumber energi terbarukan.
Program biodiesel berbasis sawit di Indonesia, misalnya, mampu mengurangi impor solar sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Implementasi mandatori biodiesel B30 hingga B35 diproyeksikan dapat menurunkan emisi sekitar 34,9 juta ton CO₂ per tahun, sembari menghemat devisa miliaran dolar.
Fakta semacam ini menunjukkan bahwa sawit bukan hanya bagian dari persoalan, melainkan juga dapat menjadi bagian dari solusi.
Antara ekonomi dan lingkungan
Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, dengan lebih dari 16 juta hektare lahan ditanami sawit dan menghasilkan devisa ekspor sekitar 30 miliar dolar AS per tahun. Industri sawit telah menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan, dimana lebih dari 16 juta orang menggantungkan hidup secara langsung maupun tidak langsung dari sektor ini, mulai dari petani kecil, pekerja perkebunan, hingga buruh pabrik dan sektor hilir.
Namun, di balik kontribusi ekonominya, industri sawit tak pernah sepi dari tekanan global. Narasi yang menuding sawit sebagai penyebab utama emisi sering dijadikan alasan untuk kebijakan diskriminatif terhadap produk Indonesia.
Uni Eropa, misalnya, memberlakukan EU Deforestation Regulation (EUDR) yang melarang impor komoditas terkait deforestasi, serta Renewable Energy Directive (RED II) yang membatasi penggunaan sawit dalam biofuel dengan alasan risiko Indirect Land Use Change (ILUC).
Langkah-langkah ini dipandang Indonesia dan Malaysia sebagai bentuk proteksionisme terselubung. Tak heran, kedua negara ini, yang memasok sekitar 85 persen produksi sawit dunia, sempat mengajukan gugatan ke WTO untuk menentang regulasi yang dianggap diskriminatif.
Di tingkat domestik, Indonesia telah menempuh berbagai langkah untuk memperkuat keberlanjutan sawit. Pemerintah menerapkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang wajib bagi perusahaan, memberlakukan moratorium izin baru sejak 2018, serta menggencarkan rehabilitasi lahan kritis dan restorasi gambut.
Data inventarisasi gas rumah kaca (GRK) nasional juga menegaskan bahwa sektor energi jauh lebih dominan menyumbang emisi dibanding sektor LULUCF. Sejak 2016, laju deforestasi Indonesia berhasil turun lebih dari 50 persen berkat kebijakan moratorium dan pengelolaan hutan yang lebih ketat.
Karena itu, target Net Zero Emission 2060 menempatkan dekarbonisasi energi, alih-alih sawit sebagai kunci utama. Dengan kata lain, tantangan emisi Indonesia lebih banyak terkait mengurangi ketergantungan pada batu bara dan BBM, sementara sawit justru berpotensi menjadi bagian dari solusi, terutama melalui pemanfaatannya sebagai biofuel.
Di bawah bayang-bayang narasi global
Indonesia tidak sendirian menghadapi stereotip negatif terhadap sawit. Malaysia, produsen terbesar kedua dunia, juga mengalami tekanan serupa. Negeri jiran ini bahkan telah mengembangkan standar Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) yang sejalan dengan ISPO sebagai bukti komitmen keberlanjutan.
Namun, kampanye hitam terhadap sawit Malaysia, dari isu lingkungan hingga tenaga kerja, tetap marak di media Barat. Thailand pun, meski volumenya lebih kecil, menjadikan sawit komoditas strategis untuk energi domestik melalui program biodiesel B20. Sementara itu, Filipina dan Myanmar melihat sawit sebagai peluang pembangunan pedesaan, sambil belajar dari pengalaman Indonesia-Malaysia.
Secara kolektif, ASEAN menyumbang lebih dari 85 persen produksi sawit dunia. Dominasi ini ironisnya justru membuat kawasan menjadi sasaran kebijakan protektif dari negara konsumen di Eropa dan Amerika.
Minyak nabati pesaing, seperti kedelai di Amerika, rapeseed di Eropa, dan bunga matahari di Ukraina, diuntungkan jika citra sawit memburuk. Di balik jargon “penyelamatan lingkungan”, terdapat indikasi perang dagang terselubung untuk merebut pangsa pasar minyak nabati global.
Menghadapi tekanan tersebut, negara-negara ASEAN mulai merapatkan barisan. Indonesia dan Malaysia membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) sebagai wadah diplomasi, melobi agar standardisasi yang fair dijadikan acuan global.
Keduanya juga pernah menggugat Uni Eropa ke WTO atas diskriminasi sawit dalam kebijakan biofuel. Diplomasi regional ini penting untuk mengoreksi narasi global yang timpang sekaligus memperkuat komitmen keberlanjutan.
Jalan ke depan adalah mengoreksi persepsi dunia dengan tiga strategi utama, yaitu diplomasi berbasis data, inovasi sawit rendah emisi melalui riset varietas unggul, praktik agroforestri, hingga pemanfaatan limbah menjadi energi, serta branding positif sawit berkelanjutan.
Dengan langkah konsisten ini, sawit dapat dipandang bukan sebagai masalah, melainkan bagian dari solusi energi terbarukan dan pembangunan inklusif.
*) Kuntoro Boga Andri adalah Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.