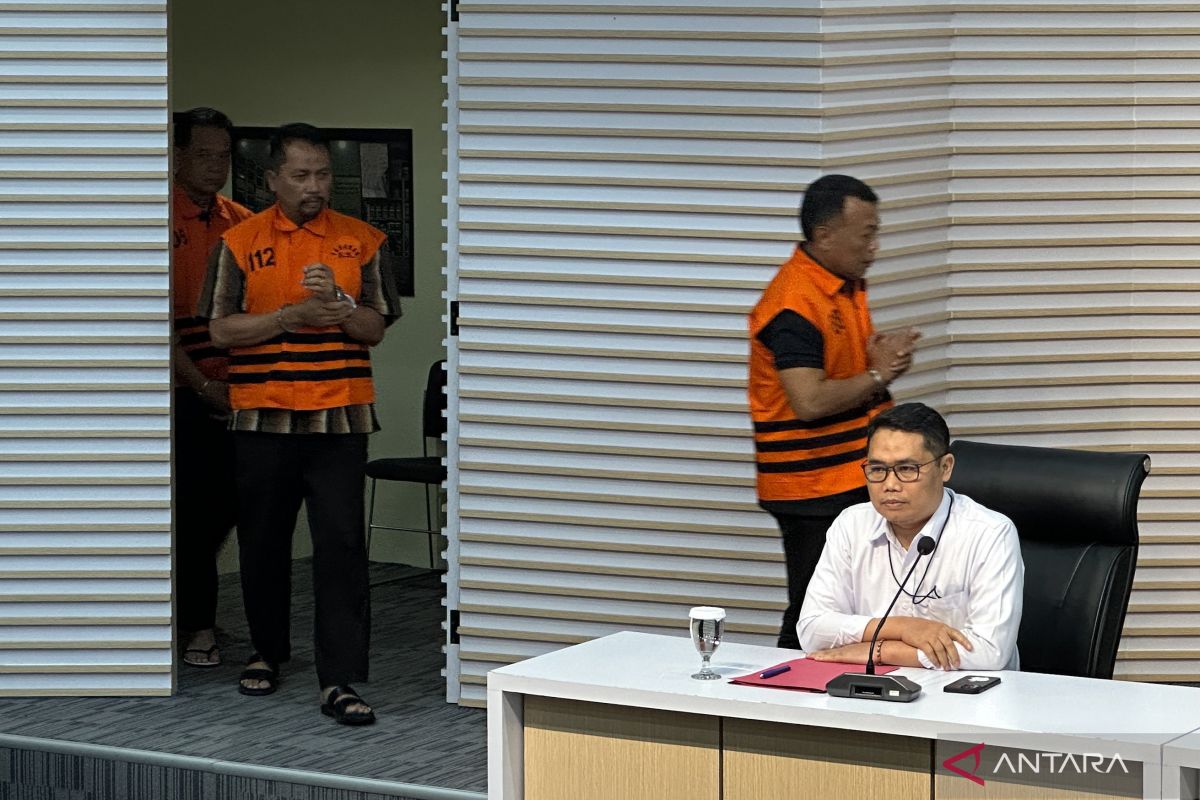Jakarta (ANTARA) - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menetapkan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk-produk asal Indonesia menjadi babak baru dalam dinamika perdagangan internasional yang kian didominasi kepentingan nasional dan kebijakan unilateralisme.
Dalam logika ekonomi global, tarif tersebut bukan hanya pukulan terhadap neraca perdagangan, tapi juga potensi ancaman terhadap penerimaan negara dan stabilitas sektor industri dalam negeri.
Saat banyak negara berlomba memperkuat integrasi pasar, kebijakan tarif tinggi dari AS justru memperkuat tren proteksionisme baru yang menantang semangat perdagangan bebas. Indonesia perlu merespons dengan taktik cermat, bukan hanya dari sisi diplomasi dagang, tetapi juga dengan menyusun ulang strategi fiskal untuk menjaga arus penerimaan negara tetap kuat.
Produk unggulan Indonesia seperti tekstil, alas kaki, karet olahan, dan sebagian elektronik ringan selama ini memiliki pasar ekspor utama ke Amerika Serikat. Dengan diterapkannya tarif 19 persen, daya saing produk-produk tersebut jelas menurun. Eksportir dalam negeri akan menghadapi tekanan biaya yang meningkat, sementara konsumen AS akan beralih pada produk dari negara pesaing seperti Vietnam atau Bangladesh yang lebih murah.
Ketika ekspor turun, pemerintah tidak hanya kehilangan potensi penerimaan dari PPN ekspor dan PPh badan dari eksportir, tetapi juga terancam kehilangan pendapatan turunan dari sektor-sektor penunjang: logistik, jasa pelabuhan, hingga pajak penghasilan karyawan sektor padat karya. Inilah efek domino dari ketergantungan pada satu pasar ekspor utama yang kini harus segera diakhiri.
Perspektif teori fiskal
Dalam konteks fiskal, fenomena tarif 19 persen yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dapat ditelaah melalui beberapa pendekatan teori ekonomi fiskal yang relevan, baik dari sisi optimalisasi penerimaan maupun ketahanan fiskal jangka panjang.
Pertama, Teori Kurva Laffer menunjukkan bahwa terdapat titik jenuh dalam hubungan antara tarif/pajak dan penerimaan negara. Ketika tarif terlalu tinggi, beban ekonomi menjadi berat, basis pajak menyempit karena volume transaksi menurun, dan penerimaan justru bisa menurun.
Dalam konteks ini, kebijakan tarif tinggi AS terhadap produk Indonesia berpotensi menurunkan volume ekspor secara signifikan, sehingga bukan hanya Indonesia yang terdampak, tetapi juga AS sebagai importir kehilangan basis pajak dari konsumsi.
Contoh nyata penerapan prinsip ini terlihat saat AS menaikkan tarif baja dan aluminium terhadap Tiongkok pada 2018–2019: alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan tersebut mendorong relokasi rantai pasok ke negara lain dan mempercepat inflasi domestik.
Untuk Indonesia, tarif tinggi ini dapat menurunkan potensi penerimaan dari PPN ekspor, PPh eksportir, bea keluar, dan PNBP pelabuhan/logistik.
Kedua, teori keunggulan komparatif (Ricardian) menggarisbawahi pentingnya suatu negara untuk fokus pada produksi barang yang memiliki efisiensi biaya relatif lebih tinggi dibanding negara lain.
Jika beban tarif dari negara mitra menghilangkan keunggulan biaya tersebut, maka produk ekspor Indonesia akan kalah bersaing. Misalnya, sektor tekstil dan alas kaki Indonesia selama ini memiliki keunggulan upah buruh yang relatif rendah dan keterampilan tinggi.
Namun, dengan tarif AS sebesar 19 persen, produk tersebut menjadi mahal dan kalah bersaing dengan Vietnam atau Bangladesh yang memiliki perjanjian tarif lebih ringan dengan AS. Akibatnya, Indonesia bukan hanya kehilangan pasar, tetapi juga produktivitas sektor industri menurun, yang berdampak langsung pada berkurangnya basis perpajakan seperti PPh 21 tenaga kerja, PPh badan pabrikan, serta PPN domestik dari aktivitas rantai pasok.
Ketiga, teori diversifikasi fiskal menekankan pentingnya memiliki portofolio sumber penerimaan negara yang luas dan tidak tergantung pada satu sektor, jenis pajak, atau pasar ekspor tertentu. Ketergantungan pada penerimaan dari ekspor ke satu negara seperti AS membuat APBN rentan terhadap gejolak geopolitik dan kebijakan proteksionis.
Negara-negara seperti Chile dan Uni Emirat Arab menjadi contoh sukses dalam diversifikasi penerimaan. Chile mengembangkan royalti tembaga dan inovasi pajak digital, sementara UEA menambahkan VAT, cukai, dan Pajak Korporasi sebagai pengganti dominasi pendapatan migas.
Indonesia perlu mendorong penerimaan dari sektor baru seperti ekonomi digital, energi terbarukan, dan pajak karbon, serta memaksimalkan PNBP dan dividen BUMN. Diversifikasi juga berarti memperluas pasar ekspor, misalnya menguatkan penetrasi ke Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan untuk mengompensasi kehilangan dari pasar AS.
Dengan menerapkan ketiga perspektif teori ini secara sinergis, Indonesia dapat menyusun ulang strategi penerimaan negara yang tidak hanya responsif terhadap krisis tarif saat ini, tetapi juga membangun sistem fiskal yang tangguh dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dari diversifikasi ke reformasi pajak
Menghadapi dampak kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat, pemerintah Indonesia harus merancang respons strategis yang komprehensif. Pendekatannya harus bersifat dua lapis: jangka pendek untuk mitigasi segera, dan jangka panjang guna membangun ketahanan fiskal nasional secara struktural.
Dalam jangka pendek, diplomasi dagang perlu ditingkatkan secara agresif. Diversifikasi pasar ekspor bukan lagi opsi, melainkan keharusan strategis. Indonesia harus mempercepat penyelesaian dan implementasi perjanjian dagang seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), memperluas skema Generalized System of Preferences (GSP) dengan negara-negara Afrika, serta memperdalam kerja sama dagang dengan India, Bangladesh, dan Timur Tengah.
Dengan mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat, Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas sektor industri padat karya, tetapi juga melindungi sumber penerimaan negara dari PPN ekspor, PPh badan eksportir, hingga bea keluar yang rentan terguncang akibat fluktuasi kebijakan eksternal.
Namun untuk menjamin keberlanjutan fiskal, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pengalihan pasar ekspor. Diperlukan strategi jangka panjang berbasis reformasi sistem penerimaan negara, yang meliputi beberapa pilar utama berikut:
Pertama, ekstensifikasi pajak domestik. Saat ini, sebagian besar potensi penerimaan negara masih terkunci di sektor informal dan ekonomi digital yang belum sepenuhnya terjangkau sistem perpajakan konvensional. Ekonomi berbasis platform, termasuk layanan daring, content creator, dan e-commerce lintas batas, tumbuh sangat cepat tetapi belum memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
Dengan implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia berpeluang melakukan perluasan basis pajak dengan pendekatan berbasis data, integrasi sistem administrasi, dan pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk deteksi otomatis wajib pajak yang selama ini tidak terjangkau. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan sukarela dan menjangkau sumber penerimaan baru tanpa harus menaikkan tarif pajak yang sudah ada.
Kedua, penerapan pajak karbon dan perluasan instrumen cukai. Dalam konteks transisi energi dan komitmen Indonesia terhadap target emisi net-zero pada 2060, pajak karbon dapat menjadi instrumen fiskal sekaligus alat perubahan perilaku.
Singapura dan Korea Selatan telah memulai langkah ini dengan tarif yang moderat namun progresif. Di Indonesia, potensi penerimaan dari pajak karbon diperkirakan dapat mencapai triliunan rupiah per tahun jika diterapkan secara bertahap pada sektor energi dan industri berat. Selain itu, perluasan cukai terhadap produk yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan seperti plastik sekali pakai, makanan dan minuman tinggi gula, serta emisi kendaraan bermotor dapat menambah sumber pendapatan sekaligus menciptakan insentif perilaku yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Ketiga, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan aset negara. Indonesia masih menyimpan potensi besar dari aset negara yang belum tergarap secara produktif. Ribuan lahan, bangunan, dan aset bergerak milik negara belum digunakan secara optimal.
Melalui skema pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berbasis kerja sama bisnis, seperti leasing, build-operate-transfer (BOT), atau kerja sama pemanfaatan aset publik, pemerintah dapat meningkatkan kontribusi fiskal tanpa membebani rakyat dengan pajak tambahan. Di samping itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas BUMN perlu diarahkan agar dividen yang disetorkan ke negara dapat meningkat secara berkelanjutan.
Ini terbukti efektif di beberapa negara, seperti Malaysia dan Norwegia, yang menjadikan dividen perusahaan negara sebagai sumber APBN strategis.
Dengan sinergi antara langkah diplomatik jangka pendek dan reformasi fiskal jangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat ketahanan penerimaan negara di tengah tekanan global. Bukan hanya mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal, tapi juga menyiapkan sistem penerimaan yang modern, adil, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan ekonomi masa depan.
Jalan menuju ketahanan fiskal
Tarif 19 persen dari AS bukan hanya tantangan, tapi juga momentum untuk Indonesia mempercepat diversifikasi penerimaan dan memperluas pasar ekspor. Ketahanan fiskal tidak akan lahir dari kebergantungan sempit pada satu pasar atau sektor, melainkan dari kemampuan negara membangun sistem perpajakan dan penerimaan yang luas, adil, dan responsif terhadap dinamika global.
Pemerintah perlu menjadikan momen ini sebagai alarm strategis untuk memperkuat arsitektur fiskal yang tangguh. Langkah-langkah seperti pembaruan data perpajakan, insentif ekspor untuk UKM, digitalisasi sistem kepabeanan, serta transparansi belanja negara harus berjalan bersamaan dengan reformasi fiskal.
Sehingga dengan demikian ,asa depan penerimaan negara Indonesia ada pada keberanian untuk berubah: dari reaktif menjadi strategis, dari sempit menjadi inklusif, dari rapuh menjadi resilien yang semuanya ditujukan untuk mewujudkan marwah tujuan bangsa Indonesia Emas 2045.
*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Kementerian Keuangan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.