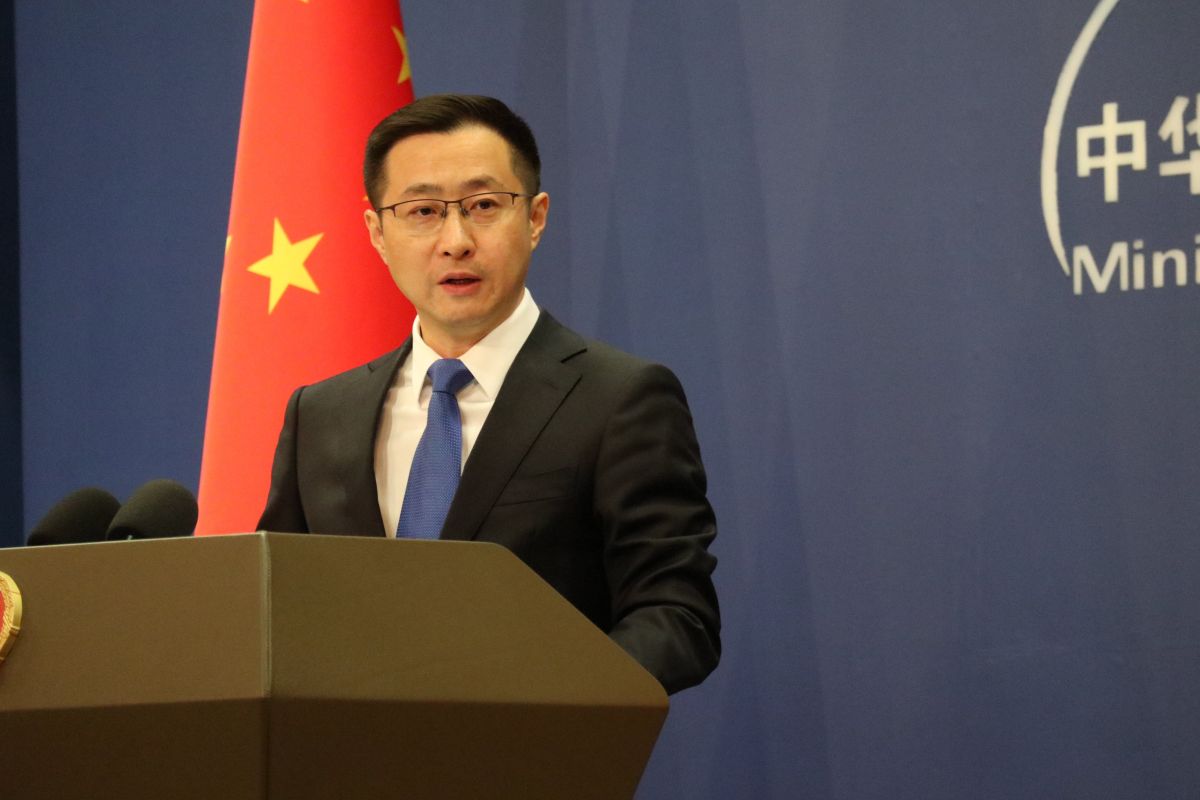Jakarta (ANTARA) - Ketika angka kemiskinan nasional perlahan turun, kita seakan menemukan secercah harapan di tengah dinamika sosial-ekonomi yang tidak mudah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,47 persen, lebih rendah dibandingkan 9,03 persen pada Maret 2024. Angka ini sekaligus merupakan catatan terendah sepanjang satu dekade terakhir.
Hanya saja, di balik capaian positif itu, ada dinamika yang perlu dicermati lebih dalam, yaitu penurunan kemiskinan di daerah perkotaan yang cenderung lebih lambat dibandingkan daerah perdesaan.
Selama periode September 2020 hingga Maret 2025, angka kemiskinan perkotaan turun dari 7,88 persen menjadi 6,73 persen, atau hanya berkurang 1,15 poin persentase. Sementara di perdesaan, angka kemiskinan turun lebih cepat, dari 13,20 persen menjadi 11,03 persen, atau berkurang 2,17 poin persentase.
Fakta ini menegaskan bahwa wajah kemiskinan perkotaan memiliki kompleksitas tersendiri yang tidak bisa hanya dijawab dengan pendekatan konvensional.
Agaknya, kemiskinan di perkotaan berkaitan erat dengan urbanisasi, yang di Indonesia berkembang pesat dalam tujuh dekade terakhir. Jika pada tahun 1950 hanya sekitar 15 persen penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan, kini lebih dari separuh populasi tinggal di perkotaan.
Fenomena ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, kota menawarkan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang relatif lebih baik dibanding perdesaan, namun di sisi lain, urbanisasi yang tidak terkendali memunculkan kantong-kantong kemiskinan baru di wilayah kumuh, dengan kondisi sanitasi buruk, keterbatasan air bersih, dan kepadatan hunian yang tidak sehat.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat bahwa pada 2022, sekitar 24,8 persen populasi urban dunia masih tinggal di kawasan kumuh, angka yang hanya turun tipis dari 25 persen pada 2015. Di Indonesia, meski akses air bersih dasar di perkotaan sudah mencapai 97,6 persen dan sanitasi dasar 91,6 persen, namun akses terhadap sistem pembuangan limbah yang layak masih sangat terbatas, yakni hanya sekitar 2 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk dalam kondisi kemiskinan kota masih jauh dari memadai.
Lebih jauh, persoalan urbanisasi dan kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan dari harga tanah dan properti di kota-kota besar yang terus melambung. Banyak keluarga miskin tidak mampu membeli atau bahkan menyewa hunian layak, sehingga terpaksa tinggal di rumah petak sempit atau permukiman informal.
Situasi ini kian pelik karena lapangan kerja formal di perkotaan juga tidak bertambah secepat laju migrasi penduduk. Akibatnya, banyak warga miskin kota yang menggantungkan hidup pada sektor informal, seperti berdagang kaki lima atau menjadi pekerja harian lepas yang rentan kehilangan pendapatan sewaktu-waktu alias terkurung dalam kondisi kemiskinan.
Pertumbuhan penduduk perkotaan tanpa perencanaan inklusif juga memperlebar jurang ketimpangan. Kemiskinan perkotaan seringkali berbeda wajah dengan kemiskinan perdesaan. Jika di perdesaan kemiskinan identik dengan keterbatasan aset lahan dan rendahnya produktivitas pertanian, maka di kota, kemiskinan lebih banyak terkait dengan tingginya biaya hidup, akses perumahan layak, maupun ketersediaan transportasi publik.
Tidak jarang, keluarga miskin perkotaan tinggal di wilayah bantaran sungai yang rawan banjir atau di gang sempit yang sulit dijangkau layanan kesehatan. Tanpa perumahan terjangkau dan sistem transportasi publik yang efisien, perkotaan bukan ruang peluang, tapi bisa menjadi jebakan bagi penduduk miskin. Kondisi ini menegaskan pentingnya menautkan agenda pengentasan kemiskinan (SDGs 1) dengan pembangunan kota berkelanjutan (SDGs 11).
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.