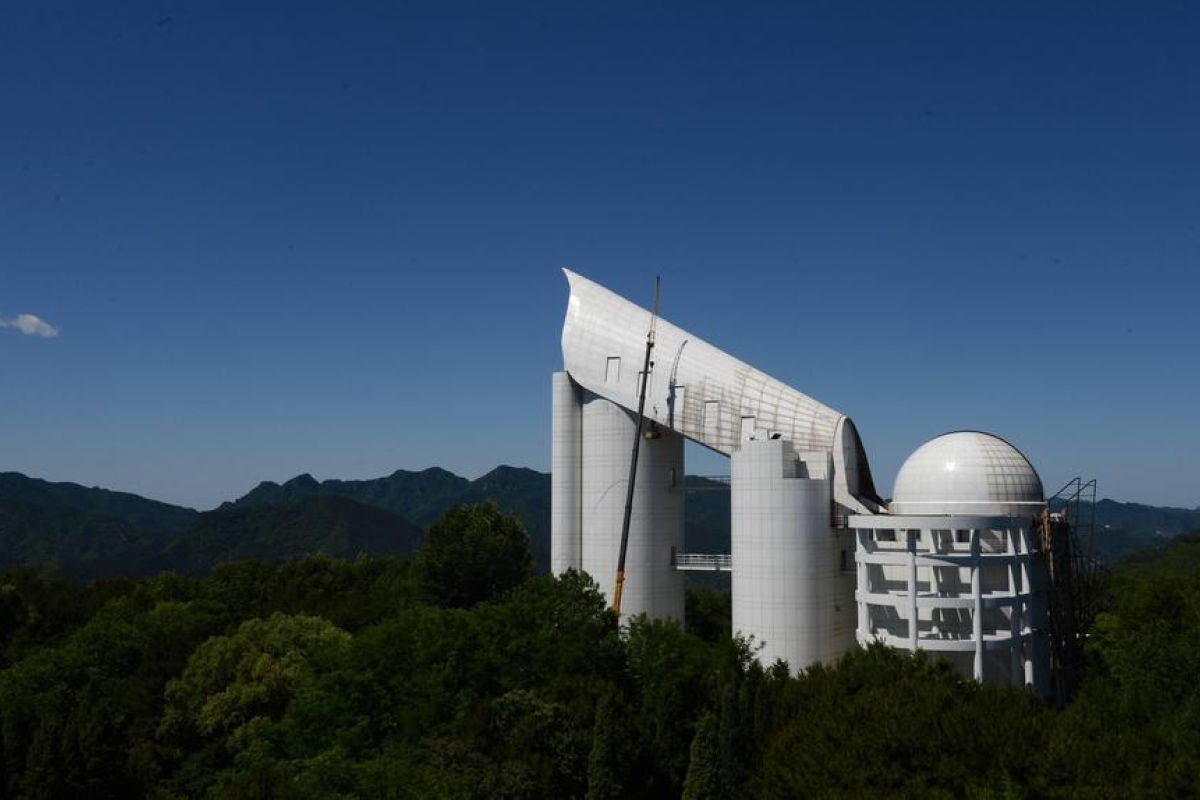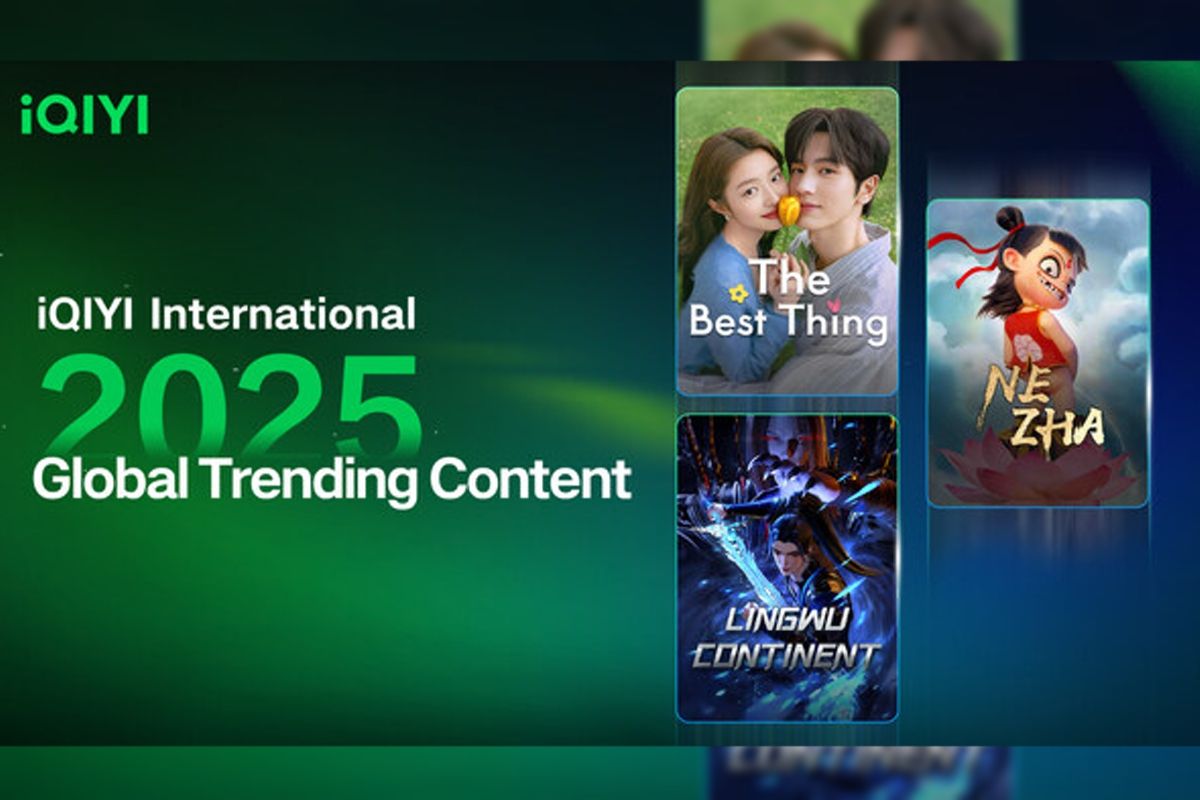Mataram (ANTARA) - Ketika hujan lebat mengguyur langit wilayah timur Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal November 2025, tidak banyak warga yang sempat waspada, sebelum air menyapu pemukiman dan jalan raya.
Di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, air mencapai ketinggian sekitar 60 sentimeter dan menutup akses jalan utama.
Sementara di Kabupaten Dompu, air juga merendam dua desa, yaitu Kramat dan Lasi, hingga memutuskan akses jalan utama dan mengisolasi warga untuk beberapa waktu.
Fenomena ini bukan sekadar kejadian alam yang singkat. Ia menuntut kita merenungkan kembali betapa rentannya wilayah NTB dalam menghadapi banjir, dan pada saat yang sama menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merespons dan mencegah bencana serupa terjadi kembali.
Dalam pengamatan cepat terhadap dua wilayah yang terdampak, tampak bagaimana sejumlah faktor berpadu membentuk bencana.
Curah hujan yang tinggi, aliran air dari hulu yang deras, sistem drainase yang sempit, hingga aktivitas manusia yang mengubah fungsi lahan, tanpa kendali, semuanya berperan menciptakan rentetan peristiwa yang sulit dibendung.
Di Bima, hujan deras sejak siang hari membuat air dari pegunungan turun deras dan meluap ke permukiman warga.
Sementara di Dompu, curah hujan disertai kilat dan angin kencang membuat empat kecamatan tergenang, dengan ketinggian air antara 20 hingga 70 sentimeter.
Genangan itu bukan sekadar akibat hujan, tetapi juga cerminan dari lemahnya tata kelola air di kawasan yang terus tumbuh, tanpa arah.
Di tengah kondisi itu, peran komunitas menjadi elemen penting. Sungai dan drainase yang dulu berfungsi sebagai jalur alami air, kini banyak tertutup bangunan, tertimbun sampah, atau menyempit karena alih fungsi lahan.
Seorang pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat menilai, persoalan banjir tidak bisa hanya dituding sebagai akibat dari curah hujan tinggi atau hutan yang gundul.
Ada rangkaian faktor yang saling terkait, yakni mulai dari menyempitnya sungai dan saluran drainase, hingga tumpukan sampah yang menghambat aliran air.
Pandangan itu menggambarkan kenyataan di lapangan. Di wilayah, seperti NTB yang didominasi perbukitan dan memiliki banyak daerah aliran sungai, waktu tanggap terhadap potensi banjir sangatlah singkat.
Ketika kawasan hulu tak terkelola dengan baik dan pemerintah daerah terlambat mengambil langkah antisipatif, air akan turun tanpa banyak peringatan, membawa lumpur dan genangan yang tak sekadar mengganggu, tetapi juga melumpuhkan aktivitas warga.
Peran pemda
Penanganan yang dilakukan pemerintah daerah di Bima dan Dompu memperlihatkan dua fase penting dalam menghadapi bencana, yakni tanggap darurat dan upaya mitigasi jangka panjang. Ketika banjir melanda, aparat di lapangan segera bergerak.
Di Dompu, tim gabungan yang terdiri atas BPBD, TNI/Polri, dan aparatur desa langsung melakukan asesmen serta membersihkan material banjir yang menumpuk di jalan dan permukiman warga.
Sementara di Bima, pemerintah kota mengerahkan petugas bersama masyarakat untuk membersihkan lumpur dan memperbaiki fasilitas yang terdampak.
Respons cepat di lapangan memang patut diapresiasi, tetapi itu belum cukup menandakan kesiapan daerah dalam aspek mitigasi.
Strategi jangka panjang, seperti memperkuat fungsi hidrologi, mengubah perilaku masyarakat terhadap sistem drainase, dan membangun tata ruang yang selaras dengan arah aliran air masih belum berjalan optimal.
Di kawasan perbukitan yang menjadi hulu air, alih fungsi lahan ke pertanian intensif atau lahan terbuka justru memperbesar risiko luapan.
Tanpa langkah pemulihan atau penghijauan, sungai-sungai yang kian menyempit akan terus menjadi ancaman laten, ibarat bom waktu yang hanya menunggu saatnya meledak.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah sejatinya memegang peran strategis. Mereka bukan hanya bertugas menanggulangi bencana setelah terjadi, tetapi juga merancang bagaimana air seharusnya mengalir, bagaimana kesadaran warga dibangun, serta bagaimana infrastruktur penahan air dibangun sesuai karakter wilayah.
BPBD NTB pernah menegaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus bertindak lebih dulu karena merekalah yang paling dekat dengan lokasi kejadian, sementara pemerintah provinsi siap memberikan dukungan.
Hanya saja, harapan ideal itu belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Koordinasi antarinstansi, ketersediaan anggaran, dan penentuan prioritas masih sering berjalan sendiri-sendiri.
Akibatnya, meski tindakan cepat selalu muncul, setelah bencana, upaya pencegahan sebelum air turun masih jauh dari kata siap.
Solusi
Tidak ada resep tunggal yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan banjir di Nusa Tenggara Barat, namun sejumlah langkah konkret sebenarnya dapat ditempuh jika pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta mampu berjalan beriringan.
Langkah pertama adalah memperkuat sistem aliran air dari hulu hingga hilir. Pemerintah daerah perlu memastikan daerah aliran sungai (DAS) kembali berfungsi sebagaimana mestinya, dengan melakukan penghijauan di kawasan hulu, menata tebing sungai, dan memeriksa secara rutin kondisi saluran air dan drainase. Jika alih fungsi lahan di wilayah perbukitan terus dibiarkan, tanpa kendali, maka bukan tidak mungkin banjir besar akan kembali datang, mengulang kisah yang sama dari tahun ke tahun.
Langkah kedua adalah meninjau ulang tata ruang dan izin pembangunan di kawasan rawan banjir. Bangunan yang berdiri di tepi sungai atau di atas jalur air kerap menjadi penghalang alami aliran air. Karena itu, pemda perlu memperketat izin serta memastikan saluran air dan drainase tetap terbuka. Dalam banyak kasus, drainase yang tersumbat oleh sampah atau bangunan membuat air hujan seketika berubah menjadi ancaman serius.
Langkah ketiga menyangkut kesiapsiagaan warga. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki BPBD dan sistem tanggap darurat, edukasi masyarakat masih sering bersifat reaktif, baru dilakukan setelah banjir terjadi. Padahal, pelatihan rutin, simulasi evakuasi, dan pemetaan wilayah rawan banjir bisa menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan komunitas. Program semacam ini perlu menjadi agenda tetap di tingkat sekolah, desa, hingga kelurahan.
Dari sisi anggaran, pemerintah juga perlu mengubah paradigma dari sekadar tanggap darurat menuju upaya mitigasi yang lebih berkelanjutan. Anggaran untuk pemulihan memang penting, tetapi porsi yang lebih besar seharusnya diarahkan pada langkah-langkah pencegahan, seperti membangun tanggul alami, menyiapkan penampungan air sementara, memperluas ruang hijau, hingga memperbaiki saluran air yang rusak. Rencana semacam ini perlu tertuang dengan jelas dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan APBD, agar tidak berhenti pada tataran wacana semata.
Terakhir, banjir bukan persoalan pemerintah semata, melainkan tanggung jawab kolektif. Dunia usaha dapat berperan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), misalnya dengan membantu penghijauan di kawasan hulu. Komunitas lokal bisa membentuk tim siaga banjir di tingkat desa atau kelurahan. Pemerintah daerah berperan sebagai penggerak, pembina, dan pengatur agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat aktif.
Hanya dengan kolaborasi lintas pihak, langkah-langkah kecil itu dapat berubah menjadi kekuatan besar yang menahan air sebelum berubah menjadi bencana.
Refleksi
Melihat kejadian banjir di Bima dan Dompu, masyarakat NTB diingatkan bahwa bencana bukan sekadar musibah yang hanya bisa ditanggulangi setelah datang; bencana adalah fenomena hidrometeorologi yang bisa ditekan dengan kesiapan dan desain ruang hidup yang tepat.
Pemda memiliki peran sangat krusial dalam meminimalisir risiko mulai dari hulu hingga hilir, dari kebijakan tata ruang hingga aksi gotong-royong di tingkat warga.
Ketika pemerintah daerah mampu menyelaraskan tindakan tanggap darurat dengan upaya mitigasi jangka panjang, ketahanan wilayah terhadap banjir akan meningkat secara nyata. Pada titik itu, warga NTB tidak lagi akan selalu tergiring oleh rasa terkejut setiap kali hujan besar datang mengguyur.
Banjir memang bisa menjadi peringatan, tetapi pada saat yang sama, ia juga dapat menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran, memperkuat sinergi, dan menata sistem yang lebih tangguh di masa depan.
Kini, pilihan sepenuhnya berada di tangan semua pihak. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus menunggu air datang dan menanggung akibatnya, atau justru bergerak lebih awal agar air tidak lagi membuat kita tak berdaya.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.