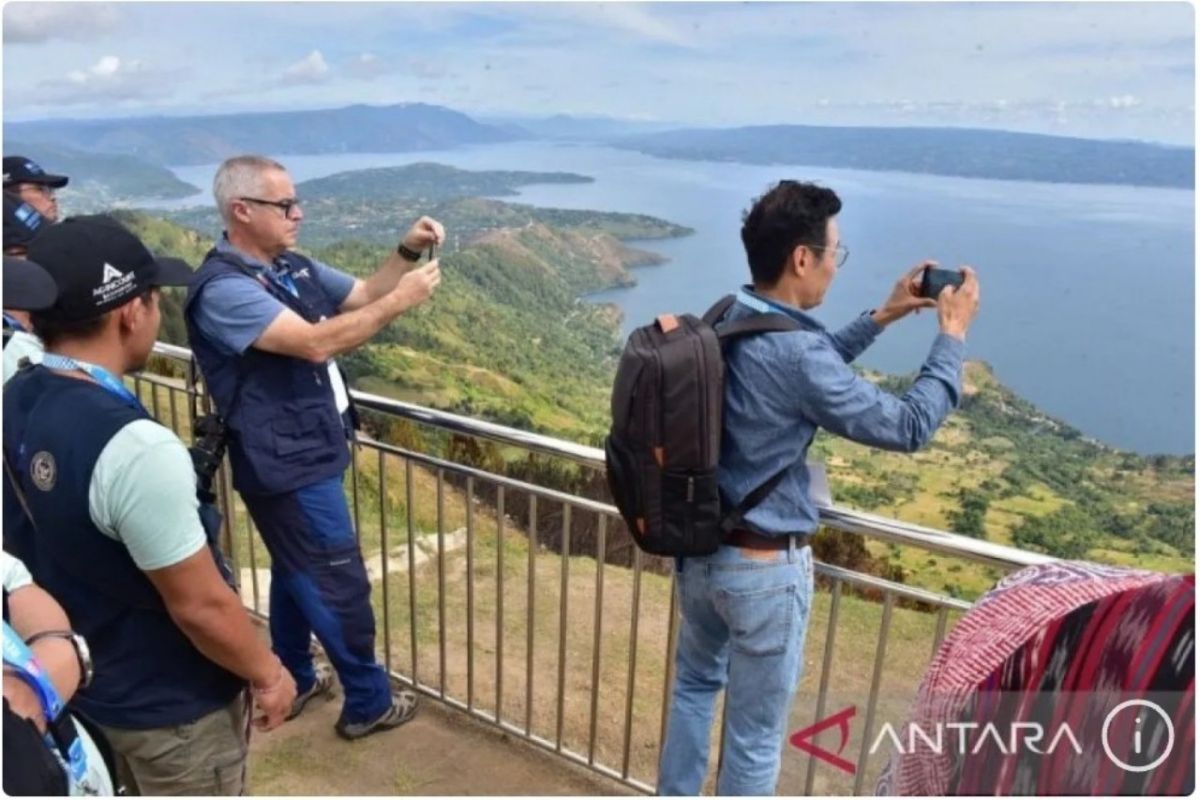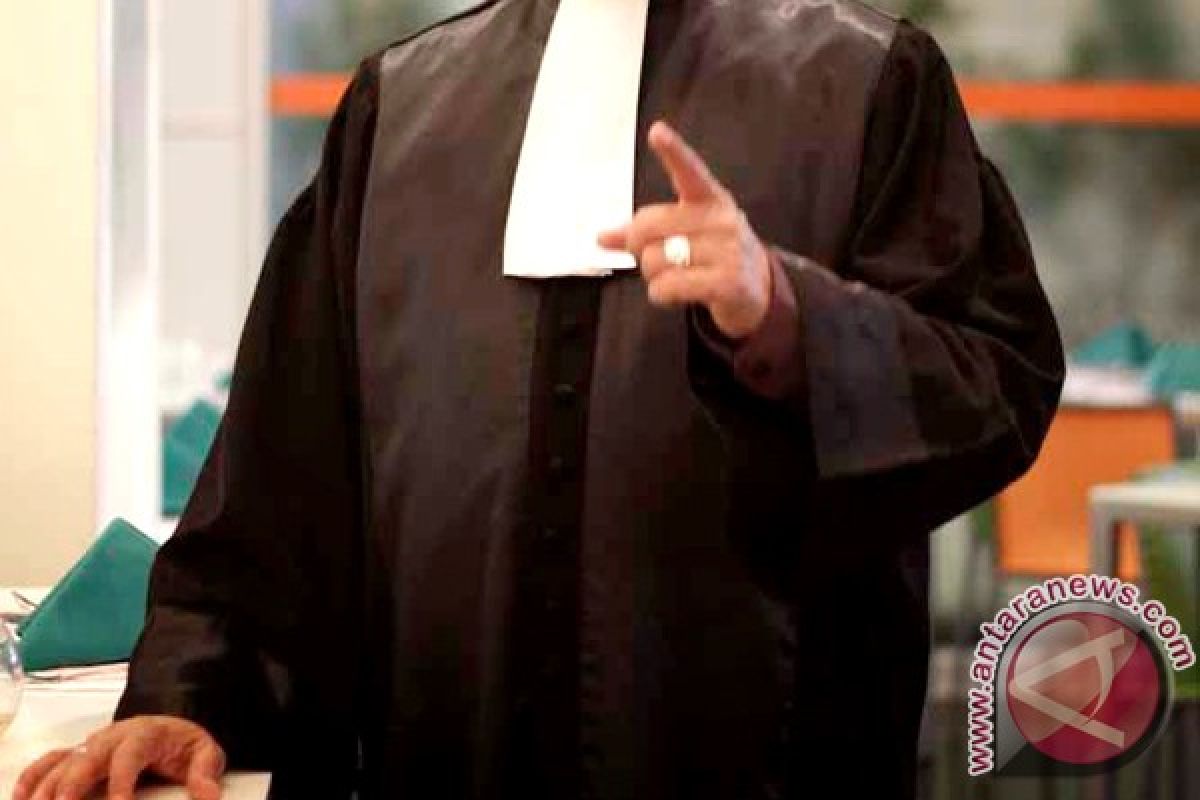Jakarta (ANTARA) - Kebijakan perpajakan selalu menjadi perbincangan penting dalam kaitannya dengan dunia usaha, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memungut pajak dari usaha kecil. Penegasan ini bukan hanya bentuk kebijakan fiskal semata, melainkan juga afirmasi dukungan nyata terhadap UMKM yang selama ini menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi akses permodalan, birokrasi, maupun tekanan pasar.
Pernyataan ini sekaligus menghapus kekhawatiran sebagian pelaku usaha kecil yang merasa terbebani dengan kewajiban perpajakan, padahal usaha mereka masih berada pada tahap merintis. Dengan kata lain, negara hadir untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan UMKM agar lebih berdaya saing, bukan justru menekan mereka dengan beban pajak di awal perjalanan bisnis
UMKM di Indonesia telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM mencapai lebih dari 64,2 juta unit usaha, atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sektor UMKM berhasil menyerap tenaga kerja lebih dari 123 juta orang atau sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, sehingga keberadaannya menjadi penopang utama dalam mengurangi angka pengangguran.
Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun sangat signifikan, yakni mencapai 61,07 persen pada tahun 2023. Angka ini tidak hanya menunjukkan kapasitas UMKM dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menggambarkan betapa vitalnya peran sektor ini dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi, terutama di tengah kondisi krisis global.
Meski demikian, kekuatan UMKM belum sepenuhnya termanfaatkan optimal. Kendala klasik masih menghantui, mulai dari keterbatasan akses permodalan hingga hambatan struktural. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada 2023 porsi kredit perbankan kepada UMKM hanya sekitar 21,26 persen dari total kredit nasional, jauh dari target pemerintah sebesar 30 persen pada 2024.
Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan digital menjadi tantangan serius. Survei Bank Indonesia mencatat bahwa baru sekitar 24,9 persen UMKM yang sudah memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk, padahal digitalisasi terbukti meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa selain dukungan pembiayaan, UMKM juga membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi hambatan struktural.
Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah untuk membebaskan pajak usaha kecil menjadi langkah afirmatif yang strategis. UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta per tahun saat ini tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
Kebijakan ini memberikan ruang bernapas bagi pelaku usaha kecil agar dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani kewajiban fiskal di tahap awal. Secara makro, insentif fiskal ini diperkirakan dapat mendorong daya tahan usaha mikro, memperluas basis formalitas, serta meningkatkan produktivitas.
Hal ini relevan mengingat pengalaman selama pandemi COVID-19, di mana UMKM menjadi sektor yang paling terdampak, dengan lebih dari 30 juta UMKM mengalami penurunan omzet signifikan.
Dengan demikian, penghapusan pajak bagi usaha kecil bukan hanya soal keringanan administrasi, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional.
Pajak usaha kecil
Perjalanan kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi dan kebutuhan negara dalam memperluas basis penerimaan pajak. Pada era sebelum 2000-an, sektor UMKM praktis belum tersentuh oleh regulasi perpajakan yang memadai.
Mayoritas pelaku usaha mikro berada di sektor informal tanpa kewajiban membayar pajak, tetapi di sisi lain mereka juga tidak memiliki akses terhadap pembiayaan formal maupun perlindungan dari sistem keuangan negara. Hal ini menjadikan UMKM ibarat "ekonomi bayangan" yang besar, tetapi belum terintegrasi dalam struktur fiskal nasional.
Upaya sistematis baru terlihat ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013. Regulasi ini menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1 persen dari omzet untuk UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Tujuannya adalah menciptakan kesederhanaan administrasi sekaligus mendorong kepatuhan pajak.
Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sejak diberlakukannya aturan tersebut, jumlah Wajib Pajak (WP) UMKM meningkat signifikan. Pada 2013, tercatat sekitar 1,3 juta WP UMKM terdaftar, dan angka ini melonjak menjadi 2,6 juta WP pada 2015.
Meski demikian, kebijakan ini menimbulkan kritik karena sistem berbasis omzet dinilai membebani pelaku usaha kecil dengan margin laba tipis. Banyak UMKM yang omzetnya cukup besar tetapi keuntungan bersihnya kecil tetap terkena kewajiban pajak yang sama, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan.
Sebagai respons, pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari omzet, sekaligus memberi batas waktu penggunaan tarif ini untuk mendorong UMKM naik kelas.
Kebijakan ini mendapat sambutan lebih baik, terbukti dari meningkatnya kepatuhan. Pada 2019, jumlah WP UMKM yang tercatat mencapai sekitar 2,9 juta WP, dan pada 2020 angkanya naik menjadi 3,5 juta WP meski ekonomi sempat terguncang pandemi COVID-19.
Menariknya, pada masa pandemi, justru lebih dari 30 juta UMKM mengalami penurunan omzet signifikan, sehingga pemerintah memberikan insentif tambahan berupa pembebasan PPh Final UMKM ditanggung pemerintah. Langkah ini berhasil menjaga keberlangsungan jutaan pelaku usaha kecil di tengah krisis.
Hingga 2024, data DJP menunjukkan bahwa jumlah WP UMKM aktif mencapai lebih dari 4,2 juta WP, meski masih jauh dari total potensi 64 juta unit usaha. Dari angka ini, sebagian besar berasal dari segmen usaha mikro dan kecil dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.
Dalam konteks inilah, pernyataan Menteri Koperasi dan UKM bahwa usaha kecil dengan omzet di bawah batas tertentu tidak akan dipungut pajak menjadi sangat relevan.
Keberpihakan
Kebijakan afirmatif ini bukan hanya sekadar keringanan fiskal, melainkan bentuk keberpihakan nyata pada sektor yang masih rentan. Negara memahami bahwa UMKM membutuhkan ruang tumbuh dan dukungan, bukan beban administrasi tambahan, agar kelak mampu naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.
Afirmasi pemerintah berupa penghapusan pajak usaha kecil sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar kebijakan fiskal. Awalnya ini menjadi bagian dari perlindungan bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang berada pada tahap awal usaha.
Dengan tidak adanya beban pajak, para pengusaha kecil dapat memfokuskan sumber daya yang terbatas untuk memperkuat modal kerja, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kapasitas produksi.
Kebijakan ini juga berfungsi sebagai dorongan pertumbuhan yang konkret. Dengan keringanan fiskal, UMKM terdorong untuk bertransformasi dari usaha subsisten menuju usaha produktif yang lebih mapan. Misalnya, banyak usaha mikro di sektor fashion dan kerajinan yang sebelumnya hanya beroperasi dalam skala rumah tangga, kini berani mengikuti pameran atau menjangkau pasar digital melalui marketplace. Mereka lebih percaya diri karena biaya operasional berkurang akibat pembebasan pajak.
Hal ini menciptakan multiplier effect: semakin besar omzet yang dihasilkan, semakin cepat usaha tersebut naik kelas ke kategori menengah, dan pada akhirnya mereka akan menjadi kontributor pajak yang signifikan.
Lebih jauh, kebijakan afirmatif ini mencerminkan keberanian pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal dengan keberlanjutan ekonomi rakyat. Dalam jangka pendek, negara mungkin kehilangan sebagian potensi penerimaan dari pajak UMKM kecil. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini adalah bentuk investasi sosial-ekonomi yang akan menghasilkan basis pajak yang lebih luas.
Pada periode pandemi COVID-19 misalnya, ketika pemerintah menanggung PPh Final UMKM 0,5 persen. Meskipun negara mengorbankan penerimaan sekitar Rp2,4 triliun pada 2020, kebijakan ini terbukti menjaga keberlangsungan 2,8 juta WP UMKM yang tetap terdaftar aktif. Dengan tetap bertahan, usaha-usaha tersebut berpeluang tumbuh dan memberikan kontribusi lebih besar setelah ekonomi pulih.
Akhirnya, afirmasi kebijakan ini membuktikan bahwa pembangunan ekonomi inklusif tidak bisa hanya dilihat dari sisi penerimaan fiskal jangka pendek. Pemerintah menempatkan UMKM sebagai mitra strategis dalam agenda pembangunan, bukan sekadar objek pajak.
*) Dr. M. Lucky Akbar adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Kementerian Keuangan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.