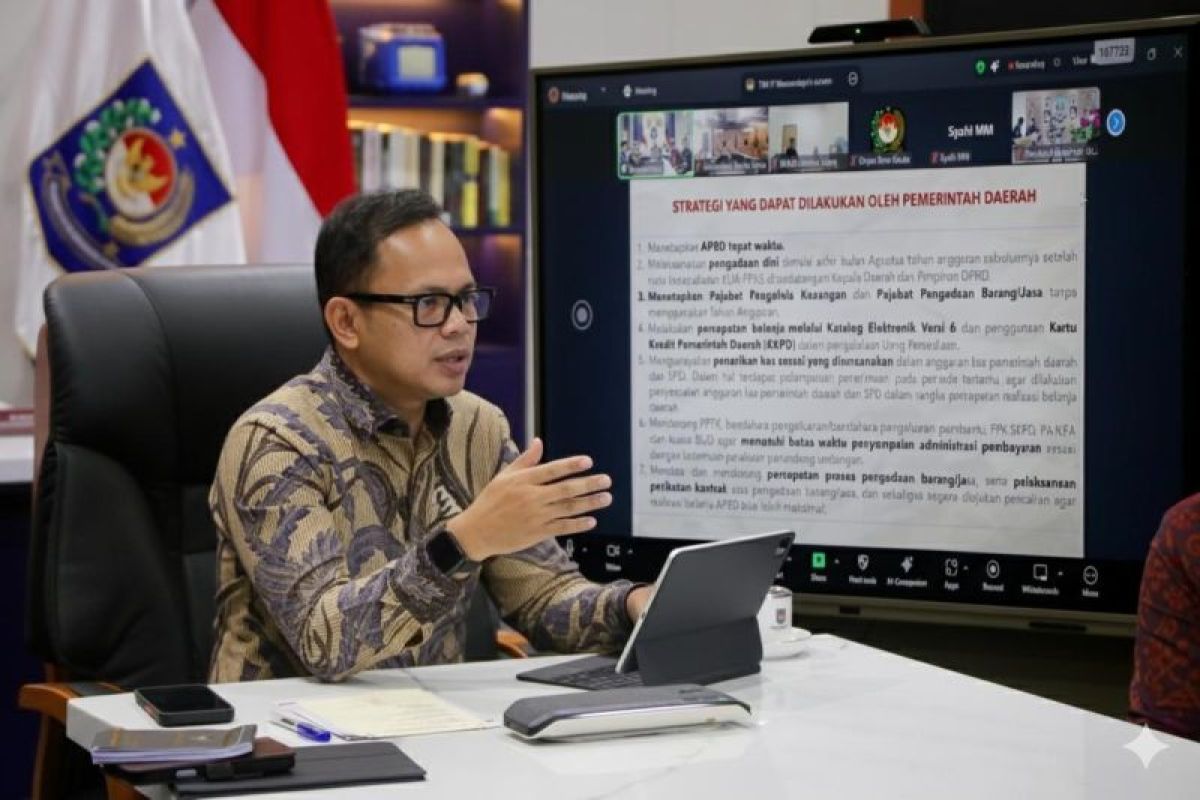Jakarta (ANTARA) - Ada satu praktik sederhana yang kerap terabaikan dalam relasi kita dengan bumi: mendengarkan.
Sejatinya, setiap detak kehidupan di alam ini menghasilkan suara. Kicau burung, gemericik air sungai, desau angin, gemerisik daun, hingga nyanyian serangga, semuanya membentuk soundscape, lanskap akustik yang menjadi cermin dari kesehatan ekosistem.
Suara alam adalah bentuk komunikasi yang paling jujur dan tidak dibungkus kepentingan. Melalui suara-suara tersebut, alam ingin memberitahu manusia, khalifah di muka bumi ini, apakah ia baik-baik saja atau tengah terluka.
Hutan yang sehat misalnya, tidak pernah sepi dengan suara burung, serangga, ataupun binatang lain, dan bahkan keheningan yang ritmis. Namun saat ekosistem terganggu, suara-suara ini berubah atau bahkan menghilang. Inilah yang kemudian dikenal dengan fenomena silent forest syndrome.
R. Murray Schafer, seorang komposer, penulis, dan pendidik asal Kanada memperkenalkan istilah soundscape untuk menggambarkan lanskap suara suatu tempat, mencakup suara alam non-biologis (geophony) seperti suara angin dan air; suara makhluk hidup (biophony) termasuk suara burung, serangga dan manusia; serta suara buatan manusia (anthrophony) seperti musik dan suara mesin.
Konsep ekologi akustik yang dicetuskan oleh Schafer menawarkan pendekatan berbeda dalam membaca keadaan lingkungan yaitu dengan mendengar. Dalam hal ini, suara dipandang sebagai data ekologis, warisan budaya, dan peringatan dini atas kerusakan lingkungan yang tak selalu kasat mata.
Baca juga: Mengungkap gunung api purba bawah laut Geopark Pegunungan Meratus
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.