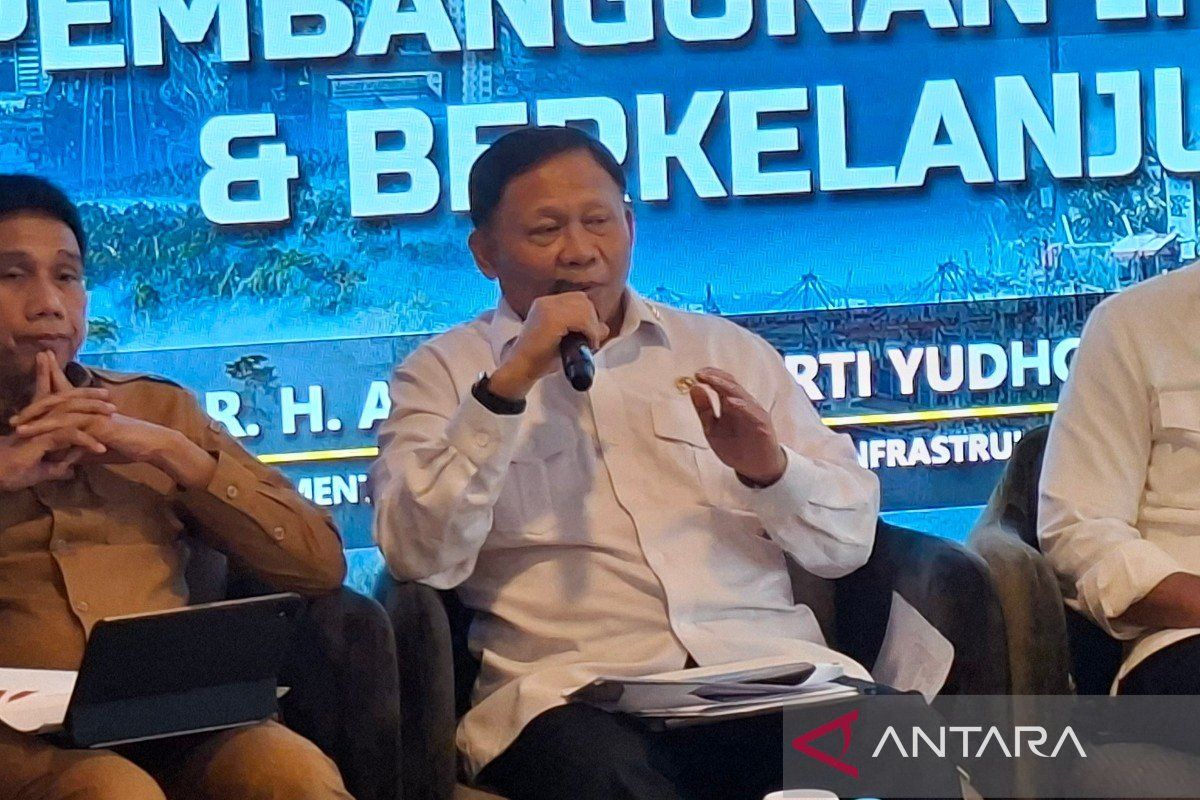Jakarta (ANTARA) - Bagi sebagian anak, masa remaja adalah waktu untuk tumbuh, bermain, belajar, dan bermimpi. Tapi di banyak sudut negeri ini, anak-anak justru mengakhiri masa remajanya terlalu cepat dengan duduk di pelaminan.
Mimpi dan angan mereka dihentikan oleh keputusan yang bukan miliknya. Kondisi ekonomi, tuntutan adat istiadat, hingga tekanan sosial budaya menjadi alasan yang selalu menjelma sebagai bayang-bayang.
Tak hanya merenggut masa depan, pernikahan anak usia dini juga menimbulkan luka menganga dan trauma yang mendalam.
Seperti yang dialami A-H, salah seorang penyintas pernikahan bocah asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ia harus mengakhiri masa lajangnya saat baru beranjak dari usia 16 tahun atau di kelas 2 SMA.
Hilangnya peran orang tua, diperparah dengan buruknya perlakuan orang-orang sekitar yang kerap menghujaninya dengan makian, kian menguatkan niat A-H untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan pasangan laki-lakinya yang juga masih belia.
Di dalam benaknya, menikah adalah satu-satunya cara untuk menuju jalur kebahagiaan yang selama ini hanya sedikit ia rasakan di kehidupan sebelumnya.
"Sebelum saya memutuskan menikah, kondisi saya saat itu memprihatinkan, saya frustrasi banget dengan kehidupan," kata A-H.
Demi memuluskan niatnya, ia dan sang pujaan hati menempuh jalan adat. Dengan restu yang belum sepenuhnya didapat dari orang tua mempelai pria, mereka menjalani tradisi Merariq.
Merariq adalah salah satu adat-istiadat yang berasal dari masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Tradisi ini berkaitan dengan proses perkawinan dan sering dikenal juga dengan istilah "kawin lari" atau "melarikan calon pengantin wanita" meskipun maknanya tidak sesederhana itu.
"Saya diculiknya sekitar dua hari ke rumahnya dia," kata A-H.
Khayalan kebahagiaan yang dulu menjadi lamunan ternyata hanya fatamorgana, berganti dengan derita dan rasa trauma yang berkepanjangan.
Usia pernikahan yang masih seumur jagung pun harus kandas di tengah jalan sebelum ia mengecap manisnya biduk rumah tangga. Kini, laki-laki yang dulu ia idam-idamkan untuk menjadi teman hidup, pergi tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya.
Setali tiga uang, cerita senada juga dialami oleh pasangan muda-mudi I-W dan R-N asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mereka menjalani kehidupan dengan tertatih setelah nekat "nikah kecil" (bahasa lokal Lombok).
Narasi cerita tidak jauh berbeda dengan yang diungkap penyintas A-H, mereka menikah di usia belia yaitu 15 dan 18 tahun.
Berawal dari trauma masa lalu yang dibumbui dengan rasa saling tidak mau kehilangan satu sama lain menguatkan pasangan ini untuk sesegera mungkin membentangkan bahtera rumah tangga dengan perbekalan seadanya.
Lagi-lagi, tradisi Merariq mereka gunakan sebagai "by pass" menuju janji suci pernikahan di kala usia belum sampai untuk memenuhi aturan dan ketentuan negara.
Tahun silih berganti, hari-hari pasangan yang telah dikaruniai seorang anak perempuan ini pun dijalani dengan berat.
Bekal ekonomi yang tidak dipersiapkan sebelum pernikahan, diperparah dengan emosi keduanya yang belum stabil, kerap menjadi penyebab munculnya perselisihan yang tak kunjung usai.
Cerita-cerita manis saat berpacaran tidak nampak saat mereka satu atap. Suara token listrik bersahutan dengan nyaring suara anak merengek meminta susu formula menjadi ujian harian yang kerap dihadapi pasangan ini.
"Kalau dirasakan, ya, banyak penyesalan. Tapi mau gimana dijalani, kan, rumah tangga gak mungkinlah kita baru nikah terus pengen cerai. Dia sering minta cerai tapi saya tahan, banyak cobaannya," kata I-W.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.