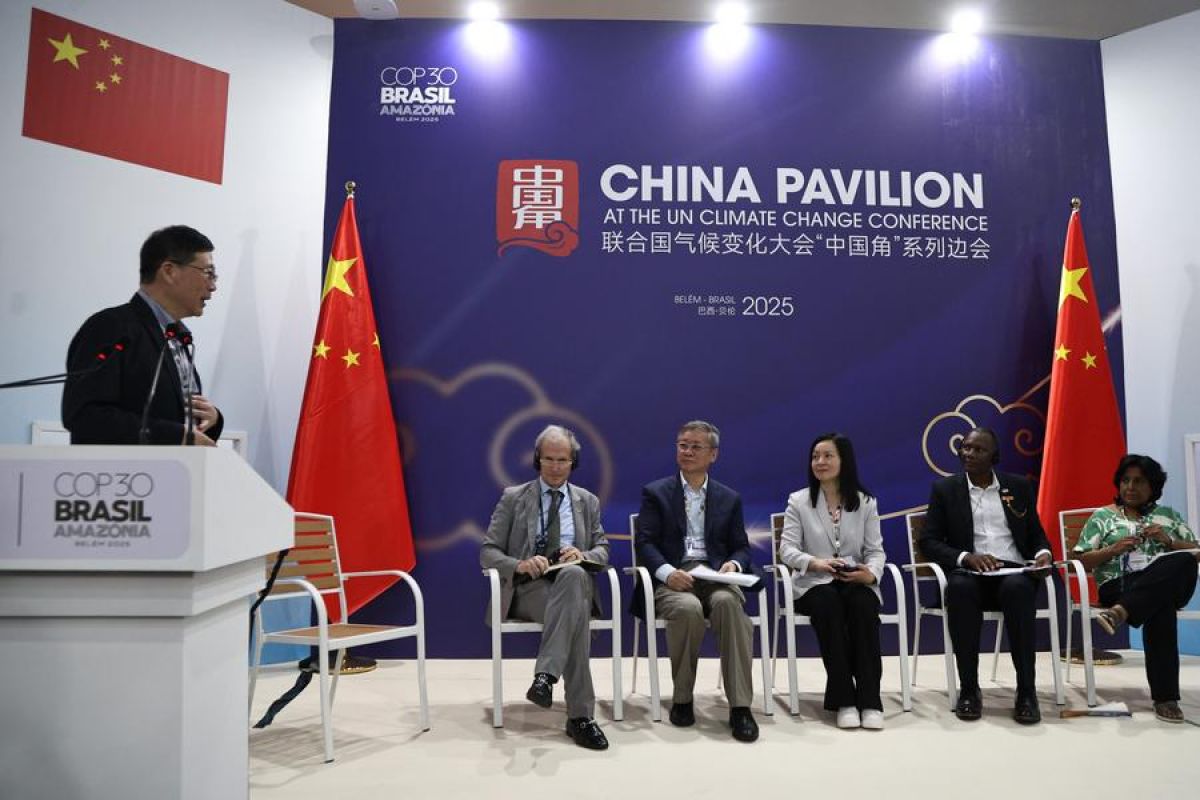Jakarta (ANTARA) - Delapan puluh tahun setelah kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang jati dirinya sebagai bangsa.
Perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat seringkali membuat nilai-nilai budaya tergeser atau hanya tampil sebagai simbol tanpa makna yang hidup.
Di tengah arus globalisasi, warisan budaya yang seharusnya menjadi kekuatan justru berisiko terpinggirkan jika tidak dihidupkan kembali melalui dialog dan kebijakan yang berpihak pada identitas bangsa.
Dalam forum GREAT Lecture di Jakarta pada 14 Agustus 2025 bertema polemik kebudayaan, pernyataan dan gagasan yang mengemuka menunjukkan bahwa bangsa ini memerlukan upaya serius untuk menemukan kembali jati dirinya.
Menteri Kebudayaan, Dr. H. Fadli Zon, menggarisbawahi pentingnya reinventing Indonesia’s identity, bukan sekadar sebagai wacana abstrak, tetapi sebagai proyek besar yang menyentuh sejarah, kebijakan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negeri dengan kekayaan budaya yang tak tertandingi, baik yang kasat mata maupun yang tak berwujud. Dari wayang hingga reog, dari jamu hingga keris, warisan ini adalah modal kultural yang mestinya menjadi sumber kekuatan di tengah arus globalisasi.
Namun, kekayaan ini terancam jika narasi kebudayaan dibungkam atau dipersempit hanya menjadi hiasan di festival, tanpa ruang dialektika yang hidup.
Dalam orasi panjang tapi tak kehilangan api, Fadli Zon mengurai kembali sejarah dialektika kebudayaan bangsa ini dari Polemik Kebudayaan 1930-an antara Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane, hingga pertarungan ideologis Manifes Kebudayaan versus Lekra pada 1960-an.
Namun, bagi Fadli, yang terpenting bukanlah siapa menang melawan siapa. Yang utama adalah pergulatan pemikiran itu sendiri.
Fadli mengaku sudah mengelilingi 101 negara dan menemukan bahwa tak ada yang sekaya Indonesia dalam hal budaya, baik yang tangible maupun intangible. Ia menyebut budaya intangible Indonesia yang tercatat 2.213, tapi baru 16 yang diakui UNESCO di antaranya wayang, batik, keris, jamu, dan reog.
Ia menyinggung Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”
Dengan mengutip penemuan-penemuan arkeologis, ia menyebut bahwa Homo erectus Indonesia telah hidup 1,8 juta tahun lalu.
Gambar-gambar gua tertua ditemukan di Muna dan Maros, jauh lebih tua dari lukisan gua di Eropa. “Kita ini melting pot sejak dulu kala. Kita bukan tempat tujuan. Tapi tempat keberangkatan,” ujarnya, menyiratkan bahwa Nusantara adalah simpul globalisasi purba.
Pandangan ini mendapat penguatan dari Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, yang mengkritisi lemahnya pemahaman elite terhadap budaya di wilayah kepemimpinannya.
Ia mencontohkan kebijakan menaikkan PBB secara sepihak di tengah penderitaan ekonomi rakyat yang berujung pada chaos yang mengarah pada pemakzulan seorang bupati.
Kebijakan yang lahir dari ketidakpahaman terhadap kultur masyarakat hanya memperdalam jarak antara pemimpin dan rakyat.
Pernyataan ini menyiratkan pesan bahwa kebijakan publik haruslah berakar pada pemahaman yang utuh terhadap realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tanpa itu, keputusan hanya menjadi produk teknokratis yang miskin empati.
Baca juga: Fadli tegaskan Indonesia miliki kekayaan budaya megadiversity
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.