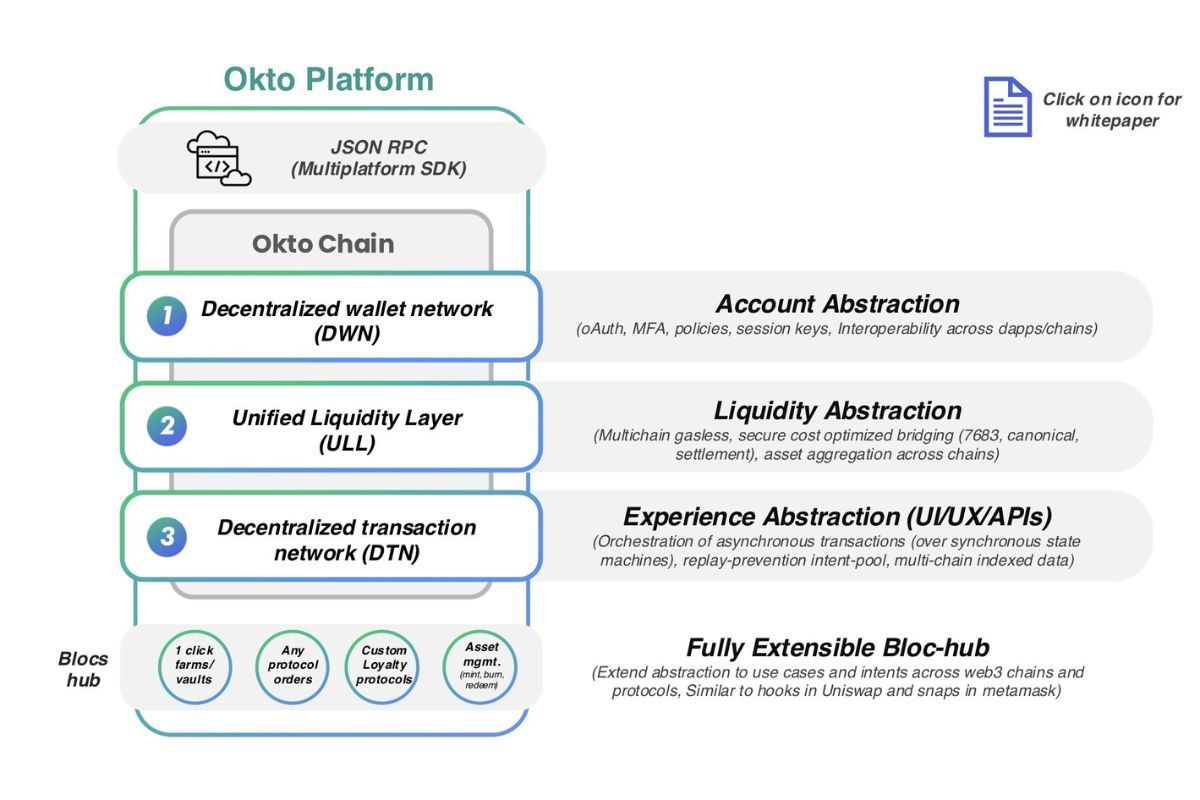Jakarta (ANTARA) - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah banyak mendapat cemoohan dan hujatan dari pihak lawannya, tetapi yang tidak disangka-sangka adalah sikap kepala negara Amerika Serikat ternyata secara gamblang menyatakan bahwa Zelenskyy adalah seorang "diktator".
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari lalu telah menyatakan pemimpin Ukraina itu sebagai diktator karena Zelenskyy menolak menggelar pemilihan umum (pemilu).
Senada dengan Trump, miliarder dan donor utama kampanye Trump, Elon Musk, juga mendesak agar Zelenskyy dapat segera menggelar pemilu untuk "membuktikan bahwa dia benar-benar mewakili kehendak rakyat".
Padahal, alasan Zelenskyy untuk membatalkan penyelenggaraan pemilu pada 2024 itu adalah karena adanya status darurat militer akibat invasi yang telah dilakukan Rusia sejak Februari 2022.
Zelenskyy juga mendapatkan pembelaan dari sejumlah pemimpin negara-negara Eropa. Juru Bicara Downing Street menyatakan bahwa Perdana Menteri Inggris Raya Keir Starmer terus mendukung Zelenskyy sebagai seorang pemimpin Ukraina yang terpilih secara demokratis.
Juru bicara pemerintahan Inggris itu juga mengingatkan bahwa sebenarnya sangatlah beralasan bahwa Ukraina menunda pemilu di tengah konflik dengan Rusia. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Inggris pada periode Perang Dunia Kedua lalu, saat Nazi Jerman menyerang hampir seluruh Eropa.
Selain dari Inggris, pembelaan juga datang dari negara lainnya seperti Jerman. Kanselir Jerman Olaf Scholz kepada surat kabar Der Spiegel mengatakan bahwa bila ada yang menyangkal legitimasi demokrasi Presiden Ukraina, maka hal itu adalah tindakan yang salah dan berbahaya.
Scholz mengingatkan bahwa pemilu selayaknya dan sepatutnya tidak dapat digelar di tengah perang. Aturan tersebut selaras dengan persyaratan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan pemilu Ukraina.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock berkomentar lebih jauh lagi dengan mengemukakan kepada lembaga penyiaran televisi ZDF bahwa bagi orang-orang yang hidup di dunia nyata dapat mengetahui siapa saja "di Eropa yang harus hidup dalam kondisi kediktatoran: orang-orang di Rusia, orang-orang di Belarus".
Baca juga: Trump: Putin dan Zelenskyy perlu bertemu untuk perundingan damai
Polemik tentang diktator
Polemik pernyataan Trump tentang Zelenskyy itu membuat kata "diktator" menjadi terangkat kembali. Diktator dalam istilah ilmu politik adalah menggambarkan seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan mutlak atas suatu negara, dan kerap kekuasaan tersebut diraih melalui kekerasan, manipulasi, atau cara-cara yang secara etika tidak sah.
Seorang diktator diketahui tidak serta merta mengikuti hukum atau konstitusi negara dan memerintah dengan tangan besi. Hal ini biasanya dikaitkan dengan kurangnya kebebasan politik, pemerintahan yang bersifat personalistik (atau sangat bergantung kepada sosok diri dari sang pemimpin), dan seringkali memegang kekuasaan dengan cara-cara ala militeristik.
Diktator itu sendiri dapat dikaitkan dengan otoritarianisme, yaitu sebuah paham politik yang membatasi kebebasan individu serta menempatkan kekuasaan terpusat di satu otoritas atau sekelompok kecil elite oligarki. Dalam sistem otoritarianisme, pemerintah biasanya memiliki kendali yang signifikan atas banyak aspek kehidupan, termasuk media, ekonomi, dan ekspresi politik, sekaligus membatasi oposisi politik atau perbedaan pendapat publik.
Hal yang patut dicemaskan juga adalah kediktatoran atau otoritarianisme sebenarnya bukanlah seperti dongeng di masa lalu, tetapi paham yang berbahaya ini dinilai sedang mengalami peningkatan terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, saat ini terdapat tren otoritarianisme yang semakin meningkat dibandingkan dengan akhir abad ke-20.
Munculnya politik yang dipimpin oleh seorang yang memiliki pencitraan "orang kuat", penindasan terhadap perbedaan pendapat, pembatasan kebebasan media, dan melemahnya independensi peradilan semakin sering terjadi baik di negara-negara Barat maupun non-Barat. Sebaliknya, pada 1990-an dan awal 2000-an terdapat optimisme yang lebih besar terhadap penyebaran demokrasi secara global.
Menurut laporan dari organisasi seperti Freedom House, demokrasi telah mengalami kemunduran secara global selama lebih dari satu dekade, dengan negara-negara otoriter memperluas pengaruh mereka dan menantang norma-norma demokrasi. Laporan Freedom in the World tahun 2021 menunjukkan bahwa demokrasi telah mengalami kemunduran selama 15 tahun berturut-turut, antara lain karena pandemi, meningkatnya populisme, dan melemahnya lembaga-lembaga demokrasi.
Tentu akan mudah bila suatu gejala otoriter tersebut dapat dideteksi sejak awal atau sebelum berkembang pesat. Masalahnya apakah ada perangkat yang bisa menilai apakah seseorang itu termasuk ke dalam mereka yang cenderung menyetujui sejumlah praktek yang kerap dilakukan di dalam lingkungan otoritarianisme?
Baca juga: Laporan: Zelenskyy semakin kehilangan dukungan AS dan Trump
Baca juga: Bekukan dana ke luar negeri, Trump bela keputusannya
Mengukur otoritarianisme
Sebenarnya ada beberapa perangkat yang digunakan oleh para peneliti dan psikolog untuk mengukur otoritarianisme dalam perilaku dan sikap individu. Alat-alat ini bertujuan untuk menilai kecenderungan seseorang terhadap nilai-nilai otoriter, yang dapat mencakup kepatuhan terhadap otoritas, kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat, serta preferensi terhadap ketertiban dibandingkan kebebasan.
Salah satu alat tersebut adalah tes kepribadian F-scale yang dirancang pada 1947 oleh filsuf Jerman Theodor W Adorno dan beberapa rekan peneliti lainnya. F-scale (F merupakan kependekan dari Fasis) merupakan salah satu upaya pertama untuk mengukur otoritarianisme pada individu, atau tepatnya mengukur kecenderungan seseorang terhadap prasangka, pemikiran kaku, dan kepatuhan terhadap norma-norma tradisional, yang merupakan karakteristik yang terkait dengan kepribadian otoriter.
Tes kepribadian ini mencakup butir pernyataan mengenai konvensionalisme, takhayul, dan sikap otoriter umum yang mencerminkan keinginan akan tatanan sosial yang ketat dan intoleransi terhadap perbedaan pendapat. Mereka yang mendapat nilai tinggi dalam skala ini cenderung memiliki gagasan yang kaku tentang tatanan sosial, bias yang kuat terhadap kelompok minoritas, dan lebih menyukai kepemimpinan otoriter.
Sejumlah contoh pernyataan dalam F-scale antara lain adalah "Seorang pria harus bisa mengungkapkan perasaannya secara terbuka, tetapi hanya dengan cara yang benar", "Saya takut pada orang asing yang tidak saya kenal", "Kekuasaan membuat yang benar, dan yang kuat mempunyai hak untuk mendominasi yang lemah", "Orang yang terlalu banyak bertanya itu menjengkelkan", serta "Hukuman seharusnya lebih keras bagi mereka yang menentang otoritas". Para responden harus menyatakan sikapnya antara sangat setuju hingga sangat tidak setuju.
Kritik terhadap F-scale adalah alat tersebut dinilai terlalu luas dalam penilaiannya serta tidak cukup membedakan antara kecenderungan otoriter dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Perangkat tes kepribadian lainnya yang serupa dengan F-scale adalah Right Wing Authoritarianism (RWA) Scale, yang dikembangkan oleh Profesor Psikologi berkebangsaan Kanada, Bob Altemeyer, pada 1981.
RWA itu sendiri memiliki tiga komponen inti, yaitu kecenderungan mengikuti otoritas, mendukung agresi terhadap kelompok luar atau sesuatu ancaman, serta dukungan terhadap norma-norma masyarakat tradisional. Ketiga kategori ini membantu menilai kepribadian otoriter individu secara keseluruhan sehingga semakin tinggi skor dalam RWA yang dimiliki seseorang biasanya berkorelasi dengan kecenderungan otoriter yang lebih tinggi.
Sejumlah contoh butir pernyataan yang terdapat dalam RWA Scale antara lain adalah "Pihak berwenang harus dipatuhi, meskipun mereka salah", "Tidak ada yang salah dengan seorang pemimpin yang memerintah dengan kekerasan jika diperlukan", serta "Cara-cara kuno dan nilai-nilai kuno masih menunjukkan cara hidup yang terbaik". Seperti F-scale, responden harus menyatakan sikapnya terkait berbagai pernyataan tersebut.
Adapun tes kepribadian yang paling mutakhir dapat disebut Political Psychology of Authoritarianism (PPA) Questionnaire, yang dikembangkan oleh berbagai sarjana psikologi politik di sejumlah negara. Kuesioner ini meminta responden untuk menilai persetujuan mereka terhadap pernyataan tentang perlunya kepemimpinan yang kuat, keinginan untuk stabilitas sosial, dan keyakinan bahwa kelompok tertentu (misalnya etnis minoritas, imigran) mengancam tatanan sosial yang ada selama ini.
Sejumlah butir pernyataan dalam kuesioner tersebut antara lain adalah "Demokrasi berjalan dengan baik secara teori, tetapi pemimpin yang kuat akan lebih praktis", "Negara akan jauh lebih baik jika masyarakat mengikuti aturan tanpa mempertanyakannya", "Orang asing membawa masalah pada masyarakat kita, dan kita perlu membatasi imigrasi", "Kita tidak boleh meminta maaf atas tindakan negara kita di panggung global", serta "Terkadang lebih baik memiliki pemerintahan yang dapat mengambil tindakan cepat tanpa terhambat oleh proses demokrasi". Lagi-lagi, responden harus menyatakan sikapnya terkait beragam pernyataan itu.
Berbagai tes kepribadian tersebut berupaya membantu menangkap sikap dalam seorang individu untuk memegang kendali, menjalankan norma-norma sosial yang kaku, serta permusuhan terhadap perbedaan pendapat, yang semuanya merupakan inti dari ideologi otoriter. Mungkin saja dengan memahami berbagai tes tersebut juga dapat membuat berbagai kalangan dapat memahami siapa saja pemimpin yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai "diktator".
Namun, meski otoritarianisme saat ini dinilai sedang meningkat di beberapa belahan dunia, harus diakui bahwa demokrasi saat ini masih dinilai sebagai cita-cita dan nilai ideal global pada tataran masyarakat kontemporer. Untuk itu, tantangan utama yang perlu dilihat adalah apakah negara-negara demokrasi dapat beradaptasi dan melakukan reformasi dalam mengatasi kecemasan sekaligus melindungi kebebasan hak asasi mendasar warganya.
Pertikaian antara demokrasi dan otoritarianisme kemungkinan akan semakin intensif di tahun-tahun mendatang, dan cara negara-negara merespons tekanan internal dan eksternal yang mereka hadapi akan menentukan masa depan politik mereka.
Diharapkan, ke depannya kata-kata seperti "diktator" dapat menjadi seperti kata usang yang tidak lagi sering terdengar, apalagi dilontarkan oleh seorang pemimpin suatu negara kepada pemimpin negara lainnya.
Baca juga: Menakar logika Trump atas solusi dua negara Palestina-Israel
Baca juga: Apa yang kau cari Donald Trump?
Copyright © ANTARA 2025