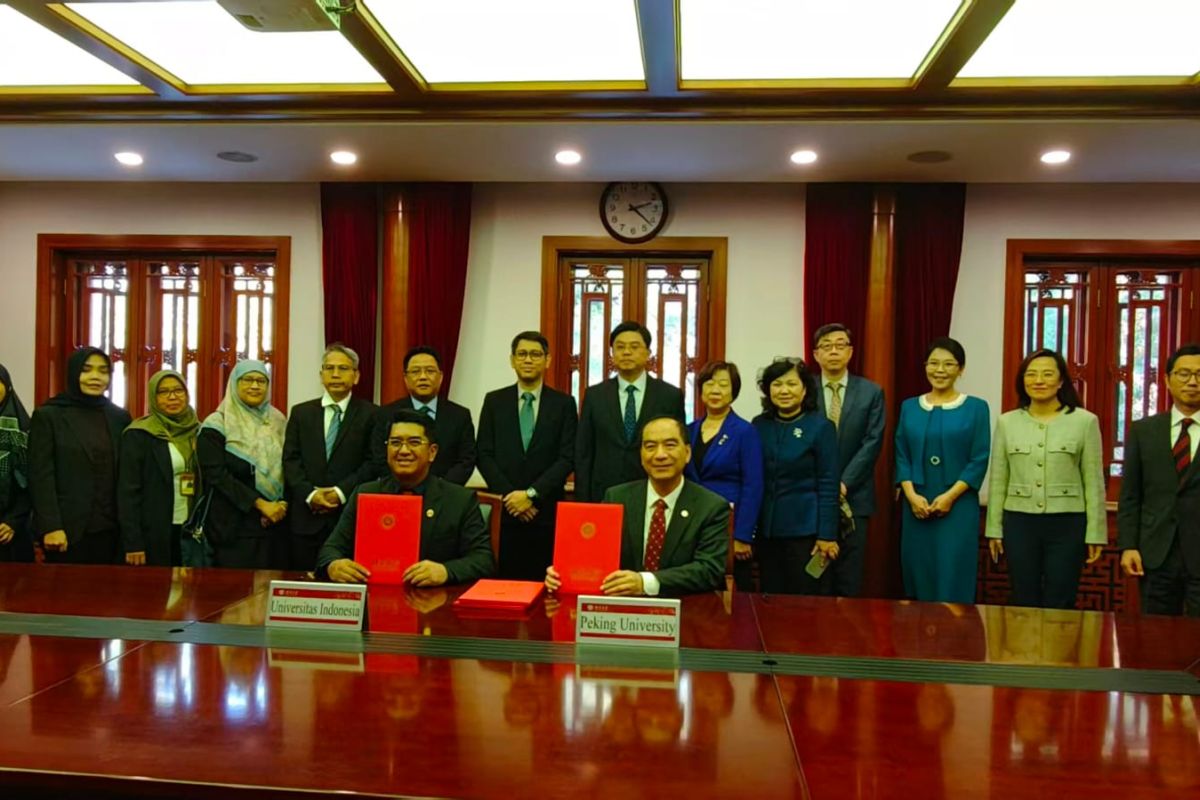Jakarta (ANTARA) - Sastra kini telah menjadi "senjata lunak" dalam arena persaingan kubu negara-negara. Di ruang simbolik ini, perang tidak lagi memakai peluru, melainkan paragraf.
Lewat buku, puisi, dan naskah, identitas sebagai negara Global Selatan pun berusaha ditegaskan. Di situlah politik dan estetika saling berpelukan.
Maka, hadirnya penghargaan sastra BRICS bukan pula sekadar acara seremonial. Ia adalah deklarasi kultural. Ia menyiratkan bahwa kisah tentang dunia tidak boleh hanya ditulis oleh Barat.
Selama berabad-abad, narasi global dikendalikan dari London, Paris, dan New York. Dunia Selatan hanya menjadi latar, bukan tokoh utama.
Kini, lewat ajang penghargaan sastra BRICS, negara-negara Global South mencoba membalik posisi. Penulis dari Brasil, India, Tiongkok, Rusia, Afrika Selatan, maupun Indonesia diberi panggung untuk menulis dunia dari arah Selatan.
Di sinilah relevansi pemikiran Antonio Gramsci menemukan nafas baru. Dalam teori hegemoni kultural, Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja lewat kekerasan atau ekonomi, tapi lewat kendali atas kesadaran dan nilai.
Barat selama ini mempertahankan dominasinya bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan makna. Sastra, film, dan media menjadi alat membentuk citra bahwa modernitas, rasionalitas, dan kemajuan adalah milik mereka.
Melawan hegemoni itu berarti merebut narasi, bukan sekadar merebut pasar. Negara-negara BRICS mencoba melakukan hal itu. Lewat diplomasi sastra, mereka memperjuangkan kebebasan simbolik. Mereka ingin menunjukkan bahwa kebijaksanaan, modernitas, dan nilai kemanusiaan juga lahir di Selatan.
Di tangan penulis Selatan, bahasa menjadi alat perlawanan. Cerita menjadi bentuk diplomasi. Imajinasi menjadi alat negosiasi global.
Kebangkitan sastra Global South ini tentu saja bukan kebetulan. Ia bagian dari gelombang besar, yakni dekolonisasi makna. Setelah sumber daya alam, kini nilai dan imajinasi ikut direbut kembali.
Negara-negara BRICS sadar, kekuatan sejati tidak hanya diukur dari cadangan devisa atau jumlah rudal. Ia juga diukur dari kemampuan menciptakan narasi yang dipercaya dunia. Narasi yang membuat orang percaya bahwa Selatan juga mampu memimpin arah sejarah.
Selama ini, jagad sastra memang selalu menjadi medan tarik-menarik kekuasaan. Dari kolonialisme hingga pascakolonialisme, sastra menjadi ruang legitimasi dan perlawanan.
Ketika Barat menulis tentang Selatan dengan cara menyepelekan, penulis Selatan membalas dengan cara menertawakan. Dalam setiap cerita, ada ideologi yang tersembunyi. Dalam setiap kalimat, ada perlawanan yang halus. Itulah kekuatan sastra sebagai alat politik yang senyap.
Sejauh ini, penghargaan sastra global dikuasai oleh lembaga Barat. Nobel, Booker, Pulitzer. Semua menetapkan standar universal yang berpihak pada estetika Eropa.
Bahasa dan nilai-nilai Selatan dianggap eksotis, bukan penting. Tema kemiskinan dan spiritualitas dipuji, tapi struktur berpikir Barat tetap dipertahankan. Nah, negara-negara BRICS ingin membalik tafsir itu, bahwa estetika tidak tunggal. Keindahan tidak harus lahir dari Eropa.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.