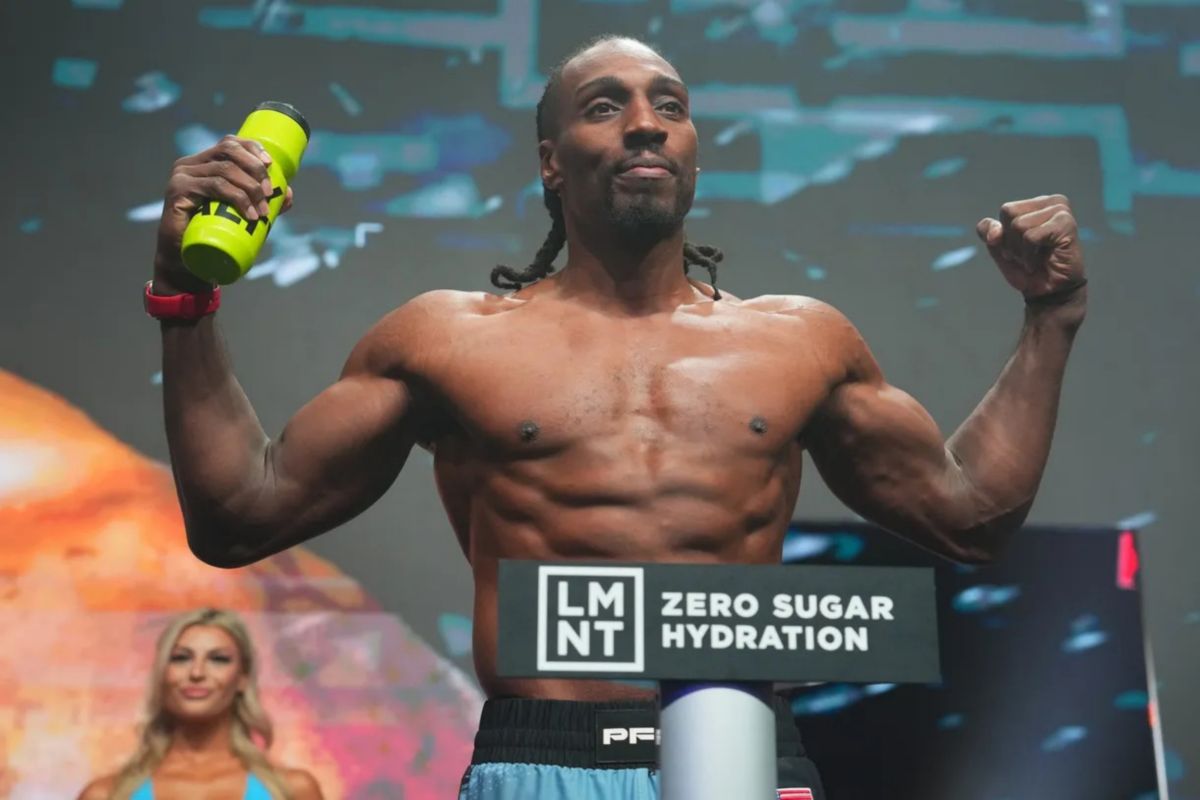Jakarta (ANTARA) - Sambil menyeruput kopi pagi, seorang sahabat berkata, “Jangan terlalu serius memperjuangkan idealisme. Di dunia nyata, idealisme sering kalah.”
Saya tersenyum, menimpali, “Mungkin itu benar, tapi dalam sejarah, semua perubahan peradaban dimulai oleh orang-orang yang militan memperjuangkan ide. Dan perubahan besar terjadi karena kemenangan idealisme.” Walau beda pandangan secara diametral, obrolan pagi itu diwarnai canda dan tawa lepas.
Rasanya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa perjuangan menjaga idealisme adalah keniscayaan zaman. Sepanjang garis waktu kehidupan, sejarah selalu memunculkan pribadi-pribadi terpilih yang setia dan terus berjuang untuk melahirkan kebaikan, melakukan perbaikan, dan terus mencari solusi atas berbagai masalah dan kerumitan yang dihadapi orang banyak.
Merekalah para public servants, pelayan publik, yang dari masa ke masa selalu memberi warna dalam setiap era, dengan idealismenya.
Ki Hajar Dewantara adalah salah satunya. Tokoh yang lahir pada 2 Mei 1889 ini, terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Kelak, hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Berlatar belakang keluarga bangsawan Kesultanan Yogyakarta, RM Soewardi kecil menikmati berbagai privilese. Ia belajar di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah dasar Belanda, lalu melanjutkan ke STOVIA, sekolah kedokteran pribumi di Batavia.
Namun, karena masalah kesehatan, ia tak menyelesaikan studinya. Kembali ke Yogyakarta, ia memilih jalur pena sebagai senjata. Sebagai jurnalis, tulisannya kritis dan tajam, lantang menentang ketidakadilan kolonial. Meski keluarganya dekat dengan pemerintah kolonial, ia tak pernah goyah dalam membela rakyat.
Pada 1913, ia menulis Als Ik Een Nederlander Was (Jika Saya Orang Belanda) dalam bahasa Belanda, sebuah sindiran pedas terhadap rencana pemerintah kolonial mengenakan pajak kepada pribumi untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis.
“Seandainya saya Belanda, saya tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang kami rampas kemerdekaannya,” tulisnya. Tulisan ini bukan sekadar protes, melainkan seruan moral yang mengguncang kesadaran publik. Tulisan itu juga telah membuat pemerintah kolonial ketar-ketir.
Ki Hajar memaknai kolonialisme bukan sekadar penjajahan fisik, tetapi juga merupakan model mental yang destruktif. Di dalamnya ada penindasan, kekejaman, ketidakadilan, pemerasan, sampai tekanan-tekanan kepada orang banyak yang didasari oleh motif sekadar unjuk kekuasaan.
Menurut budayawan Radhar Panca Dahana, inti kolonialisme adalah “rasa tidak pernah cukup,” lahir dari peradaban kontinental Eropa dengan empat musim ekstrem. Untuk bertahan di musim dingin, mereka terbiasa menimbun sumber daya, yang lama-kelamaan berubah menjadi keserakahan, mendorong mereka menjarah negeri lain, termasuk Nusantara.
Ki Hajar menentang mentalitas kolonial ini dengan pendidikan yang membebaskan. Baginya, melawan kolonialisme bukan hanya soal mengusir penjajah, tetapi juga membangun kesadaran rakyat agar tak terjebak dalam pola pikir serakah dan diskriminatif.
Perjuangan Ki Hajar tak berhenti pada kata-kata. Bersama Ernest Douwes Dekker dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, ia mendirikan Indische Partij pada 1912, partai politik pertama yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan Indonesia. Ketiganya, yang dikenal sebagai “tiga serangkai,” menjadi salah satu pelopor Kebangkitan Nasional.
Namun, idealisme mereka mengundang risiko. Karena sederet perlawanan lewat tulisan, aksi protes dan komite tandingan terhadap perayaan kemerdekaan Belanda, Ki Hajar ditangkap dan diasingkan. Mula-mula ke pulau Bangka, terus berlanjut ke negeri Belanda pada 1913.
Dasar pejuang, di pengasingan ia justru memperdalam wawasannya tentang pendidikan, yang kelak menjadi inti perjuangannya. Sekembalinya ke Indonesia pada 1919, Ki Hajar mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Taman Siswa bukan sekadar sekolah tapi gerakan yang bertujuan memberikan pendidikan setara bagi pribumi, yang selama ini terkungkung oleh sistem kolonial.
Filosofinya tercermin dalam semboyan ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani—di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Ini adalah pedoman kepemimpinan yang berpijak pada perilaku, bukan jabatan.
Sebagai ekspresi karakter dan perilaku, memimpin bisa dilakukan dimana saja: dengan atau tanpa jabatan; dan dari posisi manapun: baik di depan, di tengah, ataupun di belakang. Melalui konsep “pamong,” yang diterapkan di Taman Siswa, ia ingin menegaskan bahwa mendidik adalah memimpin, dan memimpin sejatinya adalah memberi teladan.
“Melawan kolonialisme tidak cukup dengan senjata, tetapi juga harus dengan kekuatan pikiran,” katanya. Baginya, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan alat pembebasan. Pendidikan berarti ikhtiar membangun budi pekerti, gagasan, dan keberanian rakyat untuk menuntut hak-haknya, sekaligus menanamkan sikap anti-kolonial yang menolak mentalitas eksploitatif.
Prinsip pendidikan ini selaras dengan Pedagogy of the Oppressed karya Paulo Freire (1968), yang mengusung pendidikan sebagai alat pembebasan melalui kesadaran kritis. Pikiran Ki Hajar melampaui zaman, merumuskan model serupa 46 tahun sebelumnya, yang khas Indonesia: berpijak pada budaya lokal, gotong royong, dan anti-feodalisme.
Pada usia 40 tahun, ia melepas gelar bangsawan Raden Mas dan mengadopsi nama Ki Hajar Dewantara. Langkah revolusioner ini menegaskan pendiriannya yang egaliter, menolak feodalisme dan nepotisme, meruntuhkan sekat kasta dan privilese; seraya menanam benih-benih meritokrasi.
“Mulai sekarang tidak ada lagi sebutan Raden, tidak ada lagi beda antara bangsawan atau orang biasa. Pamong laki-laki disebut Ki, yang perempuan dan sudah menikah disebut Nyi, dan yang masih belum menikah dipanggil dengan sebutan Ni”, tegasnya.
Ketika dipilih menjadi anggota Konstituante, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan pada 1951. Ia menolak konflik kepentingan, dan ingin memberi yang terbaik pada setiap peran yang dilakoninya.
Kepada anaknya ia pernah berkata, “Jangan risau kalau ada yang berpandangan negatif tentang ayahmu. Tapi kalau mereka bertanya siapa ayahmu, aku akan jawab: Aku adalah orang Indonesia, yang berbakti untuk Indonesia, dengan cara Indonesia. Aku akan berbuat yang terbaik bagi Indonesia, dan tidak akan mengambil satu sen pun yang bukan hakku.” Prinsip ini mencerminkan komitmennya pada kejujuran dan pelayanan publik.
Di hari Pendidikan Nasional 2025, yang ditandai oleh kelahiran Ki Hajar Dewantara, 136 tahun lalu, rasanya baik untuk merenung.
Pendidikan yang ia pilih sebagai jalan perjuangan telah membuahkan pembebasan. Tabiat dan tindak tanduknya untuk selalu menjaga nilai-nilai dan idealisme, telah menjadi pembuka jalan bagi terbentuknya Republik Indonesia, melalui perjuangan kemerdekaan.
Di tangan Ki Hajar, pendidikan bukan sekadar kurikulum, melainkan keberanian menegakkan nilai-nilai luhur dan menanamkan sikap anti-kolonial; anti pada keserakahan yang menzalimi rakyat.
Jalan idealisme Ki Hajar Dewantara tentu bukan jalan mudah, melainkan penuh liku, onak dan duri. Tetapi, jalan itu terbukti mampu membuahkan perubahan fundamental: dari gelap menjadi terang, dari inferior menjadi berani-percaya diri, dari sikap nrimo-pasrah menjadi perlawanan, dari tertindas menjadi terbebas, dari rakyat terjajah menjadi bangsa merdeka. Para pendidik dan kaum terpelajar harus terus mengobarkan semangat dan nilai-nilai Ki Hajar.
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Dirgahayu para pendidik, pewaris teladan Sang Pembebas.
*) Sudirman Said adalah Ketua Institut Harkat Negeri
Copyright © ANTARA 2025