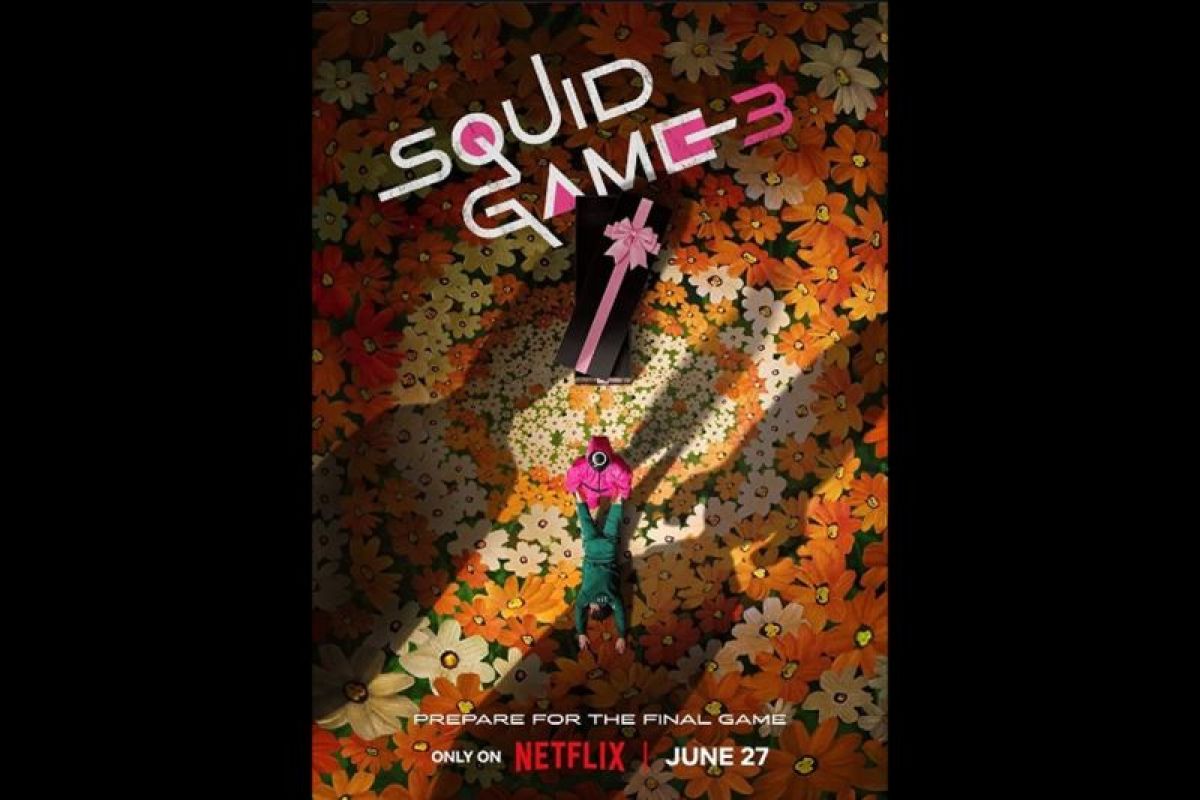Jakarta (ANTARA) - Indonesia adalah laboratorium bencana alam raksasa. Ditakdirkan terletak di atas pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, diapit oleh dua samudra, di kelilingi oleh lebih dari 100 gunung api aktif, menjadikan negeri ini "supermarket" yang memajang segala jenis ancaman, mulai dari gempa, tsunami, erupsi vulkanik, hingga banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran.
Namun, kondisi itu juga menjadikan Indonesia sebagai laboratorium hidup, tempat ribuan komunitas dengan budaya dan kerentanan lokal yang unik harus beradaptasi untuk bertahan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana alam tersebut.
Rentetan kejadian terus terjadi: banjir bandang di Bali yang terjadi di tengah musim kemarau; gempa di Sumenep, Banyuwangi, Bawean, Sumedang, dan Cianjur yang merusakkan ratusan bangunan; letusan Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT yang menghentikan kegiatan transportasi udara dan memicu pengungsian. Belum lagi potensi megathrust di barat Sumatera dan selatan Jawa yang mengingatkan perlunya kesiapsiagaan yang berkelanjutan.
Data menunjukkan bahwa ancaman ini bukan isapan jempol belaka. Sepanjang tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.107 kejadian bencana di Indonesia. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan 5.400 kejadian pada tahun 2023, dampak yang ditimbulkan tetap signifikan. Bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan cuaca ekstrem, masih mendominasi, dengan banjir saja mencapai 1.048 kejadian dari Januari hingga Juni 2025.
Sementara itu, jumlah korban jiwa akibat bencana di tahun 2024 bahkan mencapai sekitar 400 orang, meningkat dibandingkan tahun 2023. Statistik ini menegaskan bahwa, terlepas dari fluktuasi jumlah kejadian, kerentanan dan dampak bencana masih menjadi tantangan serius yang harus kita hadapi.
Pemerintah, dalam perannya, telah bekerja keras merumuskan dan membangun ketangguhan di tingkat nasional. Lahirlah berbagai kebijakan makro: BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aplikasi canggih seperti InaRISK, dan program-program ketangguhan berskala nasional, seperti DESTANA.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga telah menginisiasi berbagai kegiatan berbasis masyarakat yang patut diapresiasi, seperti Sekolah Lapang Gempa, Sekolah Lapang Iklim, dan Tsunami Ready Recognition Program. Implementasi program terakhir ini bahkan telah berhasil mendorong 22 desa mendapatkan pengakuan Tsunami-Ready dari UNESCO-IOC, sebuah capaian yang membanggakan.
Baca juga: BNPB dorong setiap daerah bentuk Forum PRB
Di balik capaian yang perlu diapresiasi itu, masih tersisa jurang menganga antara kebijakan dan realitas di lapangan. Aplikasi InaRISK bisa memberitahu kita bahwa rumah kita berada di zona merah, tetapi sudah mampukah kita mengetuk tetangga lansia agar terbantu melakukan evakuasi saat bencana terjadi? Peraturan pemerintah memang dapat menetapkan standar bangunan tahan gempa, tetapi bagaimana mengorganisir warga untuk membersihkan jalur evakuasi di tingkat RT?.
Program-program itu diharapkan menjadi solusi, tapi alih-alih menjadi potensi kegagalan sistemik yang muncul dalam bentuk ketergantungan pada solusi terpusat (top-down), abai kekuatan paling fundamental yang kita miliki, yaitu kekuatan komunitas terkecil.
Sudah saatnya kita membalik piramida, dari ketergantungan pada negara menjadi kemandirian komunal yang proaktif. Ketangguhan bukan sekadar aplikasi atau status administratif. Ketangguhan sejati lahir dari warga yang tahu harus berbuat apa, kapan, dan bersama siapa.
Kesiapsiagaan sejati adalah tentang memastikan upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berfungsi, terinternalisasi, dan menjadi budaya yang hidup dan terus-menerus diasah, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi perlu tumbuh pada mereka yang secara langsung berhadapan dengan potensi ancaman fisik.
Merasa aman karena programnya ada, peraturannya ada, aplikasinya bisa diunduh, justru membangun jebakan kesiapsiagaan yang maya.
Berbagai kajian global, secara konsisten, menunjukkan bahwa praktik terbaik untuk membangun resiliensi dan tata kelola pengurangan risiko bencana (PRB) yang efektif sangat bergantung pada konteks lokal. Pendekatan “one fits for all” seringkali tidak memadai dan bahkan justru dapat menghambat upaya PRB. Komunitas lokal adalah aktor kunci dalam merespons bencana. Mereka mengenal medan, memahami budaya, dan memiliki jaringan sosial yang bisa digerakkan secara cepat. Ketangguhan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal relasi dan pengetahuan lokal.
Kendati terdapat tantangan signifikan dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kerangka kerja PRB formal, kajian Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) menunjukkan bahwa komunitas yang telah hidup dengan bahaya alam selama beberapa generasi mampu mengembangkan metode yang efektif berbasis budaya lokal untuk persiapan dan merespon bencana dengan tepat. Pengetahuan ini seringkali sangat spesifik terhadap ekosistem dan budaya lokal, menjadikannya aset tak ternilai dalam menghadapi ancaman yang berulang.
Sejalan dengan itu, hasil riset Mwalwimba dkk. (2024) di beberapa desa di Afrika mengungkapkan bahwa respons masyarakat berbasis budaya lokal terhadap dampak perubahan iklim jauh lebih efektif. PRB berbasis budaya lokal juga mampu berperan menjadi dasar bagi pemecahan masalah kerentanan serta wahana pembelajaran terbaik bagi proses pewarisan pengetahuan antar generasi dalam menghadapi bencana yang sering keberulangannya melampaui satu generasi, misalnya tsunami.
Laporan Jingyan Wu dkk (2023) yang diterbitkan oleh the Society of Risk Analysis terkait dengan proyek PRB berbasis komunitas berskala besar di Tiongkok yang dimulai sejak 2007 dan melibatkan lebih dari 11000 orang, menggarisbawahi bahwa kontekstualisasi lokal tetap menjadi faktor penentu keberhasilan PRB.
Studi pustaka yang dilakukan oleh Tharic dkk. (2023) terhadap 516 dokumen yang relevan tentang kerangka kerja resiliensi komunitas yang diterapkan di tingkat lokal dalam berbagai konteks menyimpulkan bahwa resiliensi komunitas dalam perspektif kepentingan lokal lebih mudah dipahami dan meningkatkan keberterimaan.
Baca juga: PMI edukasi kesiapsiagaan bencana bagi siswa SLB pada Bulan PRB
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.