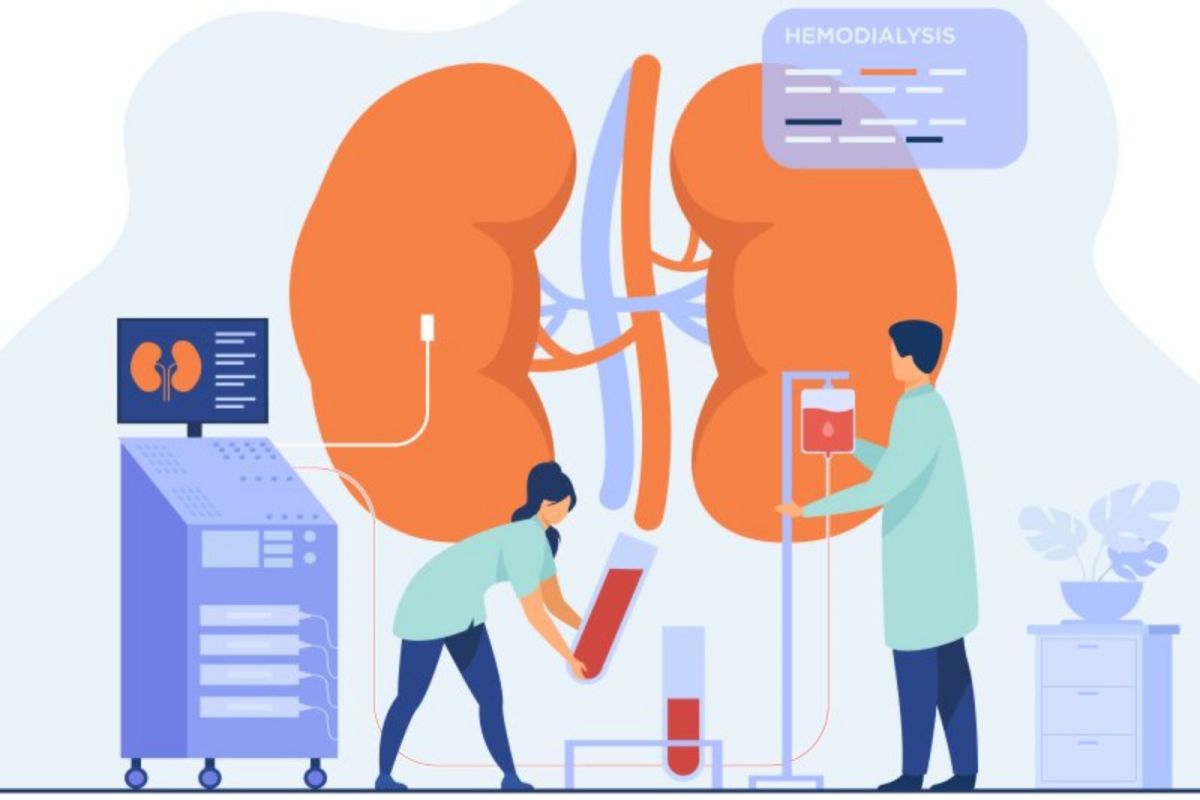Jakarta (ANTARA) - Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan potensi ekonominya dengan kebutuhan untuk menjaga sumberdaya alam.
Implementasi kebijakan mandatori B40 pada tahun 2025 menjadi salah satu langkah strategis yang mendukung kedaulatan energi nasional dan mencapai target net-zero emission. Namun, langkah ini tak lepas dari kritik dalam pengelolaan lingkungan yang dianggap belum optimal.
Diskursus tentang kelapa sawit terus berkembang, mencerminkan kompleksitas dalam mengelola komoditas strategis ini di tengah tuntutan keberlanjutan global.
Kelapa sawit telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dengan kebijakan B40, pemerintah menargetkan distribusi biodiesel hingga 16,08 juta kiloliter pada tahun 2025, yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Selain itu, perkebunan sawit membuka peluang investasi yang signifikan serta menciptakan lapangan kerja di pedesaan, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
Namun, keberhasilan ini perlu diimbangi dengan upaya pengelolaan yang baik untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Kelapa sawit memiliki keunggulan komparatif yang sulit disaingi oleh tanaman penghasil minyak lainnya.
Sebagai tanaman dengan produktivitas lahan yang tinggi, satu hektare sawit mampu menghasilkan minyak hingga 10 kali lebih banyak dibandingkan kedelai atau bunga matahari. Keunggulan ini menjadi modal besar bagi Indonesia untuk mendominasi pasar global.
Dengan dukungan regulasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), pemerintah terus mendorong penerapan praktik berkelanjutan oleh pelaku industri. Untuk itu, kebijakan terkait sawit perlu dirancang secara holistik, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Keberlanjutan sawit bukanlah persoalan yang dapat dilihat secara hitam-putih. Dengan kebijakan yang tepat, investasi dalam teknologi, dan edukasi bagi petani, Indonesia memiliki peluang besar untuk memaksimalkan manfaat ekonominya sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan
Konsekuensi ekologis
Guru Besar IPB Prof Yanto Santosa menyatakan bahwa isu deforestasi kerap digunakan sebagai alat propaganda untuk menghambat ekspansi sawit Indonesia di pasar global.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konversi hutan menjadi perkebunan sawit telah mengancam biodiversitas, mengurangi luas hutan tropis, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca, yang merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan.
Sebagai respon terhadap tantangan ini, pemerintah memperkuat kebijakan keberlanjutan dengan mewajibkan sertifikasi ISPO bagi seluruh petani dan pelaku industri mulai tahun 2025. Penerapan ISPO diharapkan mampu memperbaiki tata kelola lingkungan, memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, dan meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar internasional.
Selain itu, para pakar mendorong langkah mitigasi seperti reboisasi kawasan kritis dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai strategi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Para ahli juga menekankan pentingnya memprioritaskan perluasan lahan sawit di kawasan hutan terdegradasi daripada membuka lahan baru yang berisiko memicu deforestasi lebih lanjut. Pendekatan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan potensi produktivitas lahan tanpa mengorbankan keanekaragaman hayati.
Sementara itu, guru besar UGM Prof Priyono Suryanto menawarkan dua solusi inovatif untuk memperluas perkebunan sawit secara berkelanjutan.
Solusi pertama adalah revitalisasi agroforestri, yang mengintegrasikan tanaman pangan dan energi dalam satu lahan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani.
Solusi kedua adalah mengoptimalkan penggunaan lahan kritis, yaitu memanfaatkan lahan yang tidak produktif untuk budidaya sawit, sehingga dapat meningkatkan output tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan alami.
Selain aspek lingkungan, aspek hukum dan regulasi juga menjadi tantangan penting dalam investasi sawit.
Konflik lahan yang sering terjadi di sektor ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas dan tegas untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan. Dengan regulasi yang baik, risiko konflik lahan dapat diminimalkan, dan kepercayaan investor dapat ditingkatkan.
Pemerintah juga diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan ekonomi dan lingkungan untuk menciptakan sistem agribisnis yang berkelanjutan, di mana ekspansi sawit dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Sinergi Ekonomi dan Lingkungan
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam produksi sawit berkelanjutan. Hal tersebut memerlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, mencakup investasi teknologi, revitalisasi praktik agronomi, dan penguatan regulasi.
Dalam konteks global, sawit Indonesia menyumbang sekitar 58% dari total produksi dunia pada tahun 2023. Kontribusi ini menghasilkan devisa signifikan dengan nilai ekspor lebih dari 40 miliar dolar AS (setara Rp620 triliun).
Indonesia memiliki peluang strategis untuk memperkuat perannya dalam agenda keberlanjutan melalui inisiatif seperti sertifikasi ISPO dan standar internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Salah satu langkah inovatif yang dapat mendukung keberlanjutan adalah revitalisasi agroforestri. Pendekatan ini melibatkan integrasi kelapa sawit ke dalam sistem pertanian yang lebih beragam, seperti kombinasi dengan tanaman pangan, kayu, atau pohon bernilai ekonomi lainnya.
Strategi ini tidak hanya mengurangi risiko monokultur tetapi juga memperbaiki kesehatan tanah dan meningkatkan kapasitas penyerapan karbon.
Penelitian menunjukkan bahwa agroforestri sawit mampu meningkatkan produktivitas hingga 30% dibandingkan dengan monokultur, sekaligus mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 20%. Selain itu, sistem ini mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang.
Investasi dalam teknologi ramah lingkungan juga menjadi kunci untuk mengatasi tantangan keberlanjutan sawit.
Beberapa teknologi yang dapat diterapkan meliputi pemantauan berbasis satelit untuk mencegah deforestasi dan memonitor emisi gas rumah kaca. Juga pengolahan limbah sawit menjadi energi terbarukan melalui biomassa dan biogas, serta penerapan agronomi presisi yang memanfaatkan drone dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida.
Langkah-langkah itu memungkinkan industri sawit untuk tetap produktif tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Di sisi lain, sebagian besar petani kecil yang terlibat dalam industri sawit sering menghadapi kendala dalam menerapkan praktik berkelanjutan. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan bagi petani menjadi langkah penting. Program ini mencakup pengajaran tentang praktik agronomi berkelanjutan, pengelolaan lahan, dan pentingnya sertifikasi ISPO.
Namun, data terbaru menunjukkan bahwa baru sekitar 35% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO pada akhir tahun 2023. Angka ini menunjukkan perlunya upaya intensif untuk meningkatkan implementasi sertifikasi guna mencapai target net-zero emission pada tahun 2060.
Selain langkah domestik, kerja sama internasional juga menjadi elemen penting dalam mengatasi tantangan keberlanjutan.
Indonesia dapat memanfaatkan forum global seperti COP (Conference of the Parties) untuk memperjuangkan posisi sawit berkelanjutan dalam transisi energi global. Kebijakan seperti mandatori B40, yang mendukung kedaulatan energi nasional, sekaligus menjadi bukti komitmen Indonesia terhadap energi terbarukan.
*) Kuntoro Boga Andri adalah Kepala Pusat BSIP Perkebunan, Kementerian Pertanian
Baca juga: Apkasindo: Petani dukung gagasan presiden soal sawit
Copyright © ANTARA 2025