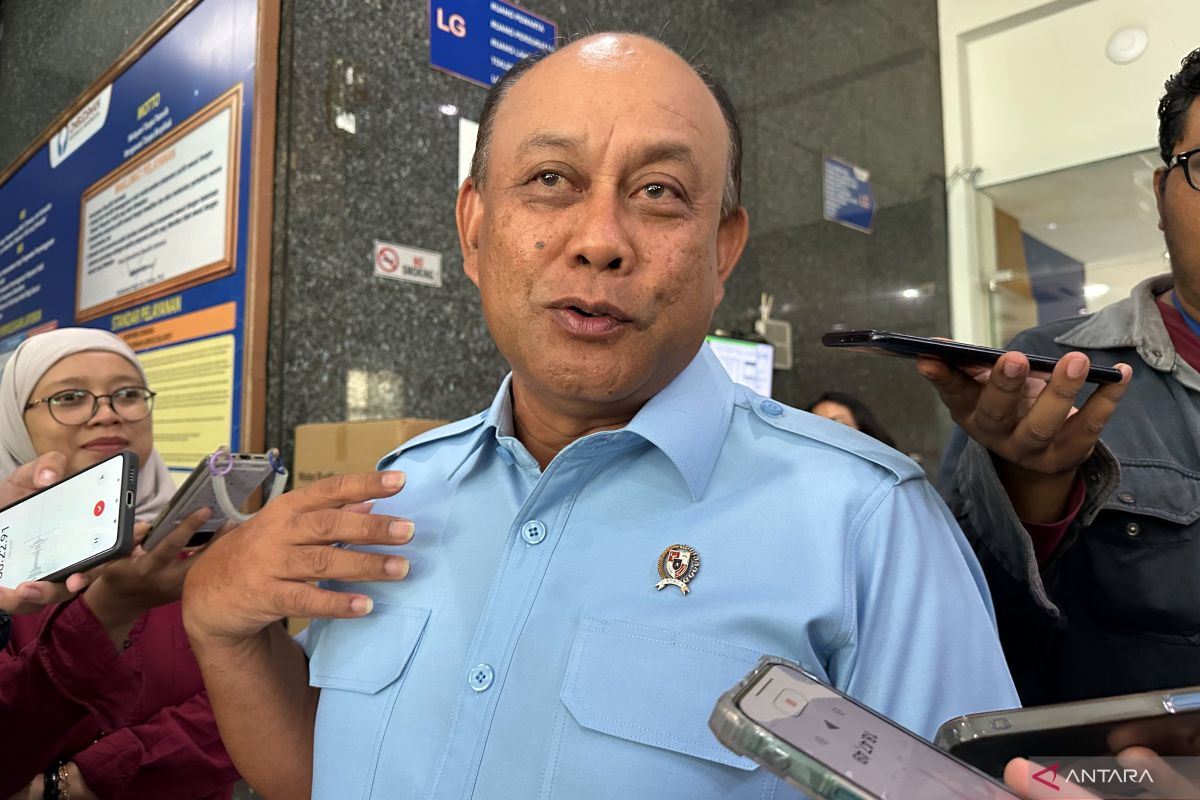Jakarta (ANTARA) - Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Padjadjaran Priguna Anugrah Pratama kembali membuka luka lama: kekerasan seksual di fasilitas pelayanan kesehatan.
Priguna kini ditahan Polda Jawa Barat atas dugaan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di RSUP Hasan Sadikin, Bandung. Selain korban berinisial FH, polisi telah memeriksa dua pasien lain yang diduga menjadi korban serupa.
Ini bukan insiden tunggal. Ini adalah puncak gunung es. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 menyebut 1.830 kasus kekerasan seksual di ranah publik, tiga di antaranya terjadi di fasilitas kesehatan. Namun angka ini kemungkinan jauh lebih kecil dari kenyataan, karena banyak korban memilih diam.
Ketakutan, trauma, dan budaya victim blaming yang mengakar kuat membuat penyintas enggan melapor. Para penyintas dituding menggoda, mencari perhatian, bahkan disalahkan karena pakaian yang dikenakan. Alih-alih mendapat perlindungan, penyintas justru kembali diserang.
Dalam iklim sosial seperti ini, dibutuhkan tekanan balik, gerakan yang tak menunggu legitimasi negara, tetapi tumbuh dari solidaritas dan keberanian untuk bersuara. Gerakan #MeToo membuktikan bahwa kekuatan itu bisa muncul dari pengalaman pribadi yang divalidasi bersama-sama.
#MeToo lahir dari pengalaman Tarana Burke di komunitas kulit hitam, dan meledak secara global setelah ajakan Alyssa Milano di media sosial tahun 2017. Jutaan orang di seluruh dunia kemudian membagikan cerita mereka sebagai penyintas kekerasan seksual.
Gerakan ini membongkar ilusi bahwa kekerasan seksual adalah peristiwa langka, memperlihatkan bahwa kekerasan seksual adalah peristiwa sistemik. Pelaku bukan hanya “orang asing” di gang sepi, tetapi juga orang terpandang, berkuasa, bahkan kolega terdekat.
Gerakan ini menjungkirbalikkan kenyamanan sosial yang selama ini membungkam kebenaran. Dalam konteks teori perubahan sosial, kita bisa memahami #MeToo lewat dua pendekatan penting: conversion theory dan divergent-convergent thinking model.
Baca juga: Hari Kartini, Puan ajak perempuan berani bersuara lawan kekerasan
Kacamata Conversion Theory
Menurut Serge Moscovici, perubahan sosial sering dimulai dari tekanan kelompok minoritas yang membawa opini berbeda dari arus utama. Pada awalnya, masyarakat meremehkan atau menolak #MeToo. Banyak yang mempertanyakan motif penyintas, mempertahankan status quo, dan berpegang pada norma yang selama ini permisif terhadap kekerasan.
Hadirnya #MeToo memicu pandangan yang berbeda dan mulai mengaktifkan proses validasi di masyarakat. Masyarakat kemudian mulai menilai dan mencoba untuk memahami bukti yang disampaikan oleh penyintas. Proses validasi ini membuat masyarakat lebih terbuka terhadap kekerasan seksual serta mengubah sikap terkait isu ini.
#MeToo tidak terlepas dari advokasi. Menurut genetic model of social influence dari Moscovici, kekuatan advokasi termanifestasi melalui perilaku yang ditandai dengan komitmen pada posisi yang diperjuangkan, otonomi dalam pengambilan keputusan, konsistensi dari waktu ke waktu dalam berbagai bentuk, serta keadilan dalam mengakui posisi orang lain.
Para penyintas konsisten berbicara terbuka tentang pengalaman kekerasan seksualnya meskipun menghadapi tantangan dan kemungkinan dampak negatif pada karier atau kehidupan pribadinya. Gerakan #MeToo juga mengedepankan otonomi individu dan mendorong penyintas untuk berbicara berdasarkan pengalaman pribadi tanpa merasa harus mengikuti standar atau batasan dari orang lain.
Gerakan #MeToo juga terus menunjukkan konsistensinya. Meskipun serangan balik dan pengabaian sering kali datang, banyak penyintas tetap konsisten dalam menyuarakan kebenaran sepanjang waktu. Gerakan ini juga meluas ke berbagai sektor dan mode komunikasi, termasuk media sosial, wawancara publik, dokumen hukum, dan diskusi masyarakat.
Para penyintas dan aktivis sadar bahwa tidak semua orang akan setuju atau memahami sepenuhnya pengalaman mereka. Namun, mereka tetap menuntut perlakuan adil dan kesempatan bagi setiap pihak untuk berbicara atau memberi pendapat. Hal ini menumbuhkan ruang aman untuk bersuara dan membuat gerakan ini menjadi masif.
Baca juga: Bantul tangani 65 kasus kekerasan pada anak dan perempuan pada 2025
Moscovici menekankan bahwa kelompok minoritas tidak boleh terlalu kaku dalam memperjuangkan sesuatu, dan gerakan #MeToo menunjukkan fleksibilitasnya. Meskipun tegas dalam menuntut perubahan, para penyintas dan aktivis sadar bahwa mereka harus terbuka dengan diskusi dan perubahan dalam memperjuangkan keadilan, sehingga tidak terlihat dogmatis.
Menantang cara berpikir lama
Perubahan pandangan pada kelompok mayoritas kemudian dapat dijelaskan dengan Divergent-Convergent Thought Model dari Charlan Nemeth, sebuah model yang menjelaskan bahwa tekanan dari mayoritas dan minoritas dapat mempengaruhi bagaimana orang berpikir, bukan hanya apa yang mereka pikirkan.
#MeToo dimulai sebagai gerakan yang mengguncang norma-norma sosial dan budaya yang telah lama membiarkan atau bahkan mengabaikan kekerasan seksual. Pada awalnya, mayoritas masyarakat mungkin merasa terkejut atau cemas dengan keberadaan gerakan ini, karena hal itu bertentangan dengan norma yang sudah ada.
Model convergent thinking Nemeth menggambarkan bagaimana tekanan mayoritas menyebabkan individu menyetujui pandangan mayoritas secara pasif untuk menghindari konflik. Namun, kesaksian penyintas dalam gerakan #MeToo mendorong divergent thinking, memicu masyarakat untuk mempertimbangkan perspektif baru, meragukan norma yang ada, dan membentuk opini yang lebih reflektif.
Dalam konteks #MeToo, ini berarti bahwa masyarakat yang terbiasa dengan budaya diam terhadap kekerasan seksual mulai mempertimbangkan sudut pandang yang lebih luas, seperti pemahaman tentang trauma, sistem kekuasaan yang melindungi pelaku, serta pentingnya mendengarkan dan mendukung penyintas.
Pengaruh minoritas tidak hanya membantu menghasilkan solusi yang orisinal, tetapi juga memicu pemikiran yang kompleks tentang berbagai pendekatan terhadap masalah yang ada. #MeToo berfungsi sebagai contoh bagaimana keberadaan gerakan minoritas ini memaksa masyarakat untuk melihat masalah kekerasan seksual dari perspektif yang lebih dalam.
Alih-alih hanya menerima narasi yang diterima secara umum, seperti "korban mungkin salah atau berlebihan”, #MeToo membuka ruang untuk memunculkan divergent thought, mendorong masyarakat untuk berpikir lebih kompleks mengenai perilaku predator, dampak kekerasan seksual, dan pentingnya perubahan dalam sistem hukum dan budaya yang lebih besar.
Poin penting dalam model Nemeth adalah bahwa pengaruh minoritas tidak bergantung pada kebenaran dari solusi yang diajukan, melainkan pada efek yang dihasilkan. Dalam kasus #MeToo, meskipun tidak mengajukan solusi yang sempurna, dampak positifnya adalah kemampuannya untuk mengintervensi kondisi sebelumnya dan membuka ruang untuk pemikiran baru.
Baca juga: Pakar: Institusi pendidikan harus giatkan pencegahan kekerasan seksual
Model ini juga menunjukkan pentingnya genuine dissent dalam memicu divergent thought. #MeToo, sebagai gerakan yang lahir dari pengalaman pribadi dan kekuatan narasi penyintas membawa genuine dissent. #MeToo adalah sebuah seruan nyata dari mereka yang tidak didengarkan, yang mendorong masyarakat untuk memikirkan kembali mengenai kekerasan seksual.
Gerakan yang Tak Selesai
#MeToo sebagai gerakan dari kelompok minoritas telah mengubah kebijakan di tempat kerja, industri hiburan, dan institusi pendidikan yang mulai memperketat aturan terkait pelecehan seksual dan memberikan lebih banyak dukungan untuk penyintas. Tokoh publik seperti Harvey Weinstein juga menghadapi konsekuensi hukum berkat gerakan ini.
Pada akhirnya, #MeToo bukan sekadar tren media sosial. Gerakan ini merupakan representasi dari perjuangan kolektif yang mendalam dan penuh risiko, yang membawa suara-suara yang selama ini dibungkam ke ruang publik. Gerakan ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari pengalaman individu yang divalidasi dalam solidaritas.
Jika perubahan sosial memang lambat dan tidak langsung seperti yang dijelaskan Moscovici dan Nemeth, maka kekuatan minoritas harus terus hadir sebagai pengganggu konsensus palsu. Dalam dunia yang terlalu sering membungkam kebenaran demi kenyamanan, suara penyintas mungkin adalah bentuk pembangkangan yang paling jujur dan paling radikal.
Kasus Priguna bukan sekadar potret individual tentang penyalahgunaan kuasa, melainkan cerminan kegagalan sistem untuk melindungi kelompok rentan. Dalam lanskap sosial yang cenderung pasif dengan kekerasan seksual, #MeToo adalah pengingat bahwa perubahan tak datang dari diam, melainkan dari keberanian untuk bersuara, meskipun itu datang dari luka.
Baca juga: Polda Jabar: PAP mengaku baru satu kali lakukan pemerkosaan di RSHS
*) Tuningsih Haryati adalah mahasiswa Magister Psikologi Sains Sosial Universitas Indonesia.
Copyright © ANTARA 2025