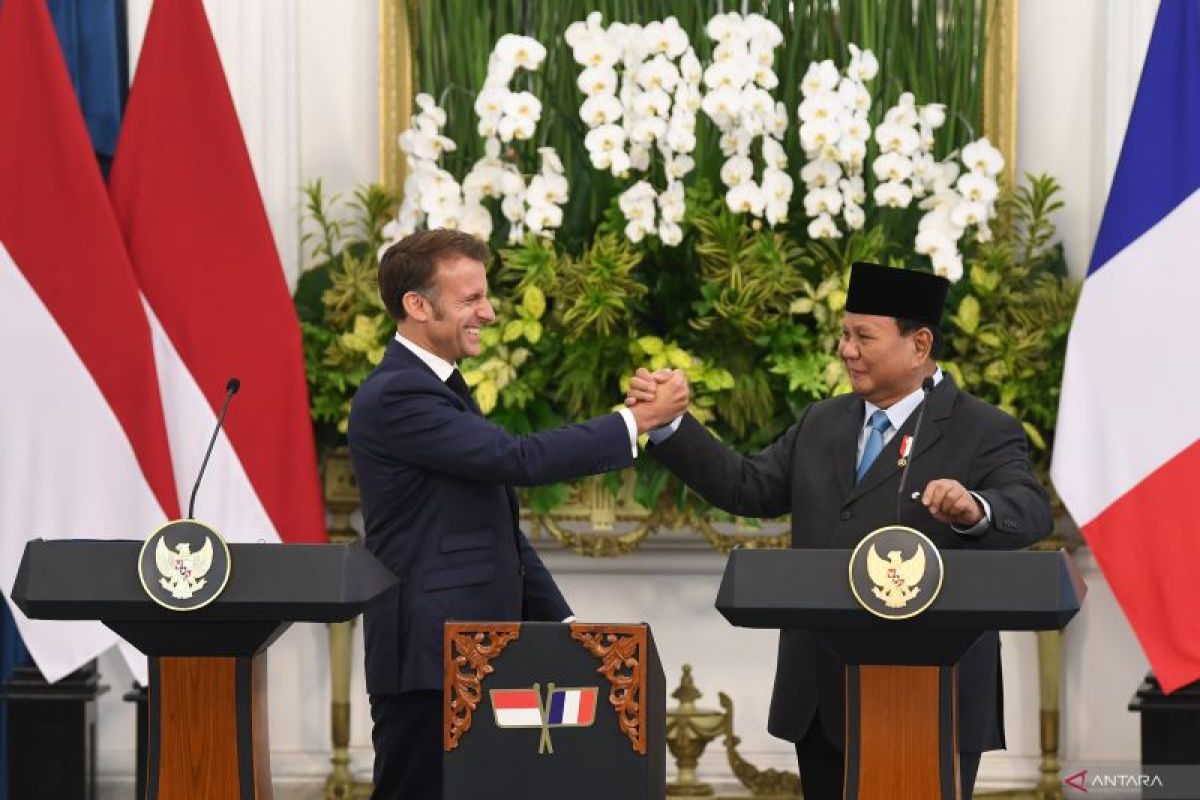Jakarta (ANTARA) - Pada 21 Agustus 2025, gempa berkekuatan 4,9 SR mengguncang wilayah Bekasi dan sekitarnya. Meski tergolong dangkal dan tidak menimbulkan korban jiwa, guncangannya terasa nyata di rumah-rumah, memicu kepanikan, dan sempat menghentikan layanan transportasi.
Hanya berselang 10 hari kemudian, gempa berkekuatan 6,0 SR melanda Afghanistan, menewaskan lebih dari 1.400 orang dan melukai ribuan lainnya.
Kedua peristiwa ini mengingatkan bahwa gempa datang tanpa peringatan. Dampaknya sangat bergantung pada kesiapsiagaan masyarakat serta kualitas infrastruktur.
Gempa bukan sekadar besaran angka magnitudo. Gempa wujud ujian terhadap sistem peringatan dini, respons kolektif, dan ketangguhan sosial.
Di Indonesia, ribuan gempa terjadi setiap tahun. Pertanyaan yang mendesak bukan lagi “apakah akan terjadi gempa?” melainkan “apakah kita siap saat gempa terjadi?”
Kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional (PUSGEN) mengidentifikasi lebih dari 295 sesar aktif di seluruh Indonesia, termasuk yang melintas di wilayah urban seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Dalam Webinar Talk to Scientists (4 April, 2024), BRIN menyatakan telah ditemukan lebih dari 100 sesar baru sehingga total patahan aktif di Indonesia menjadi 400 lebih. Temuan ini menegaskan bahwa ancaman gempa tidak hanya dari zona megathrust di laut, tetapi juga dari patahan darat yang dekat dengan permukiman. Sistem peringatan dini gempa semestinya mampu menjangkau skenario gempa lokal yang memiliki waktu respons jauh lebih pendek.
Bayangkan jika kita bisa tahu bahwa gempa bumi akan terjadi. Bukan setelah bangunan runtuh, tetapi beberapa detik sebelum guncangan terasa.
Ini bukan sekadar mimpi. Sistem ini sedang dikembangkan di Indonesia melalui kolaborasi penelitian internasional yang diluncurkan akhir Agustus lalu, melalui program pengembangan End-to-End Earthquake Early Warning and Response System (E2E-EEWRS).
Sistem yang dikembangkan, sejatinya bukan hal baru di dunia. Jepang misalnya, telah mengoperasikan sistem peringatan dini gempa sejak 2007 melalui Japan Meteorological Agency (JMA). Di Meksiko, sistem SASMEX telah menyelamatkan ribuan nyawa sejak diterapkan pada 1990-an.
Ketika gempa besar mengguncang Mexico City, sirine peringatan berbunyi hingga 60 detik sebelum guncangan utama tiba, memungkinkan evakuasi massal di sekolah dan gedung tinggi. Amerika Serikat juga mengembangkan sistem ShakeAlert di wilayah rawan gempa seperti California dan Oregon. Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi ponsel dan sistem transportasi, dan terus diperluas cakupannya.
Kini, Indonesia, merealisasikan langkah tersebut melalui Program Pengembangan E2E EEWRS SATREPS 2025 sd 2030.
Gempa adalah fenomena alam yang tak bisa dicegah. Ia terjadi karena pergerakan lempeng bumi yang berada jauh di bawah kendali manusia. Dampak kerusakan, korban jiwa, kepanikan massal tak terelakkan. Namun demikian, dampak itu bisa dikurangi, bahkan dicegah, jika tahu lebih awal dan harus berbuat apa.
Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan dua karakteristik fisik gelombang gempa. Pertama, Gelombang Primer (P-wave), karena kecepatannya tinggi (sekitar 6-8 km/detik), tiba lebih awal, dan tidak merusak. Yang kedua, Gelombang Sekunder (S-wave), merambat dengan kecepatan lebih lambat (sekitar 3-4 km/detik), namun merusak.
Selisih waktu antara kedua gelombang ini berkisar antara 5 hingga 30 detik, tergantung jarak dari pusat gempa, dikenal sebagai golden period. Periode waktu emas (golden period) inilah yang dimanfaatkan oleh sistem peringatan dini untuk mengirim sinyal peringatan dini ke masyarakat sebelum guncangan yang merusak tiba dan dirasakan dalam bentuk guncangan yang merusak.
Dalam hitungan detik, sistem memberi peringatan melalui sirine, aplikasi ponsel, atau sistem transportasi, mesin-mesin di pabrik, memberi kesempatan untuk bertindak.
Ketika sensor mendeteksi gelombang primer gempa (P-wave), sistem secara otomatis menangkap dan mengirimkan peringatan ke ponsel, televisi, kereta api, dan fasilitas publik lainnya. Informasi ini memberi waktu beberapa detik bagi masyarakat untuk berlindung atau menghentikan aktivitas yang berisiko tinggi, seperti kereta api cepat, lift, juga aktivitas dan mesin di pabrik-pabrik.
Inilah filosofi dasar sistem peringatan dini gempa bumi, yaitu memberi waktu, meski hanya beberapa detik, untuk menyelamatkan diri, menghentikan kereta, mematikan mesin, atau menjauh dari bangunan yang berisiko runtuh.
Kepala BMKG, dalam beberapa kesempatan, mengatakan: “Gempa tidak membunuh dan melukai. Justru, bangunanlah yang membunuh dan melukai manusia.” Pernyataan ini mengingatkan bahwa korban jiwa bukan semata akibat guncangan, melainkan akibat runtuhnya bangunan yang tidak tahan gempa. Sementara. respon manusia tidak siap. Ketidaktahuan, kepanikan, dan minimnya edukasi membuat dampak gempa jauh lebih besar dari seharusnya.
Oleh karenanya, penerapan Building Code yang ketat dan berbasis risiko menjadi sangat penting. Indonesia telah memiliki SNI untuk bangunan tahan gempa, yaitu SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan non-Gedung.
Namun, implementasinya masih belum merata, terutama di wilayah padat penduduk dan zona rawan. Sistem peringatan dini hanya efektif jika bangunan mampu memberi waktu dan ruang untuk evakuasi. Tanpa struktur yang dirancang untuk menahan guncangan, peringatan dini bisa menjadi informasi tanpa perlindungan.
Dengan demikian, secara prinsip terdapat dua hal yang sangat menentukan dampak gempa, terutama jumlah korban dan kerusakan.
Pertama, respon individu yang sadar dan terlatih. Peringatan dini hanya berguna jika individu tahu apa yang harus dilakukan. Berlindung di bawah meja, menjauh dari jendela, mematikan kompor, atau keluar dari bangunan jika memungkinkan, semua ini harus dilakukan secara refleks dan cepat.
Tanpa latihan dan edukasi, waktu emas bisa terbuang dalam kepanikan. Oleh karenanya keselamatan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kesiapan mental dan kebiasaan yang terbangun.
Kedua, perlindungan fisik dari infrastruktur yang tahan-gempa. Bangunan yang dirancang dengan prinsip tahan-gempa tidak hanya mencegah runtuhnya struktur, tetapi juga memberi “perlindungan ruang dan waktu” bagi individu di dalamnya.
Bahkan jika pun bangunan mengalami kerusakan, desain yang baik memungkinkan struktur tetap berdiri cukup lama untuk memungkinkan evakuasi. Gempa tidak membunuh, tetapi bangunan yang runtuh dan perilaku yang tidak siap berkontribusi besar terhadap jumlah korban jiwa.
Hulu hingga hilir
Pada sisi hulu, sistem terdiri dari peralatan padat teknologi, seperti sensor seismik dan algoritma cerdas mendeteksi gempa. Proses di hulu ini dimulai dengan monitoring gelombang primer (P-wave). Sensor seismik yang tersebar di berbagai lokasi akan menangkap rambatan P-wave ini dalam hitungan detik setelah gempa terjadi. Begitu P-wave terdeteksi, algoritma cerdas segera menghitung besaran gempa (magnitudo) dan memperkirakan lokasi pusat gempa.
Teknologi terkini, termasuk pemrosesan berbasis AI dan metode seperti PLUM (Propagation of Local Undamped Motion), memungkinkan estimasi intensitas guncangan secara real-time, cepat dan akurat, tanpa harus menunggu data lengkap. Selanjutnya, sistem akan memetakan wilayah yang diperkirakan akan dilewati oleh gelombang sekunder (S-wave), gelombang yang lebih lambat namun sangat merusak.
Berdasarkan jarak dan kecepatan rambat gelombang, sistem juga memprakirakan berapa lama waktu yang masih tersedia sebelum guncangan terasa di setiap lokasi. Informasi inilah yang dikirim ke masyarakat melalui berbagai kanal: sirine, aplikasi ponsel, sistem transportasi, dan bahkan integrasi dengan infrastruktur industri.
Di sinilah bagian hilir mulai bekerja, memberi waktu untuk berlindung, menghentikan kereta, mematikan mesin di pabrik, atau memberikan sinyal awal bagi individu untuk menjauh dari bangunan yang berisiko runtuh. Karena gempa tidak bisa diprediksi – paling tidak dari sisi kemampuan teknologi yang tersedia saat ini – penguatan pada sisi hilir perlu dilakukan. Ini bisa mencakup, antara lain: kesiapsiagaan, mengurangi kepanikan, dan pelatihan respon yang tepat dan cepat. Pada sisi fisik bangunan, perlu segera penerapan persyaratan bangunan tahan-gempa (building code, SNI).
Selain teknologi dan edukasi, daya dukung alam seperti jenis tanah, topografi, dan tata ruang berperan besar dalam menentukan dampak gempa. Wilayah dengan tanah lunak cenderung memperkuat guncangan, sementara pemukiman di lereng atau dekat patahan aktif memiliki risiko longsor dan keruntuhan struktur. Oleh karena itu, sistem ini kelak perlu diintegrasikan dengan kebijakan tata ruang dan pemetaan mikrozonasi. Dengan demikian, respons yang terbangun tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Mari bersiap bersama
Proyek ini merupakan riset kolaboratif Indonesia dan Jepang. Tim Riset Indonesia terdiri dari Konsorisum E2E EEWRS yang dikoordinasikan oleh BRIN. Terlibat BMKG, BNPB, BPBD, Pemda, dan Perusahaan swasta, serta beberapa perguruan tinggi nasional, baik negeri maupun swasta. Sedangkan mitra Jepang terdiri atas tujuh lembaga dan perguruan tinggi.
Dengan memahami cara kerja peringatan dini, mengikuti simulasi, dan mendukung kebijakan berbasis sains, kita telah berkontribusi menjadi bagian dari solusi. Sistem EEWRS mewahanai agar informasi gempa diterima sebelum guncangan merusak tiba.
Gempa bumi mungkin tak bisa dicegah. Tapi dampaknya bisa dikurangi, jika kita tahu, siap, dan bertindak tepat dan cepat.
*) Andi Eka Sakya adalah periset pada Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.