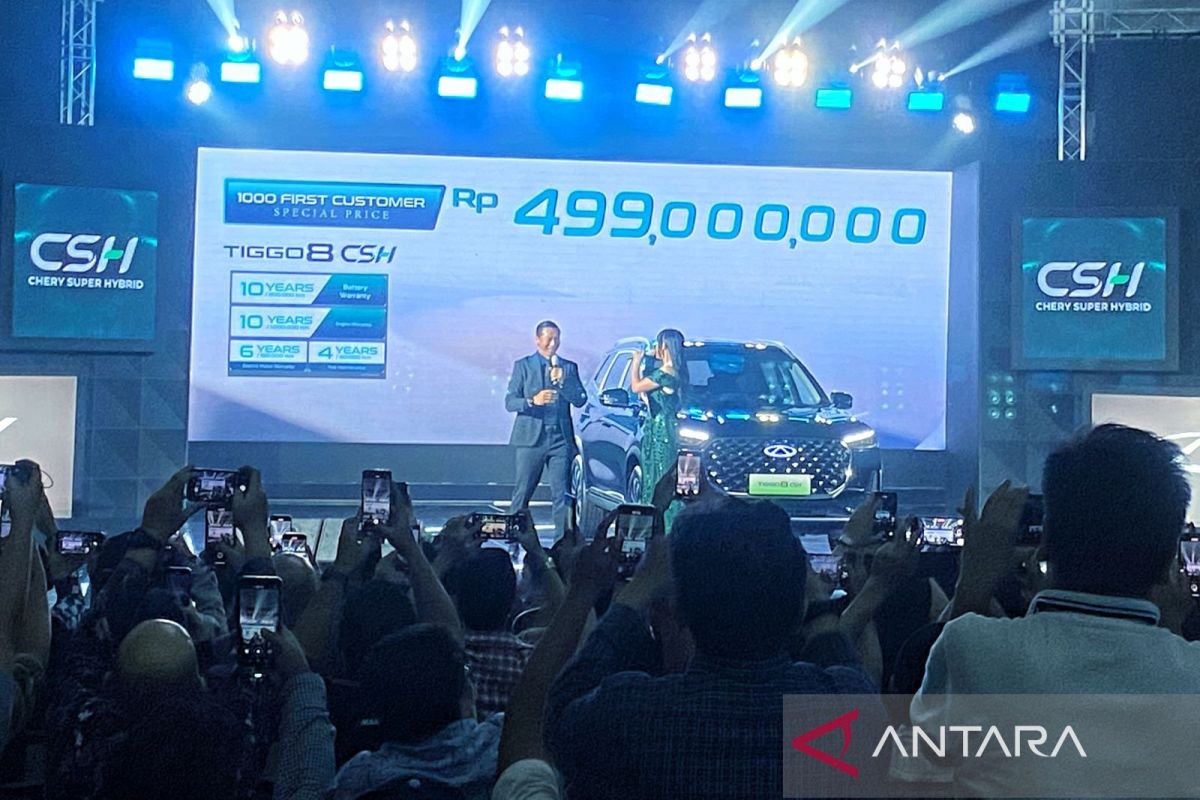Jakarta (ANTARA) - Dalam beberapa waktu terakhir, istilah "swasembada pangan" kembali ramai dibincangkan. Mulai dari Kepala Negara hingga Kepala Desa, tampak hangat membahasnya.
Apakah jika tidak dijadikan program prioritas Presiden Prabowo beserta Kabinet Merah Putihnya, masyarakat akan membahas swasembada pangan seintensif sekarang?
Padahal sebenarnya swasembada pangan bukanlah hal baru dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Swasembada pangan ibarat lagu lawas yang diputar ulang.
Ada yang suka dan ada yang tidak. Hal ini lumrah terjadi, karena beda generasi pasti beda selera. Generasi yang lahir di era 60-70-an tentu sangat berbeda dengan generasi milenial dan Z.
Sejak 20 tahun lalu, istilah swasembada pangan sudah jarang dibincangkan. Saat itu, orang-orang lebih senang bicara soal ketahanan pangan.
Swasembada pangan dinilai sudah selesai, dan di awal era reformasi, kita dihangatkan dengan kebijakan dan program pencapaian ketahanan pangan dan kemandirian pangan.
Dalam 10 tahun terakhir, isu pembangunan pangan di negeri ini mulai bergeser ke soal kedaulatan pangan. Sayangnya, baik ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan hingga kini masih belum dapat dibuktikan, mengingat syarat utamanya belum terpenuhi. Apa sebenarnya syarat utama tersebut?
Jujur kita akui, ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan akan dapat diwujudkan jika kita sudah mampu menggapai swasembada pangan.
Tanpa swasembada pangan, tidak akan ada ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Itu sebabnya, sudah cukup tepat jika Presiden Prabowo kembali mengangkat isu swasembada pangan.
Sejak Indonesia merdeka lebih dari 79 tahun lalu, belum pernah sekalipun bangsa ini meraih swasembada pangan.
Yang baru bisa kita capai adalah swasembada beras, itu pun sifatnya sementara. Artinya, kadang swasembada, kadang tidak, tergantung situasi dan kondisi. Padahal yang mesti kita kejar adalah swasembada beras berkelanjutan.
Swasembada pangan berbeda dengan swasembada beras. Swasembada pangan secara matematis adalah penjumlahan dari swasembada berbagai jenis bahan pangan yang strategis bagi kehidupan.
Sebut saja beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula pasir, bawang putih, dan lain sebagainya. Jenis-jenis bahan pangan tersebut masih kita impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Memaknai swasembada pangan seperti itu, sangat tidak realistis bila dalam tiga tahun ke depan kita ingin mencapainya.
Jangankan swasembada pangan, meraih kembali swasembada beras pun kini dihadapkan pada beragam tantangan yang cukup berat, terlebih jika ingin mewujudkan swasembada berkelanjutan.
Belum lagi swasembada kedelai, swasembada daging sapi, dan swasembada bawang putih, yang tanamannya hanya tumbuh baik di negara-negara sub-tropis.
Atas gambaran seperti ini, tentu akan lebih realistis jika tujuan utama diarahkan pada swasembada beras. Jadi, kalimatnya menjadi; “Pencapaian Swasembada Pangan, Utamanya Beras."
Kesimpulannya, swasembada pangan merupakan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya secara mandiri tanpa bergantung pada impor.
Fokus utamanya adalah pada peningkatan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, dan kedelai.
Dalam konsep ini, keberhasilan diukur dari sejauh mana negara mampu menyediakan pangan bagi penduduknya secara cukup dan berkelanjutan, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terjaga tanpa intervensi dari pasar internasional.
Kesejahteraan petani
Mengejar swasembada beras dalam tiga tahun ke depan tentu cukup realistis. Hanya saja, penting dicatat bahwa swasembada beras yang kita raih bukan hanya sekadar menggenjot produksi setinggi-tingginya, namun juga harus dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran para petani padi. Ini yang harus diwujudkan.
Semangatnya harus digeser menjadi "swasembada beras yang menyejahterakan petani padi".
Sangat memprihatinkan jika produksi beras melimpah, namun sebesar 47,94 persen, sebagaimana data Badan Pusat Statistik, dari kemiskinan ekstrem justru berasal dari sektor pertanian. Siapa lagi mereka itu, jika bukan petani gurem dan buruh tani.
Itu sebabnya, kita tentu sangat mendukung kebijakan pemerintah yang ingin membebaskan Perum Bulog dari statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara.
Ini penting, sebab Bulog sebagai lembaga parastatal seharusnya menjadi lembaga negara yang lebih memperhatikan kebutuhan dan tuntutan petani, bukan sekadar perusahaan pelat merah. Maka revitalisasi Bulog mutlak digarap.
Kata kunci swasembada pangan adalah produksi pangan yang berlimpah. Kata kunci kesejahteraan petani adalah peningkatan pendapatan petani.
Naiknya produksi pangan yang signifikan tidak otomatis mendongkrak kesejahteraan petani. Banyak faktor yang memengaruhi kesejahteraan petani, salah satunya adalah harga jual di tingkat petani.
Fakta di lapangan menunjukkan, petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga jual komoditas hasil panennya.
Bandar dan tengkulaklah yang paling menentukan harga. Pengalaman membuktikan, jarang ada bandar atau tengkulak yang mau berbagi keuntungan dengan petani. Mereka cenderung mengambil untung sebesar-besarnya.
Adanya kemauan politik pemerintah untuk menjadikan Bulog sebagai off-taker yang membeli gabah dan beras petani, dimaksudkan agar petani dapat menjual hasil panennya dengan harga yang wajar.
Bulog adalah sahabat sejati petani. Sebagai regulator pangan, Bulog diharapkan dapat memberi perlindungan dan pembelaan kepada para petani di seluruh pelosok negeri.
*) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.
Copyright © ANTARA 2025