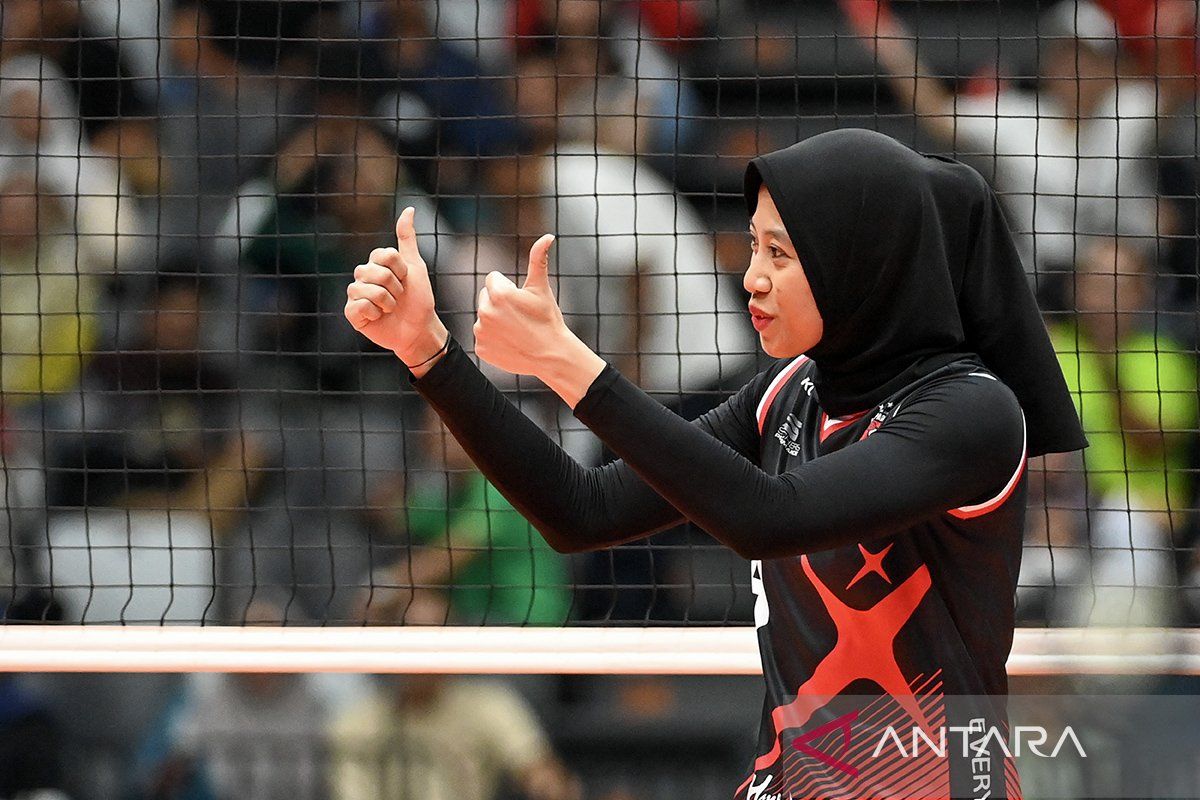Jakarta (ANTARA) - Shulamit Aloni, mantan Menteri Pendidikan Israel, dalam wawancara dengan Democracy Now (media berbasis di New York, AS) pada Agustus 2002 lampau, pernah menyatakan bahwa antisemitisme itu sebenarnya hanyalah sebuah trik atau tipuan.
Secara detail, pernyataan itu terungkap saat sang pewawancara bertanya bahwa "Kerap kali bila di AS ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan Israel, maka orang-orang itu akan disebut sebagai antisemit. Apa tanggapan Anda sebagai seorang warga Israel yang juga penganut Yahudi?"
Aloni menjawab bahwa "Well, (antisemit) itu adalah trik, dan kami selalu menggunakannya. Ketika dari Eropa ada yang mengkritik Israel, maka kami mengungkit tentang Holokaus (genosida terhadap orang Yahudi di Eropa pada Perang Dunia II)."
Dia melanjutkan bahwa "Ketika ada orang di negara ini (AS) yang mengkritik Israel, maka mereka adalah antisemit. Dan organisasi yang melakukan ini kuat, serta memiliki banyak uang, serta ikatan antara Israel dan lembaga Amerika Yahudi sangatlah kuat dan mereka sangat kuat pula di negara ini (AS)."
Antisemit atau antisemitisme kerap dimaknai sebagai bentuk prasangka, kebencian, atau diskriminasi terhadap orang Yahudi. Secara historis, hal ini telah menyebabkan beberapa peristiwa yang sangat mengerikan, seperti Holokaus pada Perang Dunia II.
Namun, sebenarnya Semit itu sendiri merupakan istilah teknis yang merujuk kepada rumpun keluarga bahasa yang mencakup bahasa Ibrani (bahasa orang Yahudi) serta bahasa Arab. Jadi secara teknis, bentuk prasangka dan kebencian serta diskriminasi terhadap Arab bisa saja disebut Antisemit.
Namun dalam media global saat ini, istilah Antisemit secara khusus telah dibiaskan hanya kepada orang Yahudi, dan bukan kelompok Semit lainnya.
Terkait dengan Antisemit, Pemerintahan Trump telah menuding bahwa beberapa universitas terkemuka di AS menyembunyikan gerakan antisemitisme, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas kampus yang mengkritik langkah yang telah dilakukan otoritas Israel.
Tudingan ini sebagian besar didasarkan pada Perintah Eksekutif 13899, yang ditandatangani pada Desember 2019, yang bertujuan untuk memerangi antisemitisme dengan memperluas interpretasi Titel VI Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964.
Meskipun Titel VI melarang diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, atau asal negara dalam program yang menerima bantuan keuangan federal, tidak secara eksplisit mencakup agama.
Perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Trump tersebut ternyata memperluas perlindungan kepada mahasiswa Yahudi dengan menafsirkan diskriminasi terhadap mereka sebagai pelanggaran Titel VI, bahkan ketika diskriminasi tersebut didasarkan pada agama, asalkan dikaitkan dengan asal negara atau ras.
Perintah tersebut juga mengadopsi definisi antisemitisme dari Aliansi Mengenang Holokaus Internasional (IHRA), yang mencakup bentuk-bentuk kritik tertentu terhadap Israel, seperti menolak hak orang Yahudi untuk menentukan nasib sendiri atau menerapkan standar ganda terhadap Israel.
Baca juga: Media: Mahasiswa asing diminta kembali ke AS sebelum pelantikan Trump
Melanggar kebebasan berpendapat
Pengkritik kebijakan tersebut berpendapat bahwa definisi yang luas dan "lentur" tersebut sebenarnya mencampuradukkan antisemitisme dengan wacana politik yang sah, dan berpotensi melanggar kebebasan untuk berpendapat yang diakui oleh hukum di Negeri Paman Sam.
Kebijakan Trump itu juga menjadi dasar untuk membungkam para aktivis yang bersuara dalam aksi unjuk rasa pro-Palestina. Beberapa mahasiswa secara langsung terdampak oleh kebijakan pemerintahan Trump yang menyasar aktivisme pro-Palestina di kampus-kampus AS.
Sejumlah kasus ternama antara lain adalah Momodou Taal, seorang mahasiswa pascasarjana di Universitas Cornell dan pemimpin protes berdarah Gambia-Inggris. Taal menghadapi skorsing pada April dan September 2024 karena keterlibatannya dalam protes kampus. Ia mengajukan gugatan terhadap pemerintahan, dengan tuduhan bahwa upaya untuk mendeportasinya melanggar hak Amandemen Pertama.
Kemudian ada nama Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa Universitas Columbia dan aktivis Palestina, yang ditangkap oleh agen ICE (Penegak Hukum Imigrasi dan Bea Cukai AS) pada Maret 2025 setelah kelompok pro-Israel melobi untuk deportasi tersebut.
Apalagi, Pemerintah AS sebelumnya telah mencabut dana federal sebesar 400 juta dolar AS (sekitar Rp6,92 triliun) bagi Columbia, dengan alasan kegagalan universitas untuk mengekang "antisemitisme" yang terkait aksi pro-Palestina.
Akibat tekanan tersebut, Universitas Columbia yang berpusat di New York telah mengeluarkan dan menangguhkan beberapa mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi pro-Palestina, termasuk dalam aksi pendudukan di Hamilton Hall kampus.
Aksi di Hamilton Hall terjadi pada April 2024, di mana Sekelompok demonstran antiperang memasuki gedung bersejarah Hamilton Hall di kampus pusat universitas tersebut pada April 2024, mengganti nama gedung tersebut menjadi "Hind's Hall," mengacu pada Hind Rajab, seorang gadis berusia 6 tahun yang dibunuh secara brutal oleh pasukan Israel.
Universitas Columbia dalam sebuah pernyataan pada 13 Maret 2025, menyatakan bahwa Dewan Yudisial universitas mengeluarkan sanksi mulai dari penangguhan selama beberapa tahun hingga pencabutan gelar sementara dan pengusiran sejumlah mahasiswa.
Di antara mereka yang dikeluarkan adalah Grant Miner, presiden Student Workers of Columbia, sebuah serikat yang mewakili instruktur dan peneliti.
Serikat tersebut mengecam keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa Miner dikeluarkan "tanpa bukti" atas partisipasinya dalam aktivisme solidaritas Palestina, yang merupakan tanggapan terhadap hubungan finansial Columbia dengan genosida Israel yang "didukung AS".
Masih dari Universitas Columbia, terdapat pula Mohsen Mahdawi, pemegang green card dari Palestina yang ditahan ICE pada April 2025. Penangkapan Mahdawi menyusul peningkatan pengawasan terhadap penanganan protes pro-Palestina oleh Columbia.
Selanjutnya, ada Rumeysa Ozturk, seorang mahasiswi PhD dari Turki di Universitas Tufts yang juga merupakan pegiat soal Palestina. Video penangkapannya pada Maret 2025 menjadi viral di dunia maya karena seperti tindakan penculikan paksa, yang memicu kemarahan secara luas.
Beberapa kasus ini menggambarkan penggunaan penegakan hukum federal oleh pemerintah AS untuk mengatasi aktivisme kampus, yang menimbulkan kekhawatiran secara signifikan di berbagai kalangan tentang kontroversi antara keamanan nasional, kebijakan imigrasi, dan kebebasan berpendapat.
Selain itu, kantor berita Anadolu juga memberitakan bahwa Pemerintahan Trump juga telah mencabut visa puluhan mahasiswa dari Universitas California, Los Angeles (UCLA), Berkeley, Stanford dan Columbia seiring dengan tindakan keras Amerika Serikat terhadap aktivis pro-Palestina.
Rektor UCLA Julio Frenk, sebagaimana dikutip Anadolu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Program Pertukaran Pelajar dan Pengunjung (Student and Exchange Visitor Program) telah mengakhiri status visa enam mahasiswa saat ini dan enam mantan mahasiswa yang terdaftar dalam program pelatihan karier.
Sedangkan University of California, Berkeley mengumumkan bahwa enam mahasiswa telah dicabut visa F-1-nya oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dan diperintahkan untuk meninggalkan negara itu pekan ini. Universitas Stanford menyatakan empat mahasiswa dan dua lulusan baru telah dicabut visanya.
Dalih yang dilakukan oleh Pemerintahan Trump melakukan pencabutan visa dengan mengutip undang-undang imigrasi yang mengizinkan deportasi karena "dampak buruk yang serius terhadap kebijakan luar negeri."
Padahal, para mahasiswa hanya berdemonstrasi dan menyuarakan pendapat mereka terhadap perang brutal Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 50.000 orang sejak 7 Oktober 2023.
Baca juga: AS cabut visa puluhan mahasiswa di tengah aksi bela Palestina
Tidak semua universitas
Namun, tidak semua mengikuti saja arahan pemerintahan Trump. Misalnya, Universitas Harvard menolak tuntutan untuk mengubah kebijakannya, yang menyebabkan pembekuan lebih dari 2,2 miliar dolar AS (sekitar Rp38 triliun) dalam bentuk hibah federal.
Institusi lain, seperti Princeton dan MIT, telah terlibat dalam negosiasi untuk menyeimbangkan persyaratan federal dengan nilai-nilai kelembagaan.
Dengan demikian, pemerintah AS menggunakan faktor pemanfaatan dana federal sebagai alat untuk menegakkan kepatuhan terhadap interpretasinya tentang antisemitisme sehingga universitas yang gagal mematuhi arahan pemerintah berisiko kehilangan dukungan dan akreditasi federal.
Pendekatan ini telah memicu perdebatan yang meluas tentang keseimbangan antara memerangi ujaran kebencian dan menjaga kebebasan akademik.
Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, juga telah mengecam taktik pemerintah sebagai tindakan yang melampaui batas yang mengancam independensi lembaga pendidikan.
Secara keseluruhan, dampak dari interpretasi "antisemitisme" untuk membungkam aksi pro-Palestina antara lain adalah menyamakan kritik terhadap Israel atau dukungan terhadap Palestina dengan antisemitisme, sehingga akan membungkam ekspresi politik, terutama dari komunitas yang terpinggirkan.
Apalagi, dalam beberapa kasus tampak adanya penargetan yang tidak proporsional, di mana mahasiswa pro-Palestina telah secara khusus terkena dampak, sehingga banyak yang mempertanyakan bahwa penerapan kebijakan Trump dilakukan secara bias, tidak adil, dan menimbulkan masalah hak asasi.
Sejumlah pendekatan alternatif yang lebih bijak yang dapat dilakukan sebenarnya bisa berupa penggunaan definisi antisemitisme yang lebih akurat, dengan fokus pada kebencian yang sebenarnya dan bukan mencakup kritik politik terhadap kebijakan Israel.
Untuk itu, dapat pula dibentuk badan pihak ketiga (nonpartisan) yang meninjau berbagai insiden kampus secara seksama untuk membuat rekomendasi, daripada memberlakukan perintah eksekutif secara top down.
Perlu pula adanya promosi dialog, lokakarya pendidikan, atau panel diskusi yang lebih mendorong pemahaman dibandingkan langsung kepada penerapan hukuman, serta adanya kepastian bahwa semua kelompok dilindungi secara setara berdasarkan hukum hak sipil yang berlaku, daripada memilih hanya satu kelompok dengan cara yang dapat memicu aksi kebencian.
Dengan kata lain, memerangi kebencian seperti di kawasan kampus adalah merupakan hal yang penting, tetapi cara melakukannya juga lebih esensial, yaitu harus dilakukan dengan cara yang adil dan menjunjung hak asasi manusia, bukan sekadar melakukan tindakan pencitraan politik atau penegakan hukum yang sewenang-wenang.
Baca juga: Kejahatan terhadap Muslim AS meningkat, CAIR suarakan kekhawatiran
Baca juga: Agensi bakat Hollywood pecat aktris pro Palestina
Copyright © ANTARA 2025