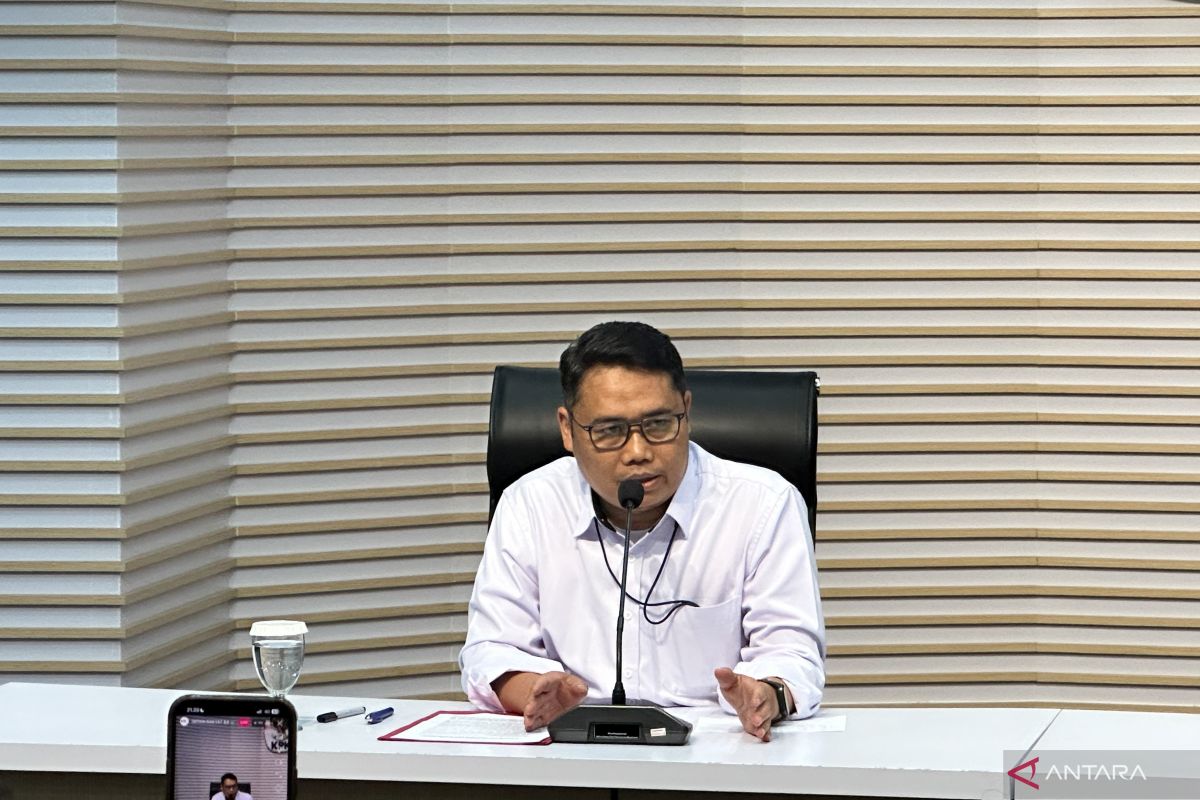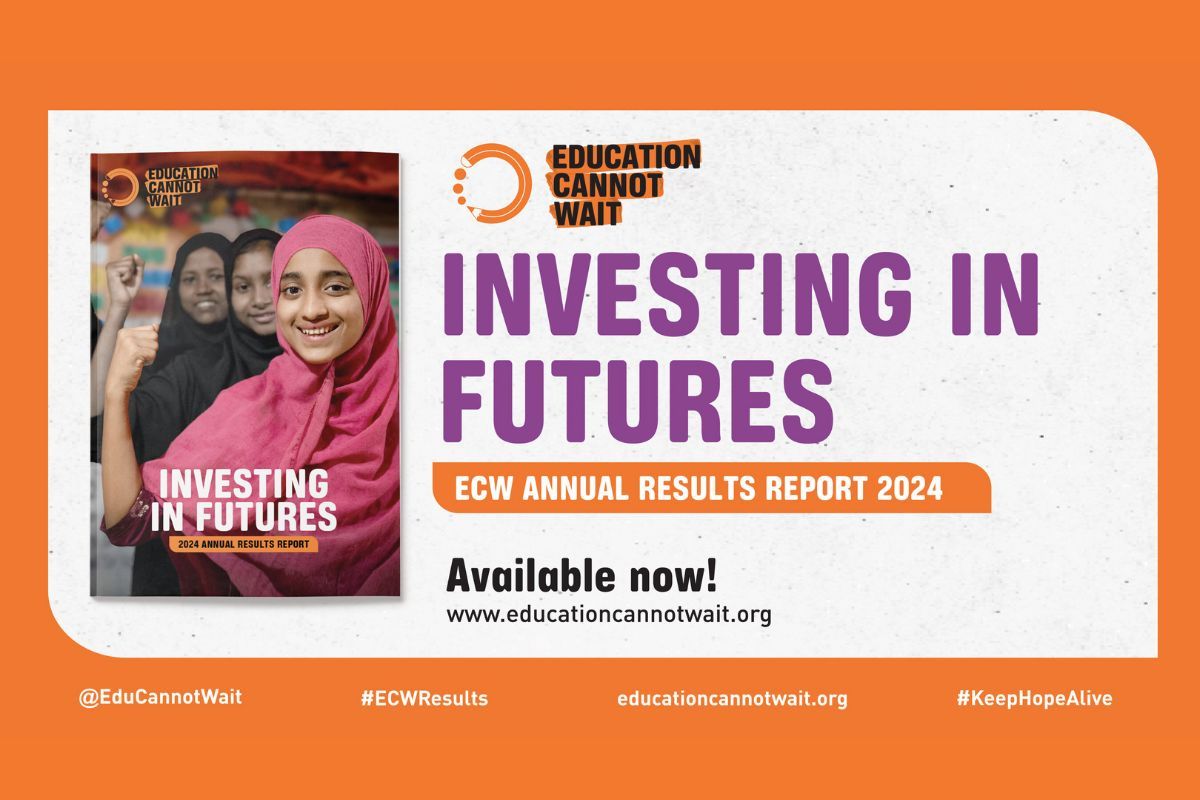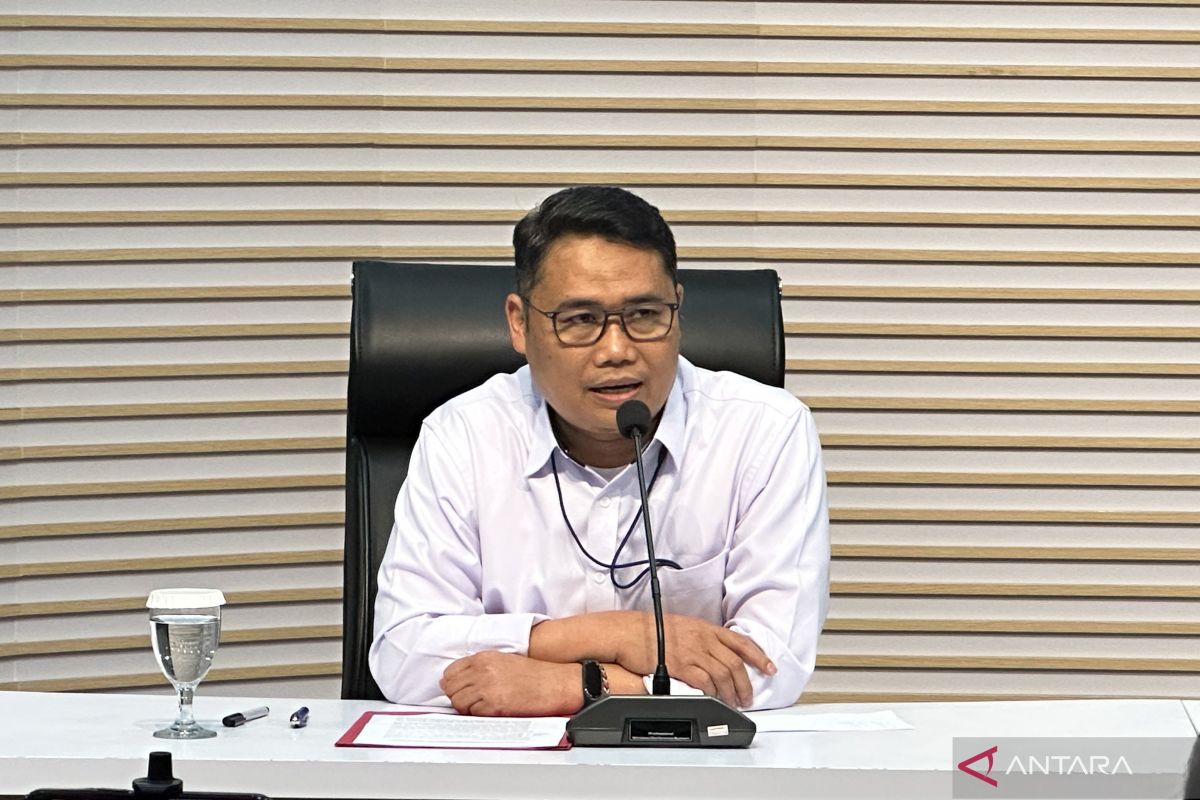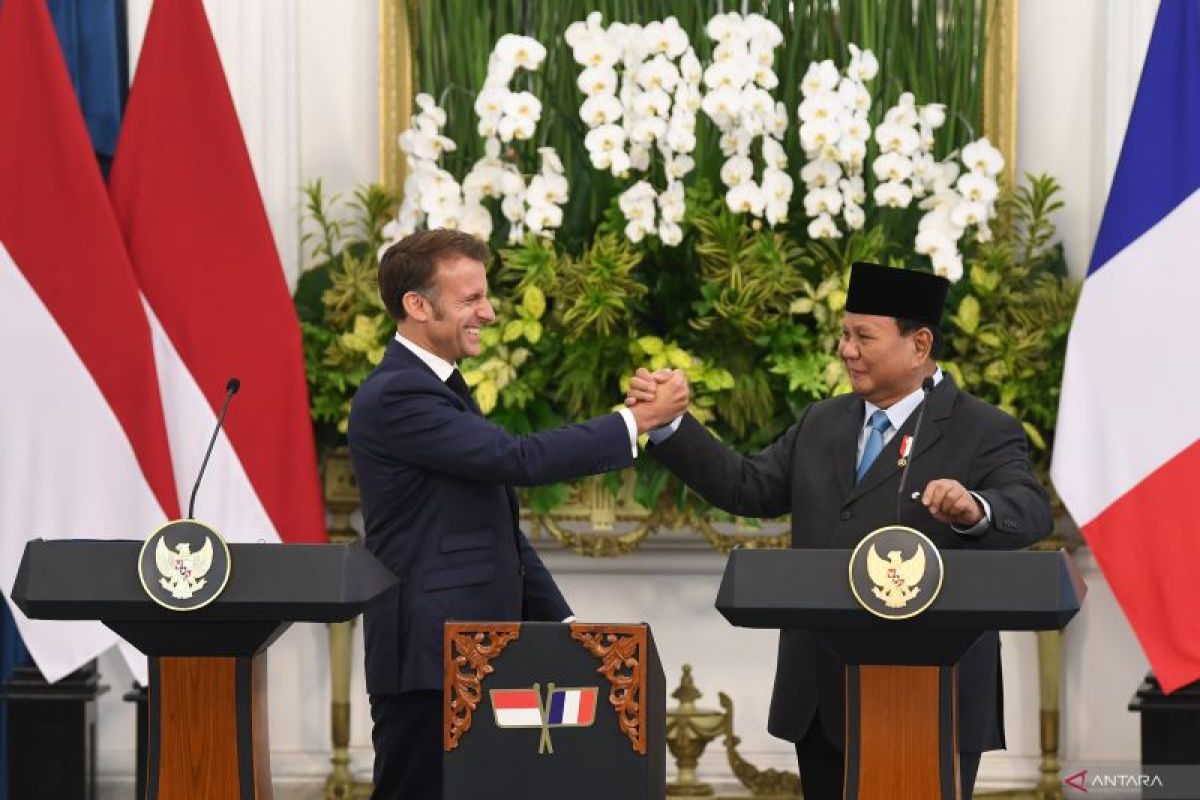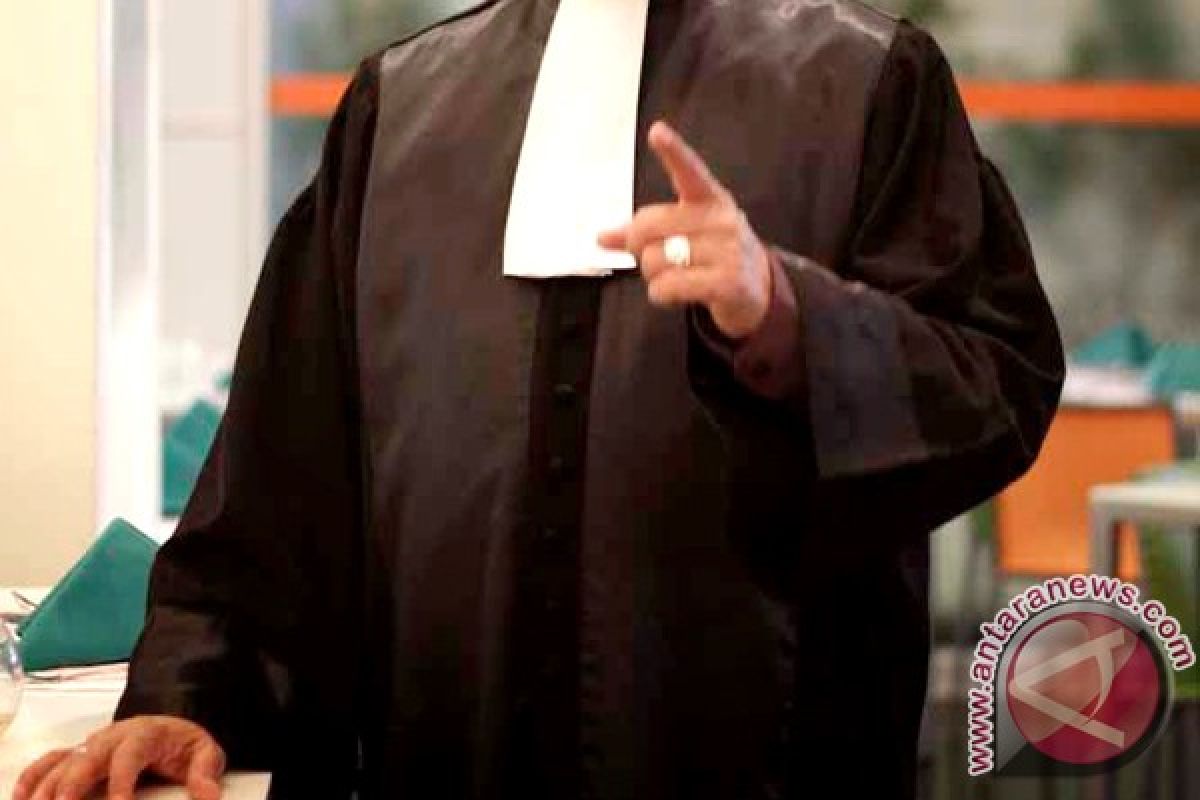Nairobi (ANTARA) - Menyadari keuntungan dari tanaman komersial, pemerintah kolonial Inggris memprioritaskan budi daya kopi.
Mereka mengidentifikasi dataran tinggi tengah, yang memiliki ciri khas tanah vulkanis subur, ketinggian antara 1.500 hingga 2.100 meter, dan iklim sedang, sebagai tempat ideal untuk perkebunan kopi Arabika, yang kemudian berujung pada komersialisasi budi daya kopi yang pesat di Kenya.
Tanah merupakan salah satu target utama perampasan kolonial. Pada 1902, pemerintah kolonial Inggris memberlakukan Undang-Undang Tanah Kerajaan (Crown Lands Ordinance), yang menyatakan bahwa semua lahan di dalam Protektorat Afrika Timur merupakan Tanah Kerajaan di bawah otoritas kerajaan Inggris.
Undang-undang itu mengizinkan penjualan atau penyewaan lahan hingga 1.000 ekar (sekitar 404,7 hektare) oleh pejabat berwenang, dengan jangka waktu penyewaan yang umumnya ditetapkan selama 99 tahun. Daerah yang paling subur, terutama dataran tinggi tengah di Kenya, ditetapkan sebagai "Dataran Tinggi Putih" dan diperuntukkan eksklusif bagi para pemukim Eropa.
Masyarakat pribumi, terutama masyarakat etnis Kikuyu dan Kalenjin, dipindahkan secara paksa dari tanah leluhur mereka dan direlokasi ke tempat yang kurang subur. Di bawah kebijakan kolonial yang ketat dan pajak yang memberatkan, banyak penduduk setempat yang tidak hanya kehilangan tanah mereka, tetapi, juga dipaksa untuk menjadi tenaga kerja dengan upah rendah di perkebunan milik para pemukim Eropa.
Kurator di Museum Enzi di Kenya Maina Kiarie mengatakan bahwa populasi pemukim Eropa di wilayah yang disebut sebagai "Dataran Tinggi Putih", termasuk Nanyuki, Nyahururu, dan daerah Uasin Gishu, berjumlah sekitar 100 orang pada 1903. Per 1950, angka tersebut melonjak menjadi lebih dari 80.000 orang.
Pada 1960, sekitar 2.000 pemukim Eropa masing-masing memiliki lahan pertanian lebih dari 2.000 ekar (sekitar 809 hektare), mencerminkan konsolidasi lahan yang ekstensif oleh pemukim Eropa selama periode kolonial.
Dalam "Out of Africa", Blixen merefleksikan eksploitasi yang dilakukan para pemilik tanah asal Eropa terhadap petani penggarap setempat.
Di lahan seluas 6.000 ekar (sekitar 2.428 hektare) miliknya, kurang lebih 1.000 ekar (sekitar 404,7 hektare) dibudidayakan oleh keluarga penggarap lahan. Para penggarap lahan, yang orang tuanya juga lahir dan dibesarkan di perkebunan tersebut, merupakan penduduk asli di lahan itu, namun, tidak memiliki hak kepemilikan atas lahan.
"Para penggarap lahan adalah penduduk asli, yang tinggal di lahan pertanian bersama keluarga mereka dan membudidayakan shamba kecil mereka di sana. Sebagai imbalannya, mereka harus bekerja untuk saya selama beberapa hari dalam setahun," Blixen menulis pada buku "Out of Africa".
Selama era kolonial, pemukim Eropa melarang penduduk asli Kenya untuk membudidayakan kopi, kata wakil ketua African Fine Coffees Association Karuga Macharia yang berbasis di Kenya.
"Mereka secara paksa dipindahkan dari tanah yang subur dan dipekerjakan sebagai buruh di perkebunan kopi milik pemukim, sering kali dalam kondisi yang eksploitatif," kata Macharia kepada Xinhua.
Industri kopi kolonial dirancang terutama untuk ekspor biji kopi mentah ke Eropa, di mana pemrosesan dan penjualan dilakukan sehingga masyarakat setempat hanya mendapatkan sedikit manfaat ekonomi meskipun tanaman tersebut ditanam di tanah mereka, ujar Macharia.
Sementara itu, direktur program di Fairtrade Africa Chris Oluoch menyoroti dampak kolonialisme yang berkepanjangan terhadap industri kopi Kenya.
Saat ini, produsen setempat di Kenya sering kali terpaksa terlibat dalam perdagangan kopi melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang berbasis di negara-negara Barat, ujar Oluoch.
Uganda, negara tetangga Kenya, menjadi protektorat Inggris pada akhir abad ke-19. Selama masa kolonial, otoritas Inggris secara aktif menggenjot budi daya teh, yang mendorong penduduk setempat untuk menjadikan teh sebagai minuman utama mereka.
Sementara itu, produksi kopi Uganda diarahkan hampir seluruhnya untuk ekspor. Pendekatan yang berorientasi ekspor itu berarti bahwa meskipun menjadi penghasil kopi utama, konsumsi domestik tetap minim.
Di Uganda, warisan kolonialisme Inggris terus memengaruhi persepsi tentang kopi. Sebuah merek kopi bernama "kiboko", yang berarti "kuda nil" dalam bahasa Swahili, juga merujuk pada cambuk yang secara tradisional dibuat dari kulit kuda nil.
Pada masa kolonial, para pengawas Inggris menggunakan cambuk tersebut untuk menerapkan kerja paksa di perkebunan kopi. Oleh karena itu, di kalangan masyarakat Uganda, kopi diasosiasikan dengan kerja paksa.
Konteks historis ini berkontribusi pada persepsi terhadap kopi sebagai "minuman orang kulit putih" di Uganda. Banyak penduduk setempat yang secara tradisional memandang kopi terutama sebagai tanaman komersial untuk diekspor, bukan sebagai minuman untuk konsumsi lokal.
Kemerdekaan dan perjuangan
Pada 1950-an dan 1960-an, Afrika menyaksikan lonjakan gerakan pembebasan nasional.
Pada 12 Desember 1963, Kenya mencapai kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris. Namun, kepergian para penjajah tidak meruntuhkan struktur ekonomi yang telah dibangun.
Kopi, yang diperkenalkan pada era kolonial sebagai salah satu komoditas tanaman komersial utama, menjadi pedang bermata dua dalam pembangunan ekonomi Kenya pascakemerdekaan.
Meskipun menghasilkan devisa, komoditas ini juga berkontribusi terhadap kerawanan pangan, kemiskinan di pedesaan, dan ketimpangan yang mengakar dalam rantai nilai pertanian.
(Bersambung ke Bagian 3)
Pewarta: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025